Esai
Intelektualitas bukan tentang diam dan kompromi. Esai kritis ini membongkar peran intelektual hari ini dalam melawan netralitas palsu, dogma ideologi, dan akademisasi kosong. Bacaan wajib bagi yang peduli pada perubahan sosial.
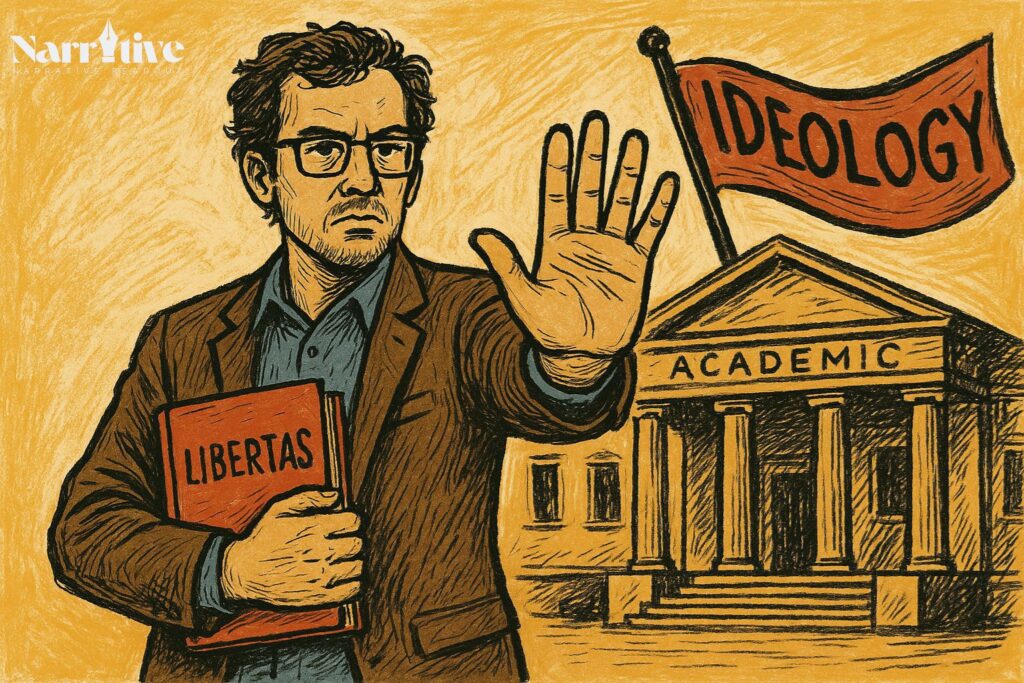
Intelektualitas Kritis: Melawan Netralitas Palsu dan Kultus Ideologi
“Intelektualitas bukanlah sikap mencari aman dengan pembiaran dan pemakluman terhadap segala sesuatu yang bersifat sewenang-wenang, tidak adil, dan manipulatif.”
Kalimat ini bukan slogan idealis, melainkan kritik keras terhadap kecenderungan sebagian kaum terdidik yang memilih sikap kompromis, diam, atau bahkan berkolusi dalam struktur kuasa yang timpang. Di tengah dunia akademik yang semakin terjebak dalam formalitas, seremonialisme ilmiah, dan logika pasar, intelektualitas sejati justru digugat habis-habisan oleh realitas yang mereka diamkan.
Kita hidup dalam zaman ketika gelar akademik dan posisi sosial lebih dirayakan daripada kepekaan etis dan keberanian moral. Ketika kampus-kampus menjadi lebih sibuk dengan akreditasi ketimbang pembebasan pikiran. Ketika para dosen, peneliti, dan cendekiawan sibuk dengan pengumpulan angka kredit, publikasi jurnal berbayar, dan seminar internasional yang hampa konteks lokal. Maka pertanyaannya: masihkah intelektual layak disebut sebagai penjaga nurani zaman?
Intelektualitas Bukan Kosmetik Gelar, Melainkan Sikap Melawan
Masalah utama dalam praktik intelektual hari ini bukan kekurangan pengetahuan, tetapi absennya keberanian berpihak. Banyak yang menyebut diri intelektual, namun justru menjelma menjadi instrumen kekuasaan: menjadi konsultan pemerintah, juru bicara korporasi, atau akademisi oportunis yang menjual netralitas demi kenyamanan. Intelektualitas kemudian dibungkam oleh logika “tidak enak”, “takut kehilangan proyek”, atau bahkan “jangan terlalu vokal, nanti dicap radikal”.
Padahal, posisi intelektual adalah posisi yang kritis. Ia wajib mempertanyakan segala bentuk otoritas yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia harus menjadi pengganggu ketika sistem mulai stagnan, dan menjadi batu sandungan ketika manipulasi dilanggengkan dalam nama pembangunan atau kemajuan. Ia tidak hadir untuk menyenangkan kekuasaan, tapi untuk menyibaknya, bahkan jika itu mengguncang posisinya sendiri.
Netralitas Bukan Kebajikan, Tapi Pengkhianatan
Dalam kajian-kajian kritis, netralitas bukanlah posisi etis, melainkan posisi fiktif. Tidak ada intelektual yang benar-benar netral; setiap kata, setiap konsep, setiap agenda akademik memiliki muatan ideologis. Ketika seorang intelektual memilih diam atas kekerasan negara, ketimpangan sosial, atau korupsi sistemik, ia sejatinya sedang berpihak pada status quo.
Netralitas hanya menjadi kamuflase bagi mereka yang enggan mempertaruhkan privilese. Dalam konteks ketimpangan struktural, bersikap netral justru berarti mengafirmasi penindasan. Intelektualitas semacam ini patut dipertanyakan, jika bukan dikecam. Seperti yang ditegaskan Paulo Freire, “Kebenaran harus diungkapkan, walaupun itu membuat kita tidak nyaman. Tidak ada pendidikan netral, semua pendidikan adalah politis.”
Ideologi Sebagai Alat, Bukan Dogma
Ironisnya, sebagian intelektual juga terjebak dalam kultus ideologi. Mereka bukan hanya kehilangan fleksibilitas berpikir, tetapi juga menolak refleksi kritis terhadap kerangka ideologisnya sendiri. Akibatnya, ideologi yang seharusnya menjadi alat pembebasan, berubah menjadi dogma baru. Alih-alih membongkar hegemoni, mereka membangun hegemoni baru dalam nama ideologi yang ‘mereka yakini benar’.
Dalam wacana akademik, ideologi bukan untuk disembah, melainkan untuk dibongkar, diperiksa, dan jika perlu diganti. Sikap terbuka terhadap alternatif pemikiran bukanlah bentuk pengkhianatan, tetapi justru bentuk kedewasaan intelektual. Intelektual tidak boleh menjadi hamba dari satu kerangka. Ia harus cukup berani untuk mengakui bahwa semua ide, termasuk miliknya sendiri, tidak pernah final.
Kampus dan Lembaga Ilmu: Menara Gading yang Dipelihara
Institusi pendidikan tinggi sering kali menjadi tempat subur untuk reproduksi status quo. Alih-alih menjadi ruang radikal untuk perubahan sosial, banyak kampus justru menjadi tempat pengkaderan teknokrat: mereka yang paham teori tapi kehilangan etika praksis. Dalam banyak kasus, kurikulum didesain agar mahasiswa patuh, bukan bertanya. Skripsi disusun demi formalitas, bukan untuk menjawab problem sosial. Seminar dilangsungkan demi dokumentasi administratif, bukan untuk melahirkan transformasi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa bukan hanya individu, tetapi juga struktur institusional turut melanggengkan kematian intelektualitas kritis. Di sinilah pentingnya membangun kembali agenda pendidikan yang membebaskan, yang tidak sekadar mengisi kepala dengan teori, tetapi juga menyentuh hati dan menggerakkan tindakan. Pendidikan, sebagaimana ditekankan Ivan Illich, harus menjadi proses yang membebaskan dari segala bentuk domestikasi sosial.
Intelektualitas dan Kerendahan Hati Epistemik
Namun, menjadi kritis tidak berarti merasa paling benar. Intelektual sejati adalah mereka yang terbuka terhadap koreksi. Ia tidak jumawa dengan wawasannya, justru sadar bahwa dunia terlalu luas untuk dipahami sendiri. Kerendahan hati epistemik menjadi syarat mutlak. Ia belajar dari rakyat, mendengar dari bawah, dan tidak merasa terancam oleh suara-suara yang berbeda.
Dengan demikian, intelektual bukan makhluk elitis yang menjauh dari realitas. Ia justru harus bersentuhan langsung dengan denyut persoalan konkret masyarakat. Ia menjadi fasilitator pemikiran, bukan penguasa kebenaran. Ia tidak menara, tapi jembatan. Ia tidak instruktur, tetapi mediator antara teori dan kenyataan.
Melawan Akademisasi Kosong
Saat ini, banyak intelektual terjebak dalam logika akademik yang hiper-formal. Artikel ilmiah dinilai dari Scopus dan indeksasi, bukan dari kebermanfaatannya bagi masyarakat. Penelitian dilakukan demi laporan, bukan untuk perubahan sosial. Ini adalah bentuk kekeringan intelektual yang memprihatinkan. Proyek pengetahuan direduksi menjadi angka-angka, bukan narasi perubahan.
Kritik akademik harus menolak semua bentuk akademisasi kosong. Intelektualitas tidak boleh hanya hidup di jurnal, tapi harus hidup di jalanan, di komunitas, di kampung-kampung, dan di ruang-ruang publik. Jika tidak demikian, maka ilmu hanyalah instrumen birokrasi, dan para cendekiawan hanyalah administrator dari wacana tanpa nyawa.
Penutup: Intelektual, Ambil Posisi atau Ditinggalkan Sejarah
Sejarah tidak pernah menunggu mereka yang ragu-ragu mengambil sikap. Intelektual yang menolak berpihak dalam kondisi krisis adalah intelektual yang telah gagal dalam tugasnya. Mereka tidak hanya gagal secara etis, tetapi juga secara epistemologis. Karena tugas pengetahuan adalah menggali kebenaran, dan kebenaran tidak akan muncul dalam kemapanan.
Maka, jika intelektualitas hari ini ingin tetap relevan, ia harus kembali ke akar utamanya: bersikap kritis, berpihak pada kebenaran, terbuka terhadap pembaruan, dan hadir dalam kehidupan nyata masyarakat. Tidak cukup menjadi cerdas, ia harus berani. Tidak cukup paham, ia harus bertindak. Tidak cukup hadir di ruang akademik, ia harus masuk ke ruang sosial, politik, dan budaya, sebagai subjek yang menggugat.
Jika tidak, maka intelektual akan menjadi fosil budaya, artefak simbolik yang tak punya pengaruh apa pun pada perubahan zaman.

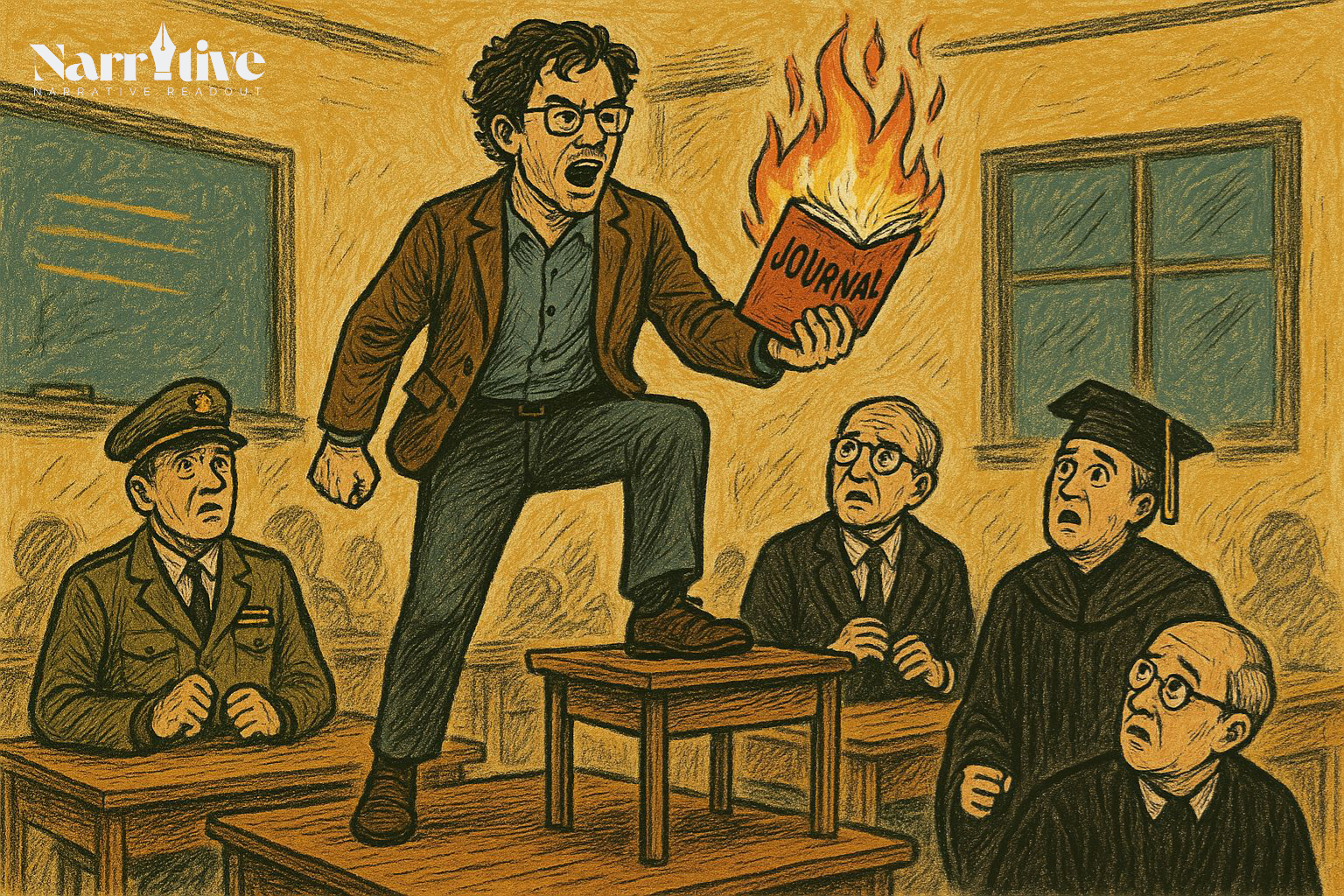
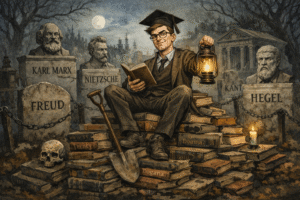



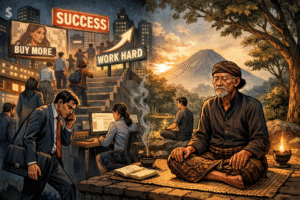
Be First to Comment