Esai | oleh: Adnan G Pandeglang
uSER hadir dari pinggiran, menantang dominasi sastra arus utama. Mereka menulis tanpa izin, menciptakan ruang alternatif, dan menghidupkan kembali makna sastra.
uSER: Suara Pinggiran yang Menggugat Hegemoni Sastra Arus Utama di Indonesia
Di ruang-ruang sastra yang terus-menerus dirayakan, diabadikan, dan dibakukan,
seringkali hanya ada satu suara yang didengar: suara pusat. Pusat yang dimaksudbukan sekadar geografis, tapi sebuah bentuk dominasi kultural yang dibungkus olehestetika, lembaga, nama besar, dan legitimasi sejarah. Dalam lanskap sastra Indonesia hari ini, apa yang disebut sebagai “sastra” cenderung dipahami melalui lensa yang sama: lensa yang dibentuk oleh institusi pendidikan, festival nasional, penerbit besar, dan kurator sastra yang bekerja layaknya orakel, memberi tahu khalayak apa yang layak dan apa yang harus dilupakan. Sementara itu, suara-suara dari pinggiran, dari ruang-ruang yang tidak diakui sebagai bagian dari tubuh utama sastra, sering kali hanya menjadi gema, pantulan, atau bahkan distorsi yang tidak dianggap sah.
uSER, dalam konteks ini, adalah mereka yang berada di luar pusat—bukan sebagai
antitesis, tapi sebagai entitas yang tidak pernah diminta pendapatnya dalam
menentukan arah wacana. uSER bisa penulis muda di kota kecil, penyair yang tumbuh dari komunitas informal, atau pembaca yang menolak berpihak pada satu genre tertentu. Mereka tidak memiliki akses ke jurnal sastra, tidak pernah dipanggil dalam residensi, tidak akrab dengan teori sastra pascakolonial, dan tidak mengenal siapa yang pernah jadi juri sayembara. Mereka hanya menulis, membaca, membuat zine, membuka ruang baca kecil di kampung, atau sesekali menggelar pembacaan puisi diemper toko. Mereka bukan “sastrawan”, setidaknya bukan menurut kamus yang dipakai oleh panitia festival sastra di kota besar.
Namun, dari luar pagar itu, uSER melihat dengan jeli bagaimana sastra dibentuk
bukan sebagai peristiwa kebudayaan yang terbuka, melainkan sebagai ruang kultus.
Ruang ini diisi oleh pengultusan pada tokoh-tokoh tertentu yang disebut “kanon”. Mereka bukan hanya dianggap penting, tetapi diberi posisi sakral. Nama-nama seperti Chairil, Pram, Sapardi, Sitor, Goenawan, dan sejenisnya terus-menerus dipanggil ulang dalam seminar, buku pelajaran, dan lomba-lomba nasional, bahkan tanpa pembacaan kritis. Bukan berarti mereka tidak penting, tapi kultus terhadap mereka
telah menghapus kemungkinan pembacaan baru. Kultus melumpuhkan, bukan menghidupkan. Bahkan di antara nama-nama kontemporer pun, sistem kultus ini terus dipertahankan: beberapa nama terus disebut, direview, dikutip, sementara yang lain hanya menjadi pengisi daftar panjang antologi yang tidak pernah dibicarakan setelah
dicetak.
Kultus ini diperkuat oleh media sastra arus utama dan jejaring akademik yang memiliki kekuasaan epistemik. Apa yang dianggap puisi, cerpen, atau naskah lakon yang “baik” seringkali mengacu pada kaidah yang didefinisikan oleh segelintir orang: gaya bahasa harus padat, metafora tidak boleh berlebihan, harus ada konflik, harus selesai dengan klimaks atau ironi. uSER yang menulis dengan gaya patah-patah, menggunakan bahasa yang campur-aduk, atau menolak struktur klasik akan dicap “belum matang”,
“tidak estetis”, atau lebih buruk lagi: “gagal sastra”. Bahkan bentuk-bentuk sastra yang lahir dari ruang digital pun seperti status Facebook, puisi Instagram, narasi WhatsApp masih dianggap rendahan karena tidak melalui jalur distribusi formal.
Hegemoni estetika ini adalah bentuk kekuasaan yang bekerja diam-diam. Ia mengatur apa yang layak disebut karya, tanpa disadari oleh mereka yang menerapkannya. Seorang penulis muda mungkin merasa harus menulis dengan gaya yang menyerupai cerpen Kompas agar dianggap “sastra”. Ia menghindari kata-kata kasar, menata struktur naratifnya serapi mungkin, dan berusaha meniru gaya cerpenis mapan. Ia tidak sedang mengekspresikan dirinya, tetapi sedang menyesuaikan diri dengan pasar nilai yang telah ditentukan. Proses ini tidak selalu brutal, tapi sangat efektif:
membuat orang menulis bukan karena dorongan kreatif, melainkan karena keinginan untuk cocok dengan selera pusat.
Sementara itu, ruang-ruang eksperimental yang mencoba keluar dari pakem dengan
menggabungkan visual, kolase, suara, puisi konkret, atau pertunjukan tubuh masih dianggap “pinggiran”, “alternatif”, atau “seni performans”. Kata “sastra” seperti dikunci pada bentuk-bentuk tertentu. Padahal, sejarah sastra sendiri tidak pernah tunggal. Jika kita melihat ke belakang, puisi Chairil dulu pernah dianggap keterlaluan, Pram pernah dicekal, dan Wiji Thukul pernah dianggap agitator. Namun ironisnya, ketika mereka masuk ke dalam sistem kultus, semua pembacaan liar terhadap mereka dimatikan. Mereka dikuduskan, bukan dihidupkan.
Dalam ruang ini, uSER melihat bahwa sastra telah kehilangan sifat revolusionernya.Ia menjadi repetitif, seremonial, dan elit. Festival sastra menjadi ajang pertemuan antara nama-nama besar yang sama, dengan moderator yang sama, dan panel diskusi yang kalaupun membahas hal-hal baru selalu dikembalikan ke “kanon yang
sudah terbukti”. Tidak ada tempat bagi suara-suara yang datang dari luar: dari buruh yang menulis puisi, dari ibu rumah tangga yang membuat fiksi di TikTok, atau dari remaja yang mencampur puisi dengan lirik dangdut koplo. Sastra menjadi eksklusif bukan karena kualitas, tetapi karena proteksi.
Kita bisa melihat bagaimana pemetaan kekuasaan ini bekerja dari cara karya diseleksidalam lomba-lomba sastra nasional. Karya yang menang biasanya yang “rapi”: mengikuti tema, tidak menyinggung agama terlalu tajam, dan menggunakan gaya bahasa yang cenderung konservatif. Sementara karya yang bermain-main dengan absurditas, tubuh, kelisanan, dan kegelisahan eksistensial yang tanpa bentuk sering
kali tersingkir. Hegemoni ini mengakar bukan hanya dalam seleksi, tapi dalam cara kritik dibentuk: bahwa sastra harus ditafsir secara formalistik, atau bahwa bahasa harus mengandung kedalaman spiritual, atau bahwa puisi harus menghindari kata-kata vulgar. Semua ini membentuk selera kolektif yang sebenarnya tidak pernah netral.
Namun uSER tidak tinggal diam. Dalam sunyi, mereka membentuk ruang-ruang
tandingan: komunitas kecil yang mencetak pamflet puisi dengan mesin fotokopi, acara baca puisi di teras rumah warga, zine digital yang menyebar lewat PDF dan link Google Drive, hingga pentas pertunjukan yang menyatukan kata, tubuh, dan suara tanpa izin dari siapa pun. Mereka tidak menunggu diundang. Mereka tahu tidak akan pernah masuk daftar nominasi atau dibahas dalam jurnal kampus. Tapi mereka terus menulis, bukan untuk validasi, tapi karena mereka tahu sastra bukan milik segelintir
orang.
Penolakan uSER terhadap ruang kultus dan hegemoni bukan hanya soal estetika, tapi juga soal kelas. Banyak dari mereka datang dari latar belakang ekonomi dan
pendidikan yang tidak memungkinkan mereka masuk ke jaringan pusat. Mereka tidak tahu siapa dosen sastra terkemuka, tidak pernah ikut lokakarya menulis berbayar, dan tidak punya uang untuk mencetak buku di penerbit mayor. Tapi mereka tahu apa itu luka, apa itu ketertindasan, dan bagaimana menuliskannya. Dan mereka menuliskannya dengan bahasa yang mereka miliki: bahasa yang tidak selalu benar menurut tata bahasa, tapi jujur menurut pengalaman.
Inilah yang membuat karya-karya uSER punya kekuatan politik yang tidak dimiliki oleh karya sastra mapan. Mereka tidak berbicara dari menara gading, tapi dari tanah Mereka tidak meminjam gaya bahasa Pram atau Seno, tapi menciptakan bahasa baru dari gabungan bahasa ibu, slang lokal, dan potongan-potongan realitas digital. Mereka tidak takut menggunakan kata kasar, tidak takut membuat narasi tidak selesai, dan tidak takut terlihat bodoh. Karena mereka tidak sedang menciptakan citra, tapi sedang menciptakan ruang.
Sastra yang dibayangkan oleh uSER adalah sastra yang berisik, tidak rapi, penuh typo, tapi hidup. Sastra yang mengizinkan seseorang menulis puisi dari keterangan
struk belanja, yang memungut frasa dari percakapan tukang parkir, atau menulis
cerpen dari mimpi buruk yang dicatat di catatan handphone. Sastra yang tidak
menunggu diakui oleh kampus, tapi tumbuh liar seperti rumput di sela-sela trotoar.
Dan dari sinilah, kita melihat bahwa sastra tidak pernah benar-benar milik institusi. Ia hanya dipinjam, dikekang, dan dipresentasikan dalam bentuk yang bisa dijual. Tapi di luar panggung itu, sastra terus bergerak, berubah, dan membentuk dirinya sendiri. uSER tahu ini. Dan itulah mengapa mereka tidak butuh altar. Mereka tidak butuh penobatan. Mereka tidak butuh mahkota. Mereka hanya butuh ruang yang tidak dikunci, mikrofon yang tidak dimonopoli, dan keberanian untuk terus menulis meskipun tidak pernah disebut “pemenang”.
Dalam konteks yang lebih luas, inilah bentuk perlawanan paling radikal terhadap sistem pengetahuan yang mapan: mengabaikannya. uSER tidak ingin menjadi bagian dari pusat, mereka ingin membongkar cara pusat berpikir. Mereka ingin menulis tanpa harus mengutip Derrida, membaca puisi tanpa harus memakai diksi yang puitis, dan menciptakan naskah teater yang tidak perlu dipentaskan di gedung kesenian. Mereka ingin membentuk dunia sastra mereka sendiri dimana dunia yang tidak dibangun dari hierarki, tapi dari kegembiraan, kemarahan, dan keberanian untuk berkata: “Aku menulis, karena aku marah.”
Dan ketika ruang-ruang kultus itu mulai retak, bukan karena debat di seminar, tapi
karena ratusan uSER menulis dari tempat-tempat yang tidak terpetakan, maka sastra akan menemukan kembali dirinya. Bukan sebagai sistem nilai, tapi sebagai medan perjuangan. Bukan sebagai altar, tapi sebagai medan perlawanan. Bukan sebagai sejarah, tapi sebagai kekacauan yang penuh kemungkinan.


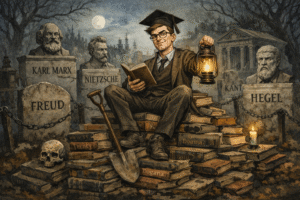



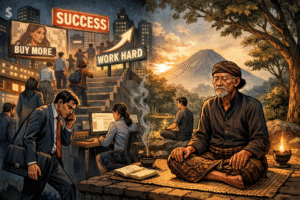
Be First to Comment