Esai
Spotify menjual mimpi kebebasan musik, tapi kenyataannya hanyalah mesin kapitalisme digital yang mengubur semangat indie.
Spotify Bukanlah Gerakan Indie: Membongkar Paradoks Kapitalisme Musik Digital
Industri musik selalu hidup dalam paradoks. Musik, sejak awal, adalah ekspresi paling intim: hasil pergulatan batin, keresahan sosial, juga kebahagiaan yang ingin dibagi. Ia lahir dari ruang-ruang kecil: kamar tidur, panggung komunitas, studio sederhana di sudut kota. Namun, begitu musik memasuki orbit industri, ia nyaris selalu dijadikan komoditas. Dari piringan hitam, kaset, CD, hingga file digital, industri menjanjikan “akses luas” dan “kebebasan distribusi,” tetapi ujung-ujungnya hanyalah jebakan baru: struktur kuasa yang timpang, distribusi yang eksploitatif, dan mesin kapitalisme yang makin lihai meraup untung.
Spotify hadir sebagai wajah paling mutakhir dari jebakan itu. Ia membungkus dirinya dengan slogan demokratisasi: siapa pun bisa merilis lagu, siapa pun bisa didengar. Narasi ini memikat, terutama bagi musisi muda. Ada imajinasi bahwa band kamar bisa sejajar dengan artis global di satu platform. Namun, di balik wajah manis itu, Spotify sama sekali bukan gerakan indie. Ia adalah korporasi raksasa dengan algoritma sebagai senjata, data sebagai komoditas, dan investor sebagai tuan. Tujuan utamanya sederhana: akumulasi keuntungan.
Indie sejak awal bukan sekadar soal label. Indie adalah sikap: otonomi, kemandirian, perlawanan terhadap dominasi pasar, dan kedekatan dengan komunitas. Indie tumbuh di distro kecil, di rilisan kaset fotokopian, di gigs alternatif yang lebih mengutamakan kebersamaan daripada profit. Indie adalah pernyataan keras bahwa musik bisa hidup tanpa tunduk pada logika industri. Maka, ketika Spotify tampil dengan dalih memberi ruang bagi semua, kita harus sadar: yang dijual bukan semangat indie, melainkan ilusi visibilitas.
Spotify menjanjikan peluang, tetapi yang terjadi hanyalah kompetisi brutal dalam samudra lagu. Ratusan ribu lagu dirilis setiap minggu; mayoritas akan tenggelam. Hanya segelintir yang naik ke permukaan, dan itu pun ditentukan oleh algoritma yang tidak transparan. Musisi baru berharap lagunya bisa masuk playlist populer, tetapi harapan itu sama saja dengan membeli lotre. Sementara itu, Spotify tetap mengantongi keuntungan dari setiap klik, dari setiap detik lagu yang diputar.
Paradoks kapitalisme digital bekerja sangat halus. Spotify seolah netral, hanya menjadi perantara. Faktanya, ia adalah gatekeeper. Algoritma menjadi kompas yang menentukan apa yang layak muncul ke pendengar, dan musisi dipaksa tunduk. Lagu dipangkas, intro dipersingkat, hook ditempatkan di awal, semua demi memenuhi logika skip-after-15-seconds. Musik dipaksa tunduk pada format cepat saji. Keunikan dan eksperimen, yang dulu jadi napas indie, perlahan terpinggirkan.
Mari tarik ke belakang: kooptasi kapitalisme atas musik bukanlah hal baru. Indonesia punya sejarah dekat dengan hal itu. Ingat ketika KFC beberapa tahun lalu memproduksi CD band-band Indonesia? Narasinya sama: mendukung musik lokal, membantu distribusi. Nyatanya, CD itu hanya gimmick untuk mendongkrak penjualan ayam goreng. CD dipajang di kasir, dibundel dengan paket makanan, dijadikan hadiah promosi. Begitu strategi usang, KFC berhenti, meninggalkan band-band yang sempat mereka “angkat.” Tidak ada keberlanjutan, tidak ada komitmen, hanya kalkulasi bisnis.
Atau contoh lain: brand rokok yang seolah peduli dengan pergerakan indie. Mereka membiayai festival, tur, panggung megah. Musisi indie tampil, penonton ramai, seolah-olah ada perhatian. Namun begitu program promosi selesai, brand menghilang tanpa jejak. Band-band itu kembali tenggelam, sementara brand sudah meraup citra keren di mata anak muda. Lagi-lagi, musik hanyalah alat untuk menggaet konsumen.
Pola ini persis dengan Spotify, hanya lebih canggih. KFC menjual ayam goreng, rokok menjual citra, dan Spotify menjual ilusi visibilitas. Sama-sama memanfaatkan musik sebagai komoditas tambahan. Bedanya, Spotify melakukannya secara permanen, global, dan dengan algoritma sebagai wajah ramahnya. Musisi indie hari ini berada pada posisi yang sama dengan band-band yang dulu dipajang di kasir KFC atau dipanggungkan brand rokok: hanya alat bagi akumulasi kapital.
Di titik inilah kita harus meminjam kaca mata teori kapitalisme budaya. Adorno dan Horkheimer sudah lama memperingatkan bahwa industri budaya tidak netral. Ia mencetak produk-produk yang tampak beragam, tetapi sejatinya homogen. Kebebasan yang ditawarkan hanyalah variasi dalam sistem yang sama. Spotify adalah contoh telanjang: ia memberi ilusi pilihan tak terbatas, padahal semua diarahkan oleh algoritma untuk memastikan kita tetap berada dalam lingkaran konsumsi.
Žižek menambahkan dimensi lain: kapitalisme modern justru semakin lihai menyerap kritik. Ia tidak sekadar menjual produk, tapi juga menjual perlawanan. Spotify punya playlist “Indie Hits,” bahkan mungkin suatu hari akan membuat playlist “Anti-Capitalist Indie.” Semua bisa dijadikan komoditas. Kritik pun dimakan, dikunyah, lalu dipasarkan kembali sebagai gaya hidup. Indie, yang semula sikap perlawanan, direduksi menjadi kategori playlist.
Chomsky dengan manufacturing consent juga relevan. Spotify adalah media baru yang membentuk konsensus, bukan hanya menyediakan musik. Dengan algoritma, ia menentukan apa yang dianggap tren, apa yang layak didengar. Musisi yang tidak sesuai dengan logika algoritmik otomatis tersingkir. Begitu pula pendengar: mereka tidak lagi memilih secara bebas, melainkan diarahkan secara halus oleh rekomendasi sistem.
Inilah wajah kapitalisme budaya: ia tidak hanya menjual musik, tapi juga membentuk cara kita berpikir tentang musik. Kita mulai mengukur keberhasilan musisi dari jumlah stream, bukan dari kedalaman karya atau ikatan komunitas. Kita mulai menganggap “didengar jutaan kali” sebagai validasi tertinggi, seolah-olah musik hanyalah statistik. Padahal inti dari musik adalah pengalaman, bukan angka.
Dan di sinilah indie kehilangan makna. Indie yang dulu menolak normalisasi kini justru dinormalisasi. Indie yang dulu menolak industri kini menjadi subkategori industri. Spotify menjual indie sebagai segmen pasar, sama persis seperti KFC menjual CD band atau rokok menjual festival. Semua demi keuntungan.
Ironinya, Spotify bisa dengan bangga menampilkan musisi protes di platform mereka, tahu bahwa setiap klik tetap akan menghasilkan uang. Bahkan kritik pun tak lagi berada di luar sistem. Kapitalisme budaya sudah berhasil mengunyah perlawanan, memuntahkannya kembali sebagai produk.
Karena itu, mari tegaskan: Spotify bukanlah gerakan indie. Ia hanyalah etalase kapitalisme digital, mal raksasa tempat semua orang boleh membuka lapak, tapi hanya segelintir yang mendapat sorotan. Spotify tidak lahir dari komunitas, tidak berpihak pada musisi, dan tidak peduli pada keberlanjutan gerakan. Ia peduli pada angka, pada data, pada laba.
Indie sejati tidak lahir dari algoritma. Indie lahir dari keberanian menolak homogenisasi, dari gig di ruang sempit yang penuh peluh, dari rilisan kaset yang dibagikan tangan ke tangan, dari komunitas yang saling menopang. Indie adalah sikap untuk menjaga otonomi artistik, bukan sekadar kategori di etalase digital.
Spotify boleh dipakai sebagai alat distribusi, tapi jangan pernah dianggap kawan seperjuangan. Kita harus jaga jarak kritis. Karena jika tidak, kita hanya akan mengulang pola lama: dari KFC, dari rokok, hingga Spotify, kapitalisme selalu meminjam energi musik untuk dijadikan komoditas. Bedanya hanya kemasan.
Indie bukan soal platform. Indie adalah perlawanan, adalah sikap, adalah keberanian menjaga suara di tengah arus besar kapitalisme budaya. Jika kita masih percaya bahwa musik lebih dari angka stream, maka kita harus berani mengatakan dengan lantang: Spotify bukanlah gerakan indie.


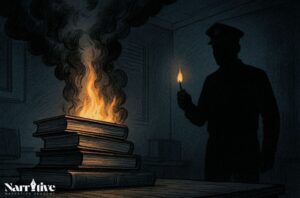
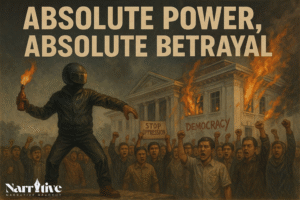

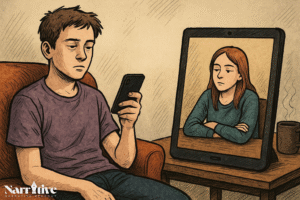
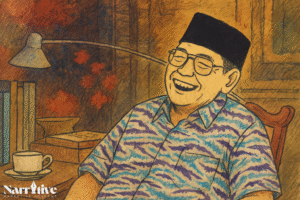
Be First to Comment