Opini
Opini tajam dan kritis terhadap pelaku seni yang berlindung di balik estetika dan narasi kebebasan. Ketika seni menjadi eksklusif, absurd, dan tak bisa lagi disentuh oleh publik—apakah itu masih layak disebut seni?
Seni Itu Kurang NYENI: Ketika Estetika Dijadikan Tameng Ketidakjelasan
“Wah ini seni banget!”
“Tunggu, kamu nggak ngerti ya? Ini karya kontemporer, Bung!”
“Kok kamu bilang jelek? Kamu tuh nggak ngerti seni!”
Ungkapan-ungkapan semacam itu rasanya makin sering terdengar di ruang-ruang diskusi seni hari ini, entah di galeri, forum daring, atau bahkan sekadar di kolom komentar Instagram. Ada semacam aura eksklusivitas yang menguar, yang membuat seni—khususnya seni kontemporer, seni eksperimental, seni instalasi, dan teman-temannya—menjadi ranah yang seolah hanya bisa diakses oleh segelintir orang yang “mengerti.”
Tapi, mari kita tarik napas dan bertanya dengan tenang: apakah benar itu seni? Atau… apakah itu seni yang kurang NYENI?
Estetika sebagai Kedok, Bukan Dasar
Dalam banyak kasus, kita bisa temui pelaku seni yang begitu getol berbicara soal estetika. Tapi anehnya, semakin panjang ia bicara, semakin kita tak mengerti apa yang dimaksud. Kalimat-kalimatnya bersayap, penjelasannya membingungkan, dan karyanya… ya begitu saja: sekumpulan tali dijepit kawat, atau kaleng kosong digantung di tengah ruangan. Lalu saat publik bingung dan mencoba bertanya, jawaban klasik yang keluar: “Itu pengalaman estetis personal.”
Itulah titik krusial kritik ini. Banyak pelaku seni berlindung di balik narasi estetika yang kabur. Estetika yang seharusnya jadi jembatan antara pencipta dan publik malah dijadikan tameng. Narasi tentang kebebasan berekspresi pun ikut dibawa-bawa, seakan semua yang keluar dari tubuh sang seniman—tanpa proses, tanpa disiplin, tanpa konsep matang—berhak disebut karya.
Memangnya siapa yang bisa melarang orang berkarya? Tentu tidak ada. Tapi ketika karya itu masuk ruang publik dan menuntut untuk dipahami serta diapresiasi, maka sah-sah saja publik bertanya, mengkritik, bahkan menolak. Di sinilah letak keberanian dan kejujuran seniman diuji: apakah ia akan membuka ruang dialog atau justru menyematkan label “nggak ngerti seni” kepada orang yang bertanya.
Kebebasan yang Impulsif
Ada kecenderungan lain yang juga patut disoroti: impulsivitas dalam proses berkarya. Banyak seniman muda, atau bahkan yang sudah dianggap mapan, tampak mengandalkan dorongan sesaat dalam mencipta. Mereka menyebut itu intuisi, insting artistik, atau bahkan kedatangan wahyu kreatif. Tidak salah. Tapi yang jadi soal adalah: di mana prosesnya? Di mana pencarian, kegagalan, dan pengendapan ide yang semestinya menyertai setiap karya seni?
Impulsif bukanlah sinonim dari bebas. Kebebasan artistik tak pernah berarti semata-mata bebas melakukan apa saja tanpa tanggung jawab intelektual dan emosional atas apa yang diciptakan. Bahkan seniman eksperimental besar seperti Jackson Pollock atau Yayoi Kusama memiliki rute panjang dan penuh luka sebelum mereka tiba pada bentuk karya yang kelihatannya sembarangan.
Impulsif bisa menyala di awal, tapi karya seni yang bernilai lahir dari pengolahan panjang—secara teknik, konsep, maupun nilai.
Antara Dekonstruksi dan Delusi
Satu lagi narasi populer yang sering jadi andalan: dekonstruksi. Segala sesuatu yang tak bisa dipahami, yang keluar dari batas kebiasaan, dengan cepat diberi label ini. Tapi apakah mereka benar-benar memahami apa yang sedang mereka dekonstruksi?
Dekonstruksi bukan sekadar menghancurkan atau membalikkan sesuatu secara acak. Ia adalah metode berpikir, hasil pergulatan panjang, bahkan bersinggungan dengan filsafat—terutama Derrida. Sayangnya, di tangan beberapa pelaku seni, istilah ini menjadi mantra tanpa makna. Pokoknya asal beda, asal rusak, asal kontra, lantas disebut dekonstruktif.
Inilah jebakan delusi dalam proses kreatif. Mengira diri sedang mendobrak padahal belum membangun apa-apa. Mengira sedang menolak norma padahal belum benar-benar memahami norma itu sendiri. Akhirnya, karya yang dihasilkan hanya jadi tabrakan acak elemen visual atau objek, tanpa benang merah, tanpa bobot, tanpa nyawa.
Estetika yang Mengintimidasi
Tak berhenti di situ, ada satu fenomena yang cukup mengganggu: estetika yang dipaksakan menjadi sistem dominasi. Iklim diskusi seni seolah dirancang agar orang takut mengkritik, takut tidak suka, takut bertanya. Orang-orang akhirnya memilih diam atau pura-pura mengerti demi terlihat “intelek.”
Salah satu contoh realnya bisa kita lihat saat pembukaan pameran. Ketika seseorang berani berkata, “Maaf, saya tidak paham karya ini,” reaksi umum bukan dialog, tapi intimidasi. Ia akan dicap tak mengapresiasi, tak memiliki sensibilitas seni, bahkan dianggap merusak semangat berkesenian.
Inilah atmosfer yang tidak sehat. Karena jika seni benar-benar ingin hidup dalam masyarakat, maka ia harus terbuka pada kemungkinan gagal, pada kritik, bahkan pada olok-olok. Seni bukan zona steril. Ia justru hidup karena pertarungan gagasan dan sensasi, bukan hanya karena standing applause dari teman sendiri.
Antara Abstrak, Kontemporer, dan Kosong
Banyak yang lupa bahwa seni kontemporer atau abstrak bukan lahir dalam kekosongan. Ia lahir dari sejarah panjang seni klasik, seni rupa modern, hingga seni konseptual. Ada proses panjang dan ketat yang dilalui oleh para pelakunya, baik secara teknik maupun wacana. Seni kontemporer tidak bisa diklaim hanya karena ingin terlihat “berbeda” atau “anti-mainstream.”
Namun hari ini, begitu mudah seseorang memajang bangku rusak atau proyeksi cahaya buram lalu menyebutnya sebagai “seni instalasi kontemporer.” Tanpa narasi, tanpa proses, tanpa penalaran. Ironisnya, banyak juga kurator atau kolega seniman yang malah mengamini hal ini dengan puja-puji kosong. Lagi-lagi, bukan karena mereka benar-benar paham, tapi karena takut tersingkir dari lingkaran pergaulan “estetik.”
Seni semacam ini kehilangan bobot sosial dan nilai puitiknya. Ia tidak menghadirkan perenungan, tidak juga mengundang imajinasi. Ia hanya menjadi tanda status sosial—sebuah objek yang dipamerkan demi gaya, bukan makna.
Seni Itu Kurang “NYENI”
Mari kita luruskan satu hal penting: ungkapan “seni itu kurang NYENI” bukanlah keluhan karena seni kurang artistik, melainkan sebuah sindiran sinis. NYENI di sini adalah istilah sarkastik—merujuk pada karya seni yang sok terlihat kompleks, sok absurd, sok eksperimental, padahal miskin proses, lemah konsep, dan dideklarasikan begitu saja hanya demi terlihat berbeda.
Istilah “NYENI” ini lazim digunakan untuk menertawakan karya-karya yang terlalu diglorifikasi oleh lingkungan seni tanpa alasan yang cukup. Misalnya, saat sebuah pameran menghadirkan benda-benda sehari-hari yang ditempatkan secara acak, lalu diselimuti dengan narasi berat penuh jargon, pengunjung awam akan bertanya-tanya: “Apa maksudnya?” Tapi jawaban yang didapat malah: “Kamu harus peka, ini NYENI banget!”
Justru di titik inilah kritik ini bermula. Kita hidup di iklim seni yang terlalu sering merayakan apa yang terlihat seni banget, namun lupa mempertanyakan: apakah ini punya bobot? Apakah ini punya proses? Apakah ini benar-benar hasil pencarian estetis, atau hanya manuver gaya-gayaan untuk mengesankan eksistensi kreatif?
Jadi, ketika kita bilang “seni itu kurang NYENI,” itu berarti kita sedang menertawakan seni yang tak terlalu sibuk berdandan jadi “seni.” Seni yang tak terlalu ngotot untuk tampil NYENI, justru kadang lebih jujur dan kuat. Sebaliknya, karya yang terlalu memaksakan diri tampak NYENI malah sering kali kehilangan makna dan kesadaran proses.
Pengalaman Estetis Tidak Sama dengan Legitimasi Mutlak
“Pengalaman estetis itu subjektif.”
Benar. Tapi subjektivitas itu tidak menjadikan karya seni otomatis “bernilai.” Pengalaman estetis adalah pintu masuk, bukan kesimpulan. Dan pengalaman estetis pun ada derajatnya—ada yang menyentuh, ada yang dangkal, ada yang nihil.
Banyak seniman menjadikan pengalaman estetis sebagai legitimasi mutlak: “Karena saya mengalami sesuatu saat membuat ini, maka ini adalah karya seni yang penting.” Ini adalah bentuk egosentris yang nyaris mistis. Ia mengabaikan peran publik, dialog, konteks sosial, dan kedalaman konsep.
Seni yang baik tak hanya tentang bagaimana perasaan penciptanya saat membuat, tapi juga bagaimana karya itu membuka kemungkinan pengalaman baru bagi orang lain. Seni bukan sekadar curhat pribadi yang tak boleh disentuh.
Seni yang Brernilai
Lalu, seperti apa seni yang “bernilai”?
Seni yang bernilai adalah seni yang menyentuh dan menggetarkan karena ia lahir dari proses. Ia tidak harus realistis, tidak harus rapi, bahkan tidak harus bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi ia memiliki benang merah. Ia mengandung sense of wholeness yang membuat publik merasakan sesuatu, meski tidak bisa menyebutkannya secara verbal.
Seni yang bernilai tidak anti kritik. Ia justru tumbuh dari diskusi. Ia tidak memaksakan pengakuan. Ia mengundang penjelajahan. Ia tidak merasa lebih tinggi dari publik, justru ingin menjangkau sebanyak mungkin orang tanpa mengorbankan integritas.
Dan yang paling penting, seni yang bernilai tidak pernah menggampangkan. Ia bukan hasil karbitan, bukan sekadar eksperimen dadakan, bukan hanya demi terlihat “aneh.” Ia tumbuh dari kerja keras, pengolahan batin, dan refleksi yang terus-menerus.
Menutup dengan Kejujuran
Opini ini tidak dimaksudkan untuk menertawakan atau menjatuhkan para pelaku seni yang sedang berproses. Tapi ia lahir dari keresahan tentang bagaimana ruang-ruang seni hari ini dipenuhi oleh polusi narasi kosong yang menjadikan seni semakin jauh dari publik.
Jika seni hanya dipahami oleh senimannya sendiri, lalu apa bedanya dengan mimpi pribadi yang tak perlu dibagikan?
Jika seni adalah ranah yang menolak kritik, lalu apa bedanya dengan kultus?
Jika seni dibuat tanpa proses dan kedalaman, lalu pantaskah ia disebut seni?
Mungkin sudah saatnya kita berani mengatakan: “Tidak semua yang disebut seni itu benar-benar bernilai.”
Dan dari titik itu, kita bisa mulai kembali membangun kesadaran baru—bahwa seni bukan tentang kemewahan narasi, tapi tentang kejujuran proses dan ketulusan menjangkau makna.


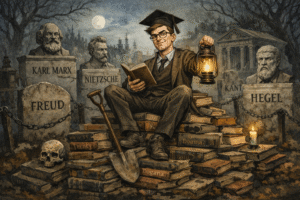

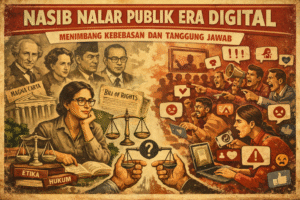


Be First to Comment