Esai| oleh: Miftakhul Shodikin
Kebijakan Presiden Prabowo melibatkan TNI dalam proyek swasembada pangan menuai pro-kontra. Apakah ini solusi krisis pangan, atau justru membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi militer?
Presiden Prabowo Subianto punya gaya yang tak bisa ditiru banyak politisi lain: langsung, blak-blakan, dan tanpa tedeng aling-aling. Ketika Prabowo mengatakan bahwa prajurit TNI akan ikut dalam proyek ambisius swasembada pangan, maka para serdadu yang terbiasa menggenggam senapan itu harus belajar membawa cangkul, traktor, palu dan arit. Militer bersenjata kini harus bertani, gagasan ini nampakanya tidak terlalu asing—terutama yang mengenal sejarah politik Indonesia—bahwa tahun 1965, Partai Komunis Indonesia menggagas pembentukan Angkatan Kelima: “Buruh dan Tani Dipersenjatai”. Kini, di era Prabowo, gagasan itu menjadi “Militer bersenjata ikut Bertani”.
Gema dari Masa Lalu: Buruh Tani dan Senjata
Pada 15 Januari Tahun 1965, D.N. Aidit, tokoh utama Partai Komunis Indonesia (PKI), menggagas pembentukan “Angkatan Kelima”—buruh dan tani bersenjata. Tujuannya sebagai bagian dari revolusi sosial dan politik. Aidit terinspirasi oleh praktik Mao Zedong di Tiongkok, yang menjadikan petani sebagai ujung tombak revolusi proletarian. Petani dipersenjatai bukan hanya dengan cangkul, tapi juga senapan.
Konsep ini, tentu saja, ditentang keras oleh militer, terutama Jenderal Nasution dan kelompok Angkatan Darat. Mereka menganggap ide tersebut subversif dan berbahaya, karena mengancam monopoli negara atas senjata dan membuka jalan bagi kekacauan sosial. Akhir dari cerita ini kita tahu bersama: G30S/PKI meletus, PKI dibubarkan, dan ratusan ribu nyawa melayang dalam gelombang anti-komunisme.
Kini, 60 tahun kemudian, arah sejarah tampak berbalik. Bukan lagi buruh tani yang dipersenjatai, tapi militer bersenjata yang menjadi buruh tani. Dari sudut pandang lain, keterlibatan militer dalam sektor pertanian mencerminkan semacam kerinduan negara pada kontrol total. Kontrol yang tidak hanya terbatas pada pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga kontrol atas produksi. Jika Negara gagal mengefektifkan birokrasi sipil dan tidak lagi dipercaya pada mekanisme pasar, Maka menjadi alarm bencana, apabila militer, dengan struktur yang rapi dan logika komando, dianggap sebagai solusi paling instan dan dapat diandalkan.
Komunisme Agraris: Negara, Tanah, dan Tentara
Dalam ajaran Marxis, tanah adalah alat produksi, dan pertanian adalah basis kekuatan rakyat. Maka dalam komunisme agraris, negara harus mengambil alih kontrol penuh atas tanah, produksi, dan distribusinya. Di Tiongkok era Mao dan Uni Soviet era Stalin, militer menjadi perpanjangan tangan partai: mengawasi kolektivisasi, mengerjakan ladang, dan menumpas perlawanan.
Apa yang kita lihat dalam proyek pertanian Prabowo, meski tidak berdiri di atas kerangka Marxis secara eksplisit, punya rona yang sama: negara mengambil alih peran petani yang dianggap gagal atau tidak efisien. Serdadu militer dipesiapkan menjadi “alat produksi nasional”, bukan hanya alat pertahanan. Mereka menggarap lahan, mengelola irigasi, bahkan dilibatkan dalam proses distribusi.
Petani: Di Mana Mereka?
Di tengah kegandrungan program pangan yang digarap militer ini, ada satu aktor yang justru nyaris tak terdengar: petani. Mereka yang selama ini menanggung beban produksi pangan nasional dengan segala keterbatasan lahan, pupuk, dan akses pasar justru “dikesampingkan”.
Padahal dalam demokrasi yang sehat, rakyat—termasuk petani—adalah subjek pembangunan. Mereka seharusnya didengarkan, dilatih, diberdayakan, dan diberi akses terhadap alat produksi. Yang terjadi justru sebaliknya, Negara menggeser petani dari orkestra utama, menggantikannya dengan militer yang tak memiliki basis kultural maupun pengalaman agraria.
Situasi ini mencerminkan suatu pergeseran besar dalam watak negara. Jika dalam teori politik liberal, negara ideal digambarkan sebagai penjaga malam (nachtwächterstaat), yakni negara yang hanya hadir untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi hak milik (sebagaimana dipopulerkan oleh pemikir seperti Robert Nozick).
Kritik terhadap negara penjaga malam justru datang dari berbagai sudut: negara semacam itu dianggap abai terhadap ketimpangan struktural, membiarkan rakyat miskin terpinggirkan oleh kekuatan pasar, dan gagal menjamin kebutuhan dasar warganya, termasuk pangan. Dalam konteks ini, masuk akal jika negara Indonesia—dengan sejarah panjang kolonialisme, krisis pangan, dan ketergantungan pada impor—memilih jalur sebaliknya: menjadi negara yang aktif, bahkan dominan, dalam sektor-sektor strategis.
Indonesia pasca-Orde Baru memang tidak memilih jalan night-watchman state, tetapi lebih menyerupai apa yang disebut sebagai negara yang mengendalikan arah pembangunan ekonomi secara ketat, yang sering kali tanpa partisipasi rakyat. Dalam proyek swasembada pangan hari ini, kita melihat bentuk baru dari kecenderungan itu—dengan militer dijadikan ujung tombaknya. Negara begitu aktif, bahkan agresif.
Ketahanan Pangan atau Kembalinya Dwifungsi?
Pasca-reformasi 1998, Indonesia berusaha keras mencabut cengkeraman dwifungsi ABRI: militer tidak lagi diberi ruang untuk berperan dalam politik dan ekonomi sipil. Tapi gagasan Prabowo—betapapun niat baiknya—membuka kembali ruang gelap ini. Jika TNI masuk ladang hari ini, apakah besok mereka akan masuk pasar, atau bahkan kembali masuk ke ruang-ruang pemerintahan?
Kita harus membedakan antara ketahanan pangan berbasis rakyat dengan ketahanan pangan berbasis kontrol negara. Yang pertama lahir dari distribusi keadilan agraria, pemberdayaan petani, dan koperasi. Yang kedua lahir dari mobilisasi paksa, militerisasi ekonomi, dan pendekatan top-down yang bertumpu pada kontrol hierarkis.
Pemerintahan Prabowo tampak memosisikan krisis iklim, potensi konflik geopolitik, dan ancaman krisis pangan sebagai dasar pembenaran proyek swasembada berbasis militer. Dalam narasi publik yang ia bangun, sektor pangan dipandang bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan bagian dari strategi pertahanan nasional.
Militer dianggap lebih mampu menjaga keamanan wilayah, efisiensi produksi, dan kontrol distribusi. Narasi ini diperkuat oleh retorika ancaman: krisis global, embargo pangan, dan disrupsi logistik akibat konflik atau bencana. Dalam skenario seperti itu, militer dipandang sebagai aktor paling siap dan sigap. Bahkan, ketahanan pangan disamakan dengan pertahanan negara—food is security.
Namun jika demikian, apakah negara hanya mengandalkan tentara dan mengabaikan petani miskin yang selama ini telah berjuang menanam di ladang?


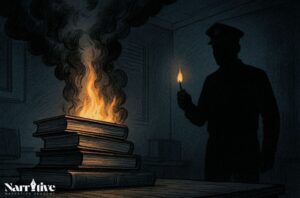
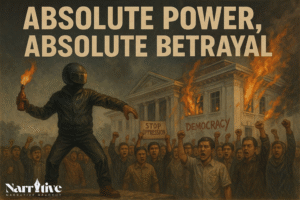
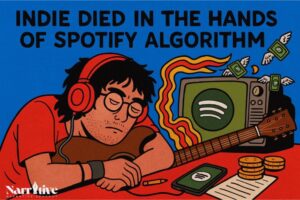

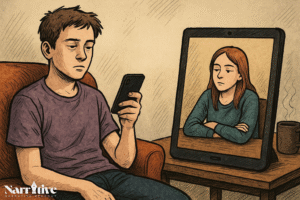
Be First to Comment