Esai
Bagaimana framing atau pencitraan politik bekerja memengaruhi persepsi publik dan memperkuat politik identitas? Artikel ini mengupas strategi komunikasi visual dan dampaknya terhadap polarisasi sosial secara mendalam.
Pencitraan dan Framing: Mesin Persepsi dalam Politik Identitas
Di era informasi dan komunikasi digital yang membanjiri kesadaran publik, pencitraan (image making) dan framing atau pembingkaian informasi bukan lagi sekadar strategi komunikasi, melainkan menjadi alat utama dalam pembentukan realitas politik. Dalam dunia politik kontemporer, kebenaran bukan ditentukan oleh fakta semata, tetapi oleh bagaimana fakta itu dikemas, dilabeli, dan dipresentasikan kepada publik. Inilah yang menjadi kekuatan utama dari pencitraan dan framing.
Namun yang lebih problematik adalah ketika pencitraan dan framing tidak lagi hanya sebatas strategi untuk menyampaikan gagasan politik, melainkan menjadi cara untuk membungkus dan mengeksploitasi identitas kolektif: etnis, agama, kelas sosial, hingga gender. Politik identitas, dalam konteks ini, bukan lagi alat perjuangan kesetaraan, tetapi dipakai sebagai komoditas dan senjata retoris dalam perebutan kekuasaan. Lalu, bagaimana sesungguhnya pencitraan dan framing bekerja dalam membentuk politik identitas, dan apa konsekuensinya terhadap kehidupan demokrasi dan sosial?
Pencitraan: Konstruksi Representasi dan Realitas Semu
Pencitraan adalah praktik strategis dalam membangun sosok atau entitas agar memiliki kesan tertentu di mata publik. Dalam politik, pencitraan bekerja dengan menciptakan kesan bahwa seorang tokoh atau kelompok memiliki kualitas, nilai, atau identitas tertentu yang “dituntut” oleh massa.
Jean Baudrillard, filsuf postmodernis, menyebut fenomena ini sebagai bagian dari simulacra—di mana representasi menjadi lebih penting dari realitas itu sendiri. Dalam pencitraan politik, yang ditampilkan bukan siapa sebenarnya tokoh itu, tetapi siapa yang harus terlihat olehnya. Maka tak heran, kita menjumpai politisi berpakaian ala rakyat jelata saat kampanye, duduk di warung kopi, atau mendadak fasih berbicara isu-isu minoritas yang sebelumnya tak pernah disentuh. Tujuannya jelas: menciptakan impresi emosional dan simbolik yang menjembatani antara citra dan simpati politik.
Namun, pencitraan bukan hanya soal teknis komunikasi. Ia menjadi arena rekayasa identitas—di mana tokoh politik mengadopsi identitas tertentu (etnis, agama, gender, dll) demi mendapatkan legitimasi. Inilah awal dari pertemuan antara pencitraan dan politik identitas.
Framing: Membingkai Fakta, Membangun Realitas
Jika pencitraan adalah seni membentuk representasi, maka framing adalah seni membingkai realitas agar terlihat sesuai dengan narasi yang diinginkan. Framing adalah bagaimana suatu isu dikemas dengan cara tertentu agar memunculkan persepsi yang selaras dengan kepentingan komunikator.
Contoh klasik adalah bagaimana media dan politisi membingkai aksi protes sebagai “kerusuhan” atau “ancaman terhadap stabilitas,” bukan sebagai “ekspresi keresahan rakyat.” Dalam politik identitas, framing sangat krusial. Isu agama bisa dibingkai sebagai simbol perjuangan atau ancaman terhadap toleransi, tergantung siapa yang memframing-nya. Identitas etnis bisa ditampilkan sebagai sumber kebanggaan atau sumber konflik, tergantung bagaimana narasinya dirangkai.
Dengan framing, aktor politik mengontrol persepsi dan emosi publik, serta memanipulasi bagaimana kelompok sosial memahami posisi dan kepentingan mereka dalam arena politik.
Politik Identitas: Dari Perjuangan Menuju Komodifikasi
Politik identitas awalnya adalah strategi perjuangan kolektif bagi kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi: perempuan, LGBTQ+, buruh, kelompok etnis minoritas, dan lainnya. Tujuan utamanya adalah pengakuan, kesetaraan hak, dan keadilan sosial.
Namun, dalam era mediatik dan populisme politik, politik identitas mengalami transformasi. Ia menjadi komoditas elektoral. Tokoh atau partai politik mulai mengeksploitasi identitas kolektif untuk mendapatkan suara. Dalam hal ini, pencitraan dan framing menjadi instrumen utama.
Misalnya, seorang calon kepala daerah bisa memframing dirinya sebagai “wakil dari rakyat kecil” hanya karena ia berasal dari daerah atau suku tertentu—padahal ia adalah bagian dari elit lama. Ia bisa mengenakan simbol agama tertentu untuk memproyeksikan dirinya sebagai pembela nilai-nilai religius, meskipun rekam jejak politiknya jauh dari itu. Identitas bukan lagi alat perjuangan, melainkan kostum elektoral.
Contoh-Contoh Framing Politik Identitas di Indonesia
Fenomena ini terlihat sangat kasat mata di Indonesia. Dalam banyak kasus, agama menjadi simbol yang mudah dibingkai sebagai garis identitas politik. Misalnya, dalam Pilkada Jakarta 2017, framing identitas keagamaan digunakan secara masif untuk menjatuhkan kandidat tertentu dan mengangkat kandidat lain, bukan karena kualitas kinerjanya, melainkan karena “kesamaan identitas.”
Begitu pula dalam isu Papua. Media dan pemerintah kerap menggunakan framing “separatisme” terhadap kelompok pro-kemerdekaan, bukan membingkai persoalan itu sebagai ekspresi ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural. Akibatnya, muncul jarak antara pusat dan pinggiran, antara “kita” dan “mereka”.
Dalam konteks perempuan, politisi sering memakai identitas gender untuk kepentingan elektoral, seperti menunjukkan bahwa dirinya peduli pada isu perempuan, tanpa membangun kebijakan yang nyata. Framing ini menjadikan perempuan sebagai alat simbolik belaka.
Dampak Negatif Pencitraan dan Framing terhadap Politik Identitas
Framing dan pencitraan memang ampuh untuk membangun opini publik, tapi efek jangka panjangnya bisa destruktif terhadap demokrasi dan keadaban politik. Berikut beberapa dampaknya:
- Reduksi Kompleksitas Isu Isu-isu sosial yang kompleks, seperti kemiskinan struktural, konflik agraria, atau ketimpangan pendidikan, direduksi menjadi persoalan identitas. Solusinya pun menjadi dangkal dan simbolik. Masalah kelas menjadi dikaburkan oleh narasi identitas sempit.
- Polarisasi Sosial Framing yang mengusung identitas tertentu dengan menegasikan identitas lain akan memperkuat sektarianisme. Masyarakat terbelah secara horizontal: antar agama, antar etnis, antar kelompok gender. Demokrasi berubah menjadi arena konflik identitas, bukan arena adu gagasan.
- Instrumentalisasi Minoritas Kelompok minoritas sering dijadikan alat pencitraan oleh aktor politik yang tidak memiliki komitmen substantif. Mereka hanya dijadikan simbol inklusivitas, tetapi tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang sesungguhnya.
- Dekadensi Etika Politik Politik menjadi ajang tipu muslihat dan sandiwara. Kejujuran dan integritas digantikan oleh kepiawaian dalam membentuk citra. Ini menciptakan distrust publik terhadap politik dan mendorong apatisme politik.
Menghadirkan Politik Identitas yang Autentik
Namun penting untuk dicatat, politik identitas tidak harus selalu menjadi alat manipulasi. Ia tetap relevan sebagai instrumen perjuangan jika dijalankan secara otentik dan berakar pada pengalaman riil kelompok tertindas.
Kuncinya adalah membedakan antara:
- Politik identitas yang memobilisasi kesadaran kritis dengan
- Politik identitas yang hanya menjual simbol dan retorika kosong.
Politik identitas yang otentik harus menyuarakan pengalaman hidup yang tidak terdengar di ruang publik, memperjuangkan keadilan sosial yang nyata, dan menghadirkan keterlibatan aktif dari komunitas—bukan sekadar menjadi obyek kampanye.
Melawan Framing: Peran Media Alternatif dan Literasi Kritis
Untuk melawan dominasi framing dan pencitraan yang manipulatif, diperlukan ekosistem media yang independen dan masyarakat yang memiliki kesadaran literasi kritis. Media alternatif harus hadir untuk menyuarakan perspektif yang tidak diangkat oleh media arus utama. Pendidikan politik dan literasi media harus menjadi bagian dari kurikulum dan gerakan sosial.
Seperti yang dikatakan Noam Chomsky, “The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum.” Inilah kerja framing: membatasi ruang berpikir sambil menciptakan ilusi kebebasan opini.
Penutup: Mengembalikan Politik kepada Kebenaran Sosial
Dalam menghadapi era banjir informasi dan pencitraan politik, kita perlu lebih waspada terhadap bagaimana identitas digunakan sebagai alat, bukan tujuan. Framing dan pencitraan akan selalu ada, tetapi yang perlu diawasi adalah bagaimana ia membentuk persepsi yang menjauhkan kita dari akar persoalan sebenarnya.
Politik identitas seharusnya menjadi ruang artikulasi penderitaan kolektif dan perjuangan pembebasan, bukan komoditas elektoral yang dibingkai dan dicitrakan oleh elite untuk meraih kekuasaan.
Kita tidak menolak politik identitas. Yang kita lawan adalah manipulasi atas identitas melalui pencitraan dan framing yang mematikan substansi. Karena jika politik hanya menjadi panggung citra dan narasi semu, maka yang menjadi korban adalah publik yang terus-menerus dibuai oleh fantasi, bukan realitas.


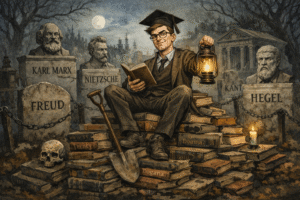



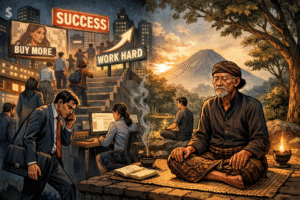
Be First to Comment