Esai
Orkes dangdut bukan sekadar hiburan, tapi gerakan budaya rakyat: dari sistem indie akar rumput hingga perlawanan terhadap label industri dan televisi.

Orkes Dangdut: Gerakan Indie Rakyat, Ekonomi Kolektif, dan Perlawanan Budaya
Di luar sorotan lampu panggung industri musik arus utama, terdapat satu entitas budaya yang selama puluhan tahun bergerak dengan gigih dan mandiri: orkes dangdut. Dalam lanskap budaya populer Indonesia, orkes bukan sekadar hiburan pinggiran. Ia adalah sistem, perlawanan diam, dan arena negosiasi identitas yang kompleks. Dari rekaman live sederhana hingga sistem distribusi kolektif berbasis lapak pasar malam, orkes tumbuh bukan karena diberi ruang, tapi karena merebutnya.
Artikel ini akan menyusuri empat lanskap besar yang membentuk kehidupan orkes dangdut: sistem gerakan independen, jaringan ekonomi kolektif, posisi simbolik dan politisnya dalam relasi kuasa, serta konflik dagang dan budaya dengan industri rekaman serta televisi nasional.
—
I. Orkes sebagai Gerakan Musik Indie Akar Rumput
Membicarakan orkes dangdut tanpa memahami sistem kerja kolektifnya sama dengan membaca naskah tanpa melihat panggung. Tak seperti industri pop yang dibingkai oleh label besar dan agensi pemasaran, orkes tumbuh dan berkembang melalui jaringan mandiri yang tersebar di berbagai desa, kecamatan, hingga kota-kota kecil. Mereka merekam sendiri penampilan live-nya, menjual CD dan kaset hasil produksi langsung ke pasar, dan menyebarkan nama mereka dari mulut ke mulut atau lewat Facebook grup kampung. Mereka hadir di hajatan, pasar malam, dan panggung-panggung tiban. Bukan sekadar penampil, mereka adalah penyintas.
Sistem kerja ini bukan sekadar kepraktisan; ia adalah bentuk gerakan indie yang autentik. Dalam literatur musik global, istilah indie sering dilekatkan pada band yang menolak industri besar dan memilih jalur distribusi alternatif. Tapi di Indonesia, istilah ini sering kali dimonopoli oleh band kota yang tampil di kafe atau festival seni. Padahal, orkes—dengan segala keterbatasan dan kreativitasnya—lebih layak menyandang predikat indie sejati. Mereka tak hanya bergerak tanpa sponsor besar, tetapi juga menciptakan sistem ekosistem sendiri: dari produksi, distribusi, hingga promosi.
Ada filosofi gerakan yang hidup di dalam orkes. Ia tak mengandalkan algoritma digital untuk dikenal, tapi pada koneksi komunitas yang organik. Mereka menciptakan solidaritas di antara teknisi panggung, pemain musik, penari, hingga tukang sound system. Dalam satu panggung orkes, ada belasan kepala yang bergantung pada keberhasilan pertunjukan malam itu. Merekalah wajah ekonomi berbasis komunitas yang terdesentralisasi, jauh sebelum istilah decentralized system menjadi jargon startup masa kini.

—
II. Orkes dan Jaringan Ekonomi Kolektif: Pasar Malam dan Sirkulasi Uang Mikro
Setiap kali orkes digelar di lapangan desa, bukan hanya musik yang hidup, tapi juga ekonomi. Pedagang kaki lima, penjual cilok, tukang balon, hingga pemilik wahana komidi putar mendadak hadir membentuk simpul ekonomi rakyat. Satu pertunjukan orkes bisa menggerakkan siklus uang yang tidak kecil. Uang berpindah dari penonton ke pedagang, dari panitia ke penyewa sound system, dari pemilik genset ke penyedia panggung tiban. Ini bukan sekadar konser, ini adalah pasar ekonomi kolektif yang bergerak dari satu desa ke desa lain.
Dalam pandangan kritis ekonomi, sistem ini dapat dibaca sebagai bentuk ekonomi informal yang menolak sentralisasi kapital. Pierre Bourdieu menyebut bahwa praktik-praktik ekonomi lokal seperti ini bukan sekadar aktivitas ekonomi, tapi juga bentuk habitus sosial yang mereproduksi nilai-nilai komunitas. Di sinilah orkes menjadi agen ekonomi sekaligus agen budaya.
Joseph Stiglitz, dalam kritiknya terhadap neoliberalisme, menekankan pentingnya sistem ekonomi berbasis komunitas untuk menyeimbangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh pasar bebas. “Ketika negara gagal menciptakan sistem pemerataan ekonomi, rakyat akan menciptakan sistemnya sendiri,” ujar Stiglitz. Apa yang dilakukan orkes dan pasar malam adalah contoh dari sistem ekonomi rakyat yang hidup dan terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tanpa harus tunduk pada logika modal besar.
Sirkulasi uang mikro dalam dunia orkes bukan berarti kecil dalam dampak. Ia menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan: buruh harian, petani kecil, pemuda pengangguran, ibu rumah tangga pencari nafkah tambahan. Ketika pemerintah mempromosikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, orkes sudah lebih dulu membuktikan bagaimana komunitas rakyat dapat saling menopang melalui sistem kolektif tanpa banyak intervensi birokratis.
—
III. Relasi Kuasa dan Identitas: Orkes, Kampungan, dan Eksistensi Kelas
Namun, di balik geliat budaya ini, orkes juga tak lepas dari stigma. Ia dianggap kampungan, sumber kericuhan, dan terlalu sensual. Padahal, stigma ini bukan sekadar persoalan selera. Ia adalah konstruksi dari relasi kuasa dan identitas kelas. Mengundang orkes tampil dalam hajatan besar atau acara desa bukan hanya soal hiburan, tapi juga pernyataan simbolik dari strata ekonomi tertentu.
Orkes menjadi representasi dari mereka yang tak memiliki akses terhadap konser musik eksklusif, jazz festival berkelas, atau gedung pertunjukan seni. Ia adalah milik rakyat biasa, dan karena itulah ia sering dipinggirkan. Michel Foucault dalam kajian relasi kuasanya menekankan bahwa pengklasifikasian budaya “tinggi” dan “rendah” adalah cara kekuasaan membentuk wacana dominan dan mendefinisikan siapa yang pantas dianggap berbudaya.
Dalam konteks ini, orkes dangdut bukan hanya musik, tetapi medan kontestasi identitas kelas sosial. Ketika sebuah kampung mengundang orkes dan warga berdatangan dengan segala ekspresi spontan mereka—menari bebas, menyanyi keras, berjoget bersama—mereka bukan sedang kehilangan kontrol, melainkan sedang merebut kembali ruang kebahagiaan yang selama ini direpresi oleh norma borjuisme.
Kaum marginal bukan tak tahu tata krama, mereka hanya tak punya cukup ruang untuk mengekspresikan kebahagiaan secara “beradab” dalam standar elite. Maka ketika negara atau elite budaya mencoba menertibkan orkes dengan alasan “mengganggu ketertiban umum”, itu bukan upaya penyelamatan moral, tapi perpanjangan dari proyek domestikasi budaya rakyat.
Raymond Williams, seorang pemikir budaya dari Inggris, menyebut bahwa budaya rakyat kerap kali disingkirkan oleh “sistem dominan” karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai resmi yang dikontrol oleh kelas berkuasa. Dalam orkes, kita melihat bagaimana yang “tidak resmi” justru menjadi arus hidup budaya yang paling jujur dan otentik.
—
IV. Perang Dagang dan Politik Pasar: Orkes Dangdut vs Label Industri dan Televisi
Dalam bentang panjang sejarah musik Indonesia, orkes dangdut bukan hanya menghadapi pengabaian, tapi juga perlawanan laten dari kekuatan ekonomi dan budaya yang lebih mapan. Salah satunya adalah industri rekaman besar dan sistem penyiaran televisi yang sejak awal memainkan peran penting dalam menciptakan selera arus utama. Di sinilah medan tarik-menarik itu terjadi: antara suara rakyat yang spontan dan hidup dengan sistem distribusi budaya yang dikendalikan oleh modal dan rating.
Orkes—dalam seluruh ketidakteraturannya yang organik—berdiri di luar skema distribusi resmi. Mereka tidak meneken kontrak dengan label besar, tidak bermain di chart tangga lagu, dan tak peduli pada sistem royalti atau algoritma pemutaran radio. Sistem orkes adalah sistem guerilla: mereka hadir langsung ke hadapan masyarakat, mencetak kaset atau CD sendiri, menjual langsung di lapak-lapak, atau bahkan menggandakan lewat tukang burning komputer di pinggir jalan.
Sementara itu, label industri memainkan politik pasar yang berbeda. Mereka menyaring siapa yang bisa masuk ke pasar melalui proses seleksi, kurasi selera, dan strategi pencitraan. Musik tidak lagi lahir dari pengalaman kolektif, tapi dari rapat strategi marketing. Eksklusivitas menjadi kunci. Inilah yang menjadi pembeda mendasar: orkes berusaha membuka ruang, sementara industri kerap kali menutupnya demi menjaga segmentasi konsumen dan prestige produk.
Televisi swasta hanya memberikan ruang pada jenis dangdut yang telah dikemas ulang: bersih, estetis, dan sesuai selera kota. Orkes dangdut pasar malam yang liar, dengan improvisasi dan kebisingan khas rakyat, dianggap tak cocok untuk layar kaca. Theodor W. Adorno, dalam kritik kerasnya terhadap industri budaya, menyatakan bahwa media massa mengubah seni menjadi komoditas, menciptakan “musik ringan” yang jinak dan seragam demi mengontrol selera massa. Dalam logika ini, orkes terlalu liar untuk dijinakkan, terlalu hidup untuk diseragamkan.
Jacques Attali dalam bukunya Noise: The Political Economy of Music menyebut bahwa musik adalah ramalan tentang masa depan masyarakat. Musik rakyat seperti orkes, yang menolak dikendalikan pasar, merupakan bentuk awal dari perlawanan terhadap logika ekonomi dominan. “Di balik musik, terdapat kekuasaan yang sedang diperebutkan,” tulis Attali.
Justru karena itulah, orkes dianggap berbahaya oleh sistem. Ia bukan sekadar kompetitor ekonomi, tapi gangguan ideologis terhadap tata rasa dan pasar yang telah dikuasai industri. Namun orkes tidak meminta pengakuan dari sistem. Mereka terus hidup karena rakyat membutuhkannya—bukan karena stasiun TV menayangkannya atau karena influencer membicarakannya.

—
Penutup: Orkes sebagai Jalan Ketiga Budaya
Dalam keberadaannya yang terus bertahan dari dekade ke dekade, orkes dangdut telah menjelma lebih dari sekadar hiburan. Ia adalah jalan ketiga dari budaya populer Indonesia—bukan budaya pop modern yang disuapi algoritma media sosial, bukan pula budaya tinggi yang hanya bisa dinikmati kaum berpendidikan. Ia adalah budaya yang hidup, bergerak, dan melekat dalam denyut kehidupan rakyat kecil.
Orkes juga memperlihatkan bagaimana sistem-sistem kolektif alternatif dapat bekerja di luar kontrol negara dan korporasi. Dari sistem produksi live performance, distribusi kaset/CD mandiri, hingga hubungan simbiosis dengan pasar malam dan ekonomi mikro, semua menunjukkan bahwa gerakan rakyat tidak mati. Mereka hanya tidak tampil di kanal-kanal resmi.
Dalam dunia yang semakin digital dan steril, orkes mengingatkan kita pada pentingnya ruang-ruang fisik dan sosial di mana interaksi, ekspresi, dan ekonomi bisa tumbuh secara organik. Orkes adalah suara akar rumput yang menolak dibungkam. Ia mungkin tak tampil di layar televisi nasional, tapi ia hidup dalam semesta pasar malam, lapangan desa, dan memori kolektif rakyat kecil.
Maka dari itu, siapa pun yang ingin memahami denyut kebudayaan Indonesia sesungguhnya, tak bisa hanya berkunjung ke galeri seni dan festival musik urban. Ia harus datang ke pasar malam, menyaksikan orkes yang tampil semalaman, dan melihat bagaimana rakyat menyusun makna hidup mereka di atas panggung tiban, di tengah debu, dan di antara riuh tawa yang tak kenal protokol.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini adalah bagian dari usaha redaksi Narrative Readout untuk menggali narasi-narasi kultural yang terpinggirkan, tetapi vital dalam lanskap kebudayaan Indonesia. Orkes dangdut adalah satu dari sekian banyak wajah perlawanan diam yang layak mendapat ruang dan penghargaan lebih dalam diskursus budaya.


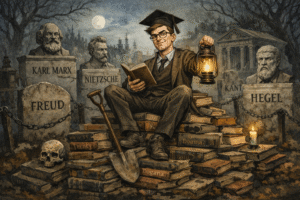



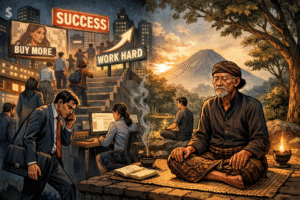





Be First to Comment