Esai
Esai kritis membongkar logika palsu negara yang tiba-tiba mematok tanah rakyat dan menarik pajak, menyingkap kesakralan palsu negara atas warganya.
Negara, Patok Tanah, dan Dogma Kesakralan yang Absurd
Bayangkan suatu pagi yang biasa. Udara masih lembab, ayam berkokok, dan seorang bapak tua sedang menyapu halaman rumahnya—tanah yang ia rawat sejak muda, tempat ia menanam pohon mangga warisan ayahnya. Tiba-tiba, datanglah rombongan orang berseragam. Ada yang membawa meteran, ada yang memegang patok kayu, ada yang sibuk mencatat di map lusuh dengan stempel resmi. Tanpa basa-basi mereka menancapkan patok di tanah, menulis angka koordinat, dan mengumumkan: “Mulai hari ini tanah ini masuk wilayah administrasi negara, dan bapak diwajibkan membayar pajak sekian rupiah setiap tahun.” Mereka pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Seolah itu adalah hal wajar, seolah itu kodrat. Padahal, bagi si pemilik tanah, yang terjadi sungguh absurd: siapa mereka hingga bisa menentukan harga hidup yang ia jalani di tanah ini?
Di sinilah kita melihat wajah telanjang dari apa yang disebut negara. Entitas yang katanya lahir dari konsensus sosial, yang semula dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur, melindungi, dan memudahkan kehidupan bersama, kini berubah menjadi semacam dewa kecil. Negara bukan lagi sekadar perangkat, melainkan sesuatu yang dianggap lebih sakral daripada manusia itu sendiri. Lebih sakral daripada tanah yang kita pijak, lebih sakral daripada keringat yang menetes ketika kita menanam, membangun, atau sekadar bertahan hidup.
Masalahnya bukan hanya tentang pajak atau patok tanah. Masalahnya lebih dalam: negara telah menjadi simulakra—tiruan yang lebih nyata dari realitas itu sendiri. Ia diciptakan manusia, tetapi kemudian tampil seakan-akan lebih berhak, lebih penting, bahkan lebih “nyata” daripada manusia yang menciptakannya. Ketika simbol-simbol negara—bendera, lambang, lagu kebangsaan—dianggap lebih sakral daripada kehidupan rakyat, maka jelas ada yang terbalik. Kita sedang menyembah ciptaan kita sendiri, lalu menganggapnya lebih tinggi dari penciptanya.
Negara pada dasarnya hanyalah kesepakatan. Sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah merasa perlu menata kehidupan bersama, lalu mereka membuat aturan, menunjuk pengurus, menyepakati batas, lalu menamai dirinya: negara. Tidak ada hukum alam yang mewajibkan itu. Tidak ada petir yang menyambar lalu menciptakan negara dari langit. Negara adalah “mengada-adakan” manusia, sebuah kontruksi sosial belaka. Tapi, karena ia terus diulang dalam wacana, dalam buku pelajaran, dalam upacara bendera, dalam propaganda televisi, lama-lama ia terasa seperti sesuatu yang absolut.
Inilah falasi pertama: kita menganggap negara itu kodrat, padahal ia ciptaan. Karena dianggap kodrat, maka rakyat harus tunduk tanpa syarat. Negara menagih pajak, rakyat bayar. Negara mengatur tanah, rakyat ikut. Negara menyatakan sesuatu “demi martabatnya”, rakyat diminta mengorbankan diri. Dengan kata lain, negara yang seharusnya tunduk pada rakyat, justru memosisikan rakyat tunduk padanya.
Mari kita bedah absurditas ini lewat contoh paling sederhana: tanah.
Bagi masyarakat, tanah bukan sekadar objek ekonomi. Ia adalah ruang hidup. Di tanah itulah orang menanam padi, membangun rumah, membesarkan anak, mengubur leluhur. Tanah adalah memori, tubuh, dan identitas. Tapi bagi negara, tanah hanyalah objek administrasi: berapa luasnya, di mana letaknya, berapa nilai pajaknya. Maka tanah yang nyata, yang dipelihara dan dihidupi, dikalahkan oleh tanah versi peta, versi sertifikat, versi dokumen.
Inilah simulakra bekerja: representasi (dokumen, peta, sertifikat) menjadi lebih berkuasa daripada realitas. Sebidang tanah yang sudah ditempati keluarga selama puluhan tahun bisa dianggap “tidak sah” hanya karena tidak ada sertifikat. Sebaliknya, tanah yang bahkan belum disentuh bisa dianggap sah milik perusahaan karena ada dokumen yang disahkan negara. Fakta sosial kalah oleh fakta administrasi. Dan administrasi adalah bahasa yang dimonopoli negara.
Lalu muncullah dalih pajak. Pajak disebut iuran gotong royong, kontribusi warga untuk membangun sekolah, jalan, jembatan, rumah sakit. Sekilas terdengar indah. Tapi coba periksa realitas: rakyat membayar dengan disiplin, sementara negara seenaknya mengalokasikan anggaran. Transparansi minim, akuntabilitas lemah, dan ketika rakyat bertanya, jawabannya normatif: “pembangunan membutuhkan biaya.” Di sini kita lihat falasi kedua: negara berlagak sebagai kontraktor publik, tapi menolak diperlakukan sebagai kontraktor. Kontraktor bisa ditagih hasil kerjanya, bisa digugat bila ingkar janji. Negara menagih pajak, tapi marah jika ditanya: “mana hasilnya?”
Yang lebih menjengkelkan, negara menempelkan dogma moral pada tindakan teknisnya. Tidak bayar pajak dianggap dosa sipil. Memprotes pematokan tanah dibaca sebagai ancaman kedaulatan. Kritik terhadap negara dipelintir jadi “tidak cinta tanah air”. Seakan-akan menolak pungutan tidak adil sama artinya dengan menghina bendera. Inilah falasi ketiga: kesakralan simbol dipakai untuk membungkam kritik substantif.
Simbol memang penting—bendera, lagu kebangsaan, lambang negara bisa mengikat rasa kebersamaan. Tapi ketika simbol naik derajat menjadi fetisisme, ia berubah jadi senjata ideologis. Rakyat tidak boleh bertanya soal ketidakadilan, karena dianggap melukai simbol. Padahal justru demi cinta tanah air rakyat menolak dijajah negara. Cinta tanah air itu cinta pada tanah dan manusia, bukan cinta pada kertas, patok, atau stempel.
Kita harus berani membalik logika ini. Negara adalah alat, bukan tujuan. Negara ada karena manusia menciptakannya, bukan sebaliknya. Negara hanya sah sejauh ia menghormati manusia, melindungi tanah mereka, dan memberi layanan yang adil. Begitu negara lupa posisinya, ia berubah menjadi predator.
Pematokan tanah dan pemungutan pajak adalah wajah paling gamblang dari predator ini. Ia datang tiba-tiba, membawa meteran dan stempel, menancapkan patok, lalu menuntut bayaran. Semua atas nama hukum, padahal hukum adalah ciptaannya sendiri. Negara menulis aturan, lalu memaksa rakyat tunduk pada aturan yang ia buat. Itulah lingkaran setan: negara membuat hukum, hukum membenarkan negara, dan rakyat terjepit di antaranya.
Sebagian orang mungkin berkata: tanpa pajak, bagaimana jalan dibangun? bagaimana sekolah berdiri? bagaimana rumah sakit berjalan? Argumen ini tampak logis, tapi sebenarnya menyesatkan. Pajak memang diperlukan, tapi harus tunduk pada logika kontraktual: rakyat membayar, negara melayani. Jika negara tidak melayani, rakyat berhak menolak. Ini prinsip sederhana, seperti kita membayar tukang. Kita tidak mungkin membayar tukang yang tidak mengerjakan apa-apa. Tapi logika negara justru sebaliknya: rakyat tetap harus membayar, meskipun tukang malas, korup, atau mangkir. Dan ketika rakyat menolak, mereka dituduh subversif.
Kita perlu menyadari dimensi psikologis dari kesakralan negara. Banyak orang merasa aman berlindung di bawah payung negara. Ada kebanggaan saat menyanyikan lagu kebangsaan, ada rasa haru saat bendera dikibarkan. Itu wajar, itu kebutuhan manusiawi akan identitas kolektif. Tapi di tangan penguasa, rasa itu sering dipelintir. Ia dipakai untuk menutupi ketidakadilan, dipakai untuk membungkam suara kritis. Identitas kolektif yang seharusnya menguatkan rakyat, justru dijadikan alat legitimasi bagi negara untuk menindas rakyatnya sendiri.
Jadi, apa yang harus dilakukan?
Pertama, bongkar simulakra. Ingatkan terus bahwa negara hanyalah ciptaan manusia. Ia bukan dewa, bukan kodrat. Ia hanya alat. Kedua, tegakkan kontrak sosial. Pajak sah hanya bila ada layanan nyata, bukan janji kosong. Ketiga, runtuhkan kesakralan palsu. Kritik bukan pengkhianatan, melainkan bentuk tertinggi dari cinta tanah air. Keempat, pastikan tanah kembali dipahami sebagai ruang hidup, bukan sekadar objek administrasi. Dokumen dan peta harus tunduk pada kenyataan sosial, bukan sebaliknya.
Mari kembali ke halaman kecil bapak tua tadi. Jika suatu hari aparat datang lagi, mereka harus datang dengan wajah berbeda. Bukan sebagai tuan yang memerintah, tapi sebagai tamu yang meminta izin. Bukan dengan stempel dan ancaman, tapi dengan penjelasan dan musyawarah. Pematokan tanah seharusnya bukan tanda kuasa, melainkan tanda kesepakatan. Pajak seharusnya bukan upeti, melainkan kontrak layanan yang bisa ditagih rakyat.
Negara tidak perlu dihapus. Yang perlu dihapus adalah aura kesakralannya. Begitu kesakralan itu runtuh, negara akan kembali ke wujud aslinya: sekumpulan manusia yang digaji rakyat untuk bekerja bagi rakyat. Mereka bukan dewa, dan kita bukan umat. Kita adalah warga, dan tanah tempat kita berpijak lebih tua daripada semua lambang negara. Hormatilah tanah dan manusia yang menghidupinya, maka negara akan menemukan martabatnya yang sejati: bukan martabat yang menuntut sujud, melainkan martabat yang lahir dari kesetiaan pada tugas melayani.
Dan jika suatu hari patok harus berdiri, biarlah ia berdiri bukan sebagai bekas luka, melainkan sebagai tanda persetujuan yang adil.


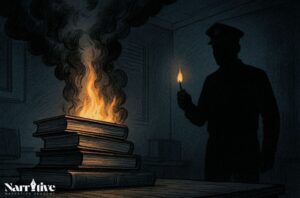
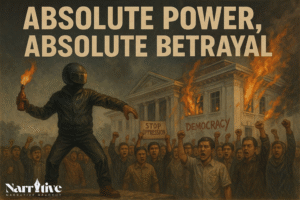
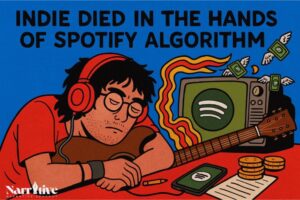

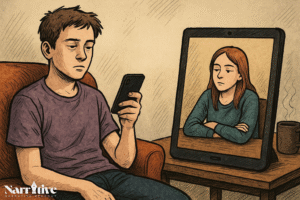
Be First to Comment