Opini
Lagu “Tarik Tambang” dari Methosa menyuarakan perlawanan terhadap perampasan hutan, tanah adat, dan ilusi investasi tambang di Indonesia.
“Tarik Tambang” Methosa: Ketika Lagu Menjadi Teriakan Terakhir untuk Tanah yang Dirampas
“Wey, ada maling!”
Di banyak tempat di Indonesia, teriakan ini bukan cuma peringatan tentang maling motor atau copet. Ia kini juga bisa berarti sesuatu yang jauh lebih besar dan sistemik: perusahaan tambang yang mencaplok hutan adat, menggusur warga, lalu meninggalkan lubang-lubang raksasa yang menganga di tanah ibu.
Babak Pertama: Lagu Protes di Tengah Surga yang Dilucuti
Methosa, band indie yang selama ini bergerilya dengan napas protes sosial dan politik, baru saja melepas sebuah lagu dengan judul sederhana namun penuh makna: “Tarik Tambang.” Sepintas, judulnya terdengar seperti lomba agustusan. Tapi jangan salah—lagu ini bukan tentang lomba, melainkan tentang kalahnya rakyat dalam permainan kuasa atas tanah.
Di dalam lagu ini, Methosa merangkum keresahan selama puluhan tahun: tanah adat yang digusur, hutan yang dibabat, janji investasi yang palsu, dan rakyat yang selalu jadi penonton dalam pesta pora sumber daya alam.
Hutan Diganti Tambang, Rakyat Diganti Statistik
“Miliaran kilo sejak puluhan tahun / Mereka mengeruk tanah beruntun / Hutan kini berubah jadi gurun / Kita dikibulin turun temurun”
Tak butuh waktu lama bagi pendengar untuk menangkap arah lagu ini. Kalimat pembuka Methosa langsung menggambarkan realitas sosial-ekologis yang akrab di banyak wilayah Indonesia. Dari Kalimantan ke Papua, dari Sulawesi hingga Sumatra, tanah-tanah adat dan hutan tropis yang dulunya kaya raya kini berubah jadi lahan tambang dan lubang maut.
kita bisa bilang: ini bukan pembangunan, ini kolonialisme versi upgrade.
Narasi Lama, Luka Baru
“Ini lagu lama modus investasi / Rakyat sejahtera hanyalah ilusi”
Frasa ini menyindir narasi usang yang selalu diputar ulang dalam pidato-pidato peresmian tambang: “akan membuka lapangan kerja”, “meningkatkan pendapatan daerah”, “mempercepat pembangunan”.
Sayangnya, kita tahu bagaimana ending-nya: yang kaya makin kaya, yang miskin kehilangan tanah.
Methosa mengangkat ironi itu secara vulgar tapi jujur. Bahwa model pembangunan berbasis ekstraksi ini sudah terlalu sering membuktikan kegagalannya. Tapi tetap saja kita percaya. Atau mungkin, kita dipaksa percaya?
“Wey Ada Maling!”: Ketika Teriakan Menjadi Senjata
Inilah bagian paling memorable dari lagu ini—teriakan berulang “Wey ada maling!” diiringi ketukan yang repetitif, seolah-olah sedang mengajak pendengar untuk bergabung dalam demonstrasi jalanan.
Teriakan ini bukan cuma gimmick. Dalam konteks budaya Indonesia, menyebut seseorang “maling” adalah bentuk puncak kemarahan sosial. Methosa mengubahnya jadi mantra politik. Mereka tidak sedang bicara tentang maling perhiasan. Mereka bicara soal pencurian yang lebih licik—pencurian hutan, pencurian laut, pencurian hak hidup.
Lagu ini ingin kita sadar bahwa kita sedang dirampok. Tapi beda dengan maling biasa, yang ini datang dengan izin pemerintah dan didampingi alat berat.
“Masuk Bawa Alat Berat”: Simbol Invasi Korporasi
“Masuk bawa alat berat / Ambil alih hutan adat”
Kalimat ini sederhana tapi keras. Ia menggambarkan bagaimana kekerasan struktural bekerja: tidak selalu lewat tentara, kadang cukup dengan ekskavator, peta konsesi, dan surat keputusan pejabat.
Selama dua dekade terakhir, lebih dari 12 juta hektare hutan di Indonesia telah hilang, sebagian besar karena izin pertambangan dan perkebunan. Seringkali, lahan-lahan itu adalah milik masyarakat adat yang tak punya kekuatan hukum karena negara enggan mengakuinya.
“Dulang Uang, Mereka Pulang, Kita Terbuang”
Salah satu bagian paling menyakitkan dari lagu ini adalah ketika Methosa menyimpulkan seluruh ironi itu dalam satu baris:
“Bangun tambang, dulang uang, mereka pulang, dan kita terbuang”
Begitulah logika kapitalisme ekstraktif bekerja: ambil yang bisa diambil, tinggalkan sisanya. Setelah kekayaan bumi dikeruk, yang tersisa hanyalah tanah rusak, konflik sosial, dan generasi muda yang tidak lagi punya tanah untuk ditanami atau air untuk diminum.
Musik yang Jadi Medium Peringatan
Lagu “Tarik Tambang” bukan hanya tentang lirik. Secara musikal, Methosa menciptakan atmosfer yang mendesak: repetisi chant “na-na-na” seolah menyuarakan amarah kolektif. Iramanya mendekati anthem, cocok untuk diteriakkan di depan gedung DPR atau saat aksi di tambang.
Dan ini bukan kali pertama musik dipakai sebagai alat perlawanan.
Dari Fela Kuti di Nigeria, Rage Against the Machine di Amerika, sampai Navicula dan Efek Rumah Kaca di Indonesia—musik telah lama menjadi ruang alternatif bagi mereka yang suaranya dikalahkan oleh media arus utama dan uang iklan.
Methosa: Dari Pinggiran, Suara yang Menggelegar
Karya terbaru mereka memiliki bobot politis yang tak bisa diabaikan. Methosa tidak cuma bikin musik, mereka sedang membangun kesadaran. Dan seperti yang kita tahu, kesadaran adalah musuh paling berbahaya bagi sistem yang korup.
Dengan “Tarik Tambang”, mereka mengukuhkan diri sebagai bagian dari tradisi musik perlawanan di Indonesia. Sebaris dengan Iwan Fals, Marjinal, Navicula, hingga musisi-musisi lokal di kampung-kampung yang menggunakan gitar bolong untuk menyuarakan ketidakadilan.
Mengapa Kita Harus Peduli?
Karena cerita dalam lagu ini bukan fiksi. Kita hidup di negara yang memiliki 13% cadangan nikel dunia, tapi masih punya desa-desa tanpa listrik.
Kita punya ribuan tambang, tapi jutaan warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Kita mengekspor batu bara dalam jumlah masif, tapi anak-anak di Kalimantan harus belajar di bawah atap sekolah yang nyaris rubuh akibat truk tambang.
Dan sekarang, ketika Methosa membuat lagu tentang itu semua, masa iya kita hanya diam dan menyukai postingan mereka di Instagram?
Ketika Lagu Jadi Senjata, Diam Adalah Kekalahan
“Tarik Tambang” bukan sekadar karya seni. Ia adalah pengingat keras: bahwa kita sedang dalam perang—perang memperebutkan ruang hidup, identitas, dan masa depan.
Dan seperti dalam permainan tarik tambang yang sesungguhnya, jika kita tidak menarik, kita akan terseret. Kalah. Tertinggal. Terbuang.
Apa Selanjutnya?
1. Dengarkan lagunya. Bukan cuma satu kali, tapi berulang-ulang.
Biarkan kata-kata itu menempel di kepala. Teriakan “wey ada maling!” bisa jadi nyanyian internalmu saat melihat berita tentang tambang baru yang merusak hutan lagi.
2. Sebarkan.
Jadikan lagu ini bagian dari aksi—entah itu di story Instagram, forum kampus, atau obrolan tongkrongan. Biarkan musik bergerak bebas dan liar seperti semangat yang dikandungnya.
3. Jangan lupa siapa yang dirugikan.
Di balik tiap konsesi tambang, ada keluarga yang kehilangan rumah, ada hutan yang lenyap, ada mata air yang mengering. Kita tidak boleh lupa.
Akhir Kata: Methosa Telah Bernyanyi, Tugas Kita untuk Mendengarkan dan Bergerak
Lagu ini mungkin tidak akan diputar di stasiun radio nasional. Ia terlalu jujur. Terlalu berani. Terlalu berbahaya bagi mereka yang nyaman dalam kekuasaan.
Tapi justru karena itulah kita harus menjadikannya nyanyian kita.
Karena jika kita tidak menyanyikannya, siapa lagi?


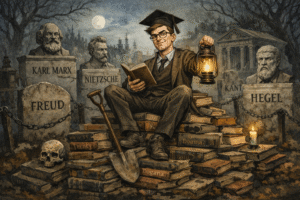

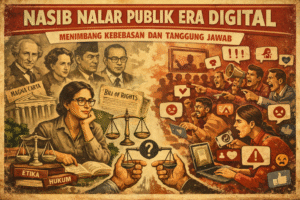


Be First to Comment