Opini
Artikel ini mengupas secara tajam posisi Multatuli sebagai kolonial yang penuh privilese dalam novelnya Max Havelaar, serta bagaimana karya itu merefleksikan kemunafikan moral ala kolonialis. Dilengkapi refleksi kontemporer tentang “Havelaarisme” dalam dunia NGO, aktivisme, dan politik.
Multatuli dan Warisan Ambivalensi Kolonial: Membongkar Kemunafikan Moral dalam Max Havelaar
Dalam sejarah kesusastraan kolonial, nama Multatuli alias Eduard Douwes Dekker seringkali dielu-elukan sebagai pelopor kesadaran antikolonialisme. Karyanya yang monumental, Max Havelaar (1860), dianggap sebagai titik balik dalam upaya membuka mata dunia terhadap praktik brutal kolonial Belanda di Hindia Timur. Namun pujian tersebut tidak boleh mengaburkan kenyataan mendasar: Multatuli tetaplah seorang kolonialis. Ia adalah bagian dari sistem yang menindas dan mengeksploitasi rakyat Hindia. Max Havelaar bukanlah sebuah karya revolusioner dalam pengertian praksisnya; ia lebih menyerupai pengakuan bersyarat dari seorang kolonial yang terganggu nuraninya, tetapi enggan menanggalkan privilese dan posisinya dalam struktur penjajahan.
Ketika membaca Max Havelaar, pembaca seakan diajak menyelami penderitaan rakyat di Lebak, Banten, melalui perspektif seorang asisten residen idealis bernama Havelaar. Ia menentang korupsi para bupati lokal dan kelambanan sistem kolonial Belanda dalam melindungi rakyat. Namun, penolakan ini tetaplah terbingkai dalam semangat paternalistik: rakyat Hindia dilukiskan sebagai objek penderitaan yang memerlukan penyelamatan dari seorang Eropa yang tercerahkan. Dalam hal ini, Multatuli tetap meneguhkan hierarki kolonial. Ia tidak benar-benar membongkar sistem, melainkan sekadar mengritiknya dari dalam sambil terus berdiri di dalamnya.
Privilegi Multatuli sebagai seorang kolonial tidak bisa dipisahkan dari cara pandangnya dalam menulis Max Havelaar. Ia adalah pegawai tinggi kolonial yang memiliki opsi untuk pergi dari Hindia jika merasa tidak nyaman. Dan memang, itulah yang ia lakukan: setelah gagal memperbaiki keadaan di Lebak, ia memilih kembali ke Belanda, membawa serta kisah “heroiknya” untuk dijual sebagai literatur. Inilah bentuk kemunafikan moral yang harus disorot: seseorang yang terlibat langsung dalam sistem penjajahan, menikmati gaji dan statusnya, tetapi ketika sistem itu membuatnya tidak nyaman, ia keluar dan menjadikannya sebagai bahan narasi penebusan diri.
Multatuli tidak pernah benar-benar membayar harga politik atau moral atas penderitaan yang ia saksikan. Ia tidak menjadi revolusioner, tidak tinggal untuk berjuang bersama rakyat Hindia, dan tidak mengguncang struktur kekuasaan kolonial secara sistematis. Ia lebih tepat disebut sebagai whistleblower yang aman: menggonggong dari luar setelah keluar dari kandang yang memberinya makan. Novel Max Havelaar tidak ditulis untuk rakyat Hindia; ia ditujukan kepada para pemilih Belanda, untuk mempengaruhi opini publik Eropa—bukan untuk membebaskan kaum tertindas.
Di sinilah pentingnya membedakan antara narasi moral dan tindakan politis. Multatuli, melalui Havelaar, menunjukkan simpati moral, tetapi tidak keberpihakan politik. Ia mencela ketidakadilan, tetapi tidak menyerukan pembongkaran sistem kolonial. Bahkan dalam keberaniannya, ia tetap berada dalam kerangka borjuis: perhatiannya pada prosedur, norma hukum, dan moralitas Kristen-Eropa menjadi penanda bahwa perjuangannya tidak pernah dimaksudkan untuk radikal.
Sebagai perbandingan, tokoh-tokoh kolonial lain seperti Conrad Theodor van Deventer atau bahkan Seneviratne di wilayah kolonial lain menunjukkan ambivalensi yang berbeda. Mereka menyadari kebobrokan sistem kolonial dan kemudian berkontribusi secara material terhadap pendidikan atau infrastruktur lokal. Tentu ini tidak menyelesaikan persoalan kolonialisme, tetapi menunjukkan keinginan untuk menebus dosa kolonial secara praksis. Multatuli, sebaliknya, tetap menjual pengalaman kolonialnya sebagai produk sastra, sebagai pengakuan moral yang diam-diam meningkatkan kredibilitas dirinya di mata Barat.
Jika kita membaca Edward Said dalam Orientalism (1978), kita dapat memahami bagaimana Max Havelaar tetap terjebak dalam bingkai representasi kolonial. Multatuli, bagaimanapun, adalah produk dari cara pandang Barat yang merasa berhak berbicara untuk yang Timur. Ia menjadi juru bicara bagi suara-suara yang tidak terdengar, tetapi dengan cara yang membuatnya tetap dominan. Dalam istilah Said, ini adalah “kekuasaan untuk mewakili” yang menjadi inti dari orientalisme: mengklaim empati, namun mengukuhkan superioritas.
Multatuli mungkin tidak sebrutal para administrator kolonial lainnya, tetapi ia tetaplah bagian dari mesin itu. Dan ini perlu ditekankan: bahwa keberpihakan sejati terhadap rakyat tertindas tidak cukup hanya dengan narasi, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam pilihan hidup, dalam pengorbanan privilese. Multatuli tidak menolak kolonialisme sebagai struktur; ia hanya menolak kekejamannya yang berlebihan. Seperti seseorang yang hidup dalam rumah besar hasil perampokan, lalu merasa bersalah karena melihat tetangganya kelaparan, tetapi tetap tinggal di rumah itu, hanya menuliskan catatan harian tentang perasaannya.
Analogi yang lebih dekat dengan konteks hari ini: Multatuli seperti seorang pejabat dalam sistem korup, yang tahu betul bobroknya sistem, lalu menuliskan status panjang di media sosial tentang pentingnya integritas, sambil tetap menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas dari sistem yang ia kecam. Ia tidak membocorkan dokumen rahasia, tidak memobilisasi rakyat untuk turun ke jalan, dan tidak memutuskan hubungan dengan struktur kekuasaan. Ia hanya menyuarakan keresahannya—dan itupun dalam bentuk sastra yang dijual kepada pasar Eropa.
Dalam refleksi ini, kita dapat menyebut fenomena semacam ini sebagai Havelaarisme: bentuk kemunafikan moral yang tampak progresif, tetapi sebenarnya hanya meneguhkan status quo. Havelaarisme adalah ketika seseorang mengecam sistem yang memberinya keuntungan, tetapi enggan melepaskan privilese tersebut. Kita bisa melihatnya pada banyak aktivis lingkungan yang bekerja untuk NGO yang dibiayai oleh perusahaan-perusahaan perusak lingkungan. Atau pada politisi yang bicara tentang keadilan sosial tetapi menikmati fasilitas kelas elite. Atau para akademisi yang berbicara lantang tentang dekolonisasi sambil membangun karier di institusi warisan kolonial. Havelaarisme adalah kamuflase moral yang tidak mengganggu akar masalah, melainkan sekadar memperindah permukaannya.
Kita tidak perlu meragukan bahwa Multatuli memiliki empati. Namun empati saja tidak cukup untuk membebaskan. Yang diperlukan adalah keberanian untuk merombak sistem, bukan hanya mendokumentasikan luka. Dalam hal ini, Multatuli tetaplah seorang kolonialis yang gelisah, bukan pejuang pembebasan. Ia bukan lawan kolonialisme, hanya saksi yang kecewa.
Kesimpulan ini mengajak kita untuk melihat lebih jernih tentang siapa yang berbicara, dari posisi mana ia berbicara, dan untuk kepentingan siapa ia menulis. Kita tidak bisa terus memuji Multatuli hanya karena ia lebih “manusiawi” dari rekan-rekan kolonialnya. Karena pada akhirnya, Max Havelaar tetaplah catatan dari seorang penguasa tentang mereka yang dikuasai. Bukan suara rakyat, tapi gema dari ruang-ruang kekuasaan Eropa yang sedang bergulat dengan rasa bersalahnya sendiri.

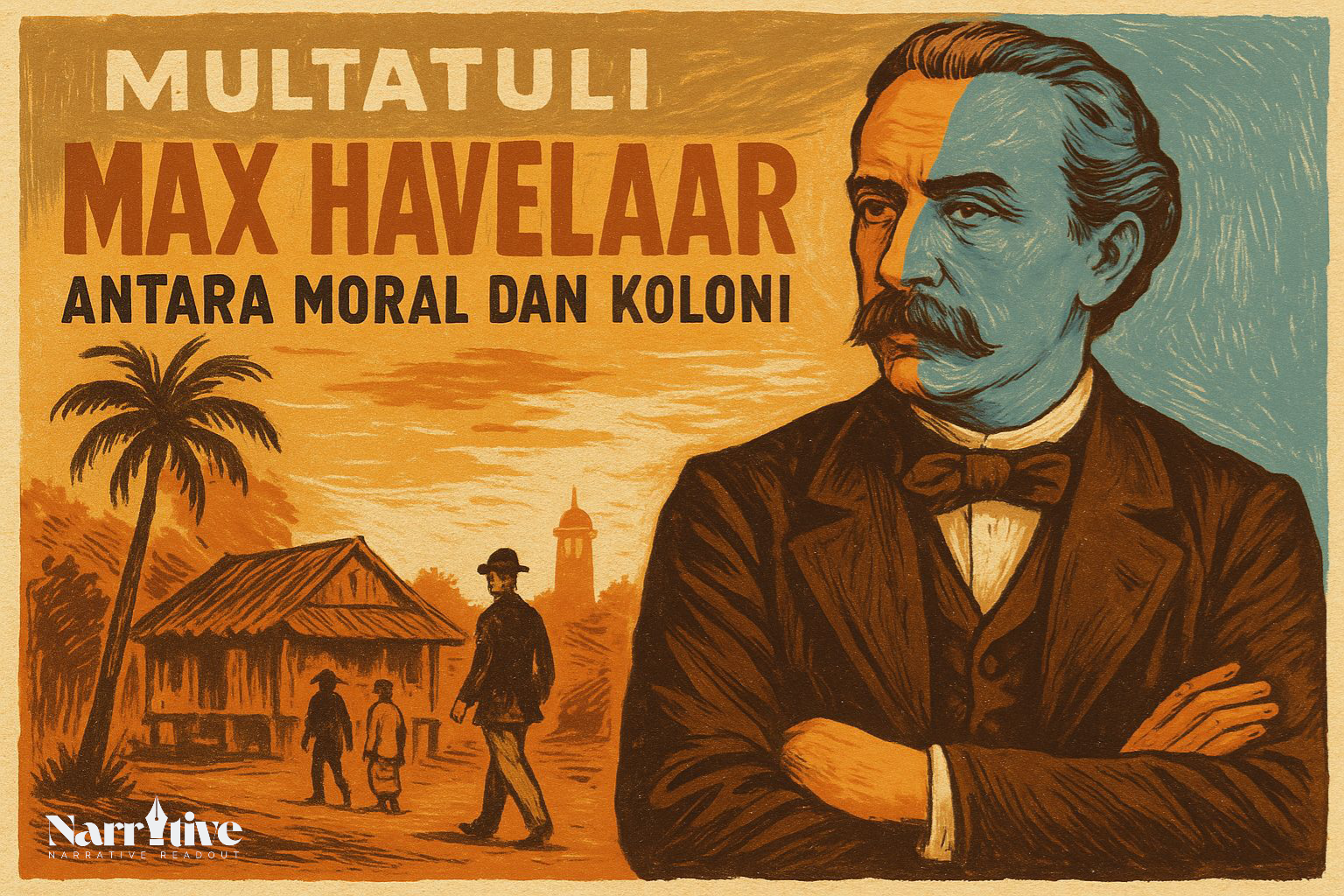
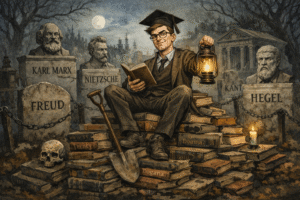

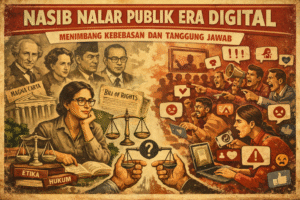


Be First to Comment