Opini
Artikel ini adalah dukungan terhadap sikap etis para pegiat budaya yang memilih mundur dari struktur kaku demi membangun kebudayaan yang partisipatif, membumi, dan merdeka dari kooptasi politik.
Keluar dari Struktur, Kembali ke Akar: Dukungan untuk Perlawanan Budaya dari Bawah
“Tidak diam. Kami memilih bicara, karena jika kami terus bertahan, maka kami turut mengukuhkan kebusukan yang seharusnya dilawan.” Kalimat dari tulisan Probo Darono Yakti ini tidak hanya sebuah ekspresi keberanian, tapi juga sebuah tamparan halus terhadap kita semua yang pernah, atau masih, terjebak dalam kebisuan struktural yang disfungsional. Di balik narasinya, terdapat pesan kuat tentang perlunya meninjau ulang bagaimana kebudayaan dikelola, dihidupi, dan dikawal.
Tulisan ini kami buat sebagai bentuk dukungan terhadap pilihan Probo dan banyak pegiat budaya lainnya yang memutuskan untuk keluar dari struktur. Bukan karena menyerah. Bukan karena anti institusi semata. Tapi karena kesadaran bahwa dalam struktur yang kaku dan semakin menjauh dari akar, ide-ide segar justru terancam punah. Dan ketika struktur tak lagi memberi ruang, maka keluar darinya adalah tindakan etis. Tindakan yang lahir dari cinta dan tanggung jawab.
Budaya Bukan Proyek, Tapi Proses
Selama bertahun-tahun, banyak dari kita percaya bahwa pemajuan kebudayaan hanya bisa terjadi lewat program-program resmi: proposal, audiensi, koordinasi lintas sektor, dan seremonial. Tapi realitasnya, kita semakin menyaksikan bagaimana ruang-ruang itu justru menyingkirkan substansi. Makna kebudayaan direduksi menjadi daftar kegiatan tahunan, kalender event, atau konten promosi daerah.
Pendekatan birokratis ini menjebak para pegiat dalam logika kuantitatif: berapa kegiatan terlaksana, berapa peserta yang hadir, berapa output yang tercapai. Tapi apa makna yang hidup di sana? Siapa yang benar-benar merasakan perubahan dari dalam? Apakah warga kampung, anak muda desa, atau hanya segelintir elite yang bicara atas nama kebudayaan rakyat?
Lebih jauh lagi, orientasi proyek membuat kerja budaya kehilangan dimensi jangka panjang. Ketika kebudayaan dibatasi oleh siklus anggaran tahunan, maka tidak akan pernah ada kontinuitas nilai. Gagasan hanya dipanen untuk laporan, bukan ditumbuhkan sebagai visi. Di sinilah kita belajar bahwa struktur yang terlalu prosedural justru menjadi kuburan bagi gagasan-gagasan progresif.
Kritik terhadap Birokratisasi Kebudayaan
Pendekatan struktural dalam pengelolaan budaya seringkali mematikan dinamika lokal. Semua harus seragam, semua harus tunduk pada format pelaporan, semua harus sesuai arahan pusat. Padahal, budaya itu hidup dari konteks, dari spontanitas, dari eksperimen. Ketika semua dipaksa masuk dalam sistem yang baku, yang terjadi adalah stagnasi.
Lebih parah lagi, seringkali keputusan strategis diambil bukan oleh para pelaku budaya itu sendiri, tetapi oleh aktor-aktor politik atau birokrat yang tidak hidup di dalam realitas komunitas. Ini yang disebut oleh Boaventura de Sousa Santos sebagai bentuk “epistemicide”—pembunuhan terhadap pengetahuan lokal yang tidak sesuai dengan logika institusi formal.
Sering kita jumpai: tradisi lokal yang masih hidup dianggap tidak valid hanya karena tidak terdokumentasi secara formal. Sebaliknya, upacara yang dibuat-buat untuk proyek justru dianggap lebih “berbudaya”. Ini adalah paradoks yang menghina nalar, sekaligus mempermalukan akar-akar kebudayaan itu sendiri.
Maka keluar dari struktur bukanlah bentuk anti-kemajuan, tetapi cara untuk menyelamatkan kreativitas dari kepunahan.
Etika Perlawanan: Mundur untuk Menumbuhkan
Di tengah atmosfer politik kebudayaan yang penuh kooptasi, mundur adalah tindakan yang radikal. Ia bukan kekalahan, tapi pembebasan. Probo menyebut ini sebagai bentuk kesadaran etis. Saya sepakat. Karena dalam banyak kasus, bertahan dalam sistem yang membusuk justru memperpanjang usia kebusukan itu sendiri.
bell hooks menyebut pentingnya menciptakan “ruang terbuka radikal”—ruang yang bebas dari dominasi dan memungkinkan munculnya cara berpikir baru. Keluar dari struktur menciptakan ruang itu. Ruang tempat ide bisa bernafas, tempat gagasan bisa berbenturan tanpa sensor, tempat perbedaan bisa dirayakan tanpa takut kehilangan akses.
Di balik tindakan mundur itu, ada refleksi panjang. Ada percakapan malam yang tak kunjung usai dengan sesama pegiat. Ada perasaan bersalah dan pertimbangan etis tentang siapa yang akan terdampak. Tetapi justru karena itu, sikap ini menjadi penting. Karena dilakukan bukan demi posisi, melainkan demi menjaga integritas nilai.
Bersikap adalah Tindakan Kebudayaan
Dalam dunia yang semakin menyamakan kebudayaan dengan program kerja dan laporan kegiatan, tindakan personal seperti yang dilakukan Probo adalah oase. Ia mengingatkan kita bahwa kebudayaan bukan produk, melainkan proses. Bukan hasil akhir, tapi perjalanan yang penuh dengan pilihan-pilihan etis.
Bersikap, apalagi ketika tahu bahwa sikap itu akan membuatmu sendirian, adalah kerja kebudayaan yang paling berat. Tapi justru di situlah kemurniannya. Tidak tunduk pada tekanan, tidak hanyut dalam kompromi, dan tidak silau pada posisi—itulah bentuk kebudayaan yang tak bisa dipalsukan.
Probo menunjukkan bahwa keberanian untuk bersikap adalah perlawanan terhadap banalitas struktural yang mereduksi manusia menjadi operator. Ia memilih menjadi manusia seutuhnya, bukan roda gigi yang bisa diganti kapan saja.
Membangun Ekosistem Alternatif
Kita tidak hanya butuh keberanian untuk keluar dari struktur. Kita juga butuh imajinasi untuk membangun ekosistem baru. Ekosistem yang tak bergantung pada anggaran negara, tapi bergantung pada solidaritas, kepercayaan, dan kolaborasi.
Banyak komunitas di berbagai daerah telah menunjukkan bahwa ini mungkin. Di Papua, di Kalimantan, di pesisir selatan Jawa, hingga di tengah kota Jakarta—komunitas budaya membangun ruang belajar sendiri, pertunjukan jalanan, festival kampung, riset warga, hingga dokumentasi tradisi dengan teknologi murah.
Bentuk ini bukan hanya alternatif, melainkan koreksi struktural terhadap sistem lama. Ketika anak-anak muda membangun rumah baca dari sumbangan buku, saat petani membuat panggung kesenian dari papan bekas, atau ketika musisi jalanan menginisiasi sekolah musik berbasis donasi, mereka sedang menunjukkan bahwa kebudayaan bisa tumbuh dari gotong royong, bukan dari tender proyek.
Ini adalah bentuk lain dari pemajuan kebudayaan: bergerak dari bawah, bukan dari atas. Dari mereka yang punya relasi langsung dengan budaya, bukan dari mereka yang hanya menjadikannya laporan.
Sejarah Telah Menunjukkan
Apa yang dilakukan Probo bukan hal baru. Sejarah pergerakan budaya Indonesia penuh dengan jejak pembangkangan terhadap struktur.
Rendra dengan Bengkel Teater-nya menolak tunduk pada seni yang steril dan formal. Komunitas Utan Kayu pada era 90-an membangun ruang diskusi independen di tengah rezim otoriter. Komunitas Teater Garasi memilih jalan seniman-kolektif, bukan seniman-pegawai. Begitu pula dengan kelompok-kelompok sastra jalanan, pengarsip desa, dan kolektif seni jalanan masa kini.
Mereka semua punya satu kesamaan: menolak dibatasi oleh struktur yang tidak berpihak pada rakyat. Mereka memilih meretas jalan sendiri, meski lebih sepi, tapi lebih bermakna.
Bahkan jika kita mundur lebih jauh ke sejarah perjuangan bangsa, banyak pendiri republik ini juga memulai dari ruang-ruang budaya: Tan Malaka, Amir Sjarifuddin, hingga Chairil Anwar—mereka bukan orang yang lahir dari sistem formal, tetapi dari bara perlawanan yang menjadikan budaya sebagai alat perjuangan.
Dilema Loyalitas dan Beban Emosional
Tidak mudah keluar dari struktur. Ada loyalitas yang harus dihadapi, ada teman seperjuangan yang mungkin kecewa, ada beban moral yang tak ringan. Tapi justru karena itu, pilihan ini bernilai. Karena dilakukan bukan dengan emosi sesaat, tapi dengan pertimbangan etis dan spiritual.
Dalam dunia kerja budaya, seringkali kita dipaksa merasa bersalah jika tidak ikut dalam program negara. Tapi siapa yang lebih bersalah: mereka yang diam dalam sistem yang rusak, atau mereka yang memilih bicara dari luar?
Perasaan bersalah bukan hanya soal meninggalkan lembaga, tetapi soal kemungkinan ditinggalkan oleh rekan sendiri. Namun harus diingat, kesetiaan tertinggi bukan pada struktur, melainkan pada nilai dan cita-cita bersama. Dan terkadang, demi nilai itu, kita harus menempuh jalan sendiri.
Menuju Politik Budaya yang Membumi
Apa yang sedang kita perjuangkan hari ini bukan sekadar soal kegiatan seni atau pelestarian tradisi. Ini adalah soal bagaimana kebudayaan bisa menjadi ruang pembebasan, ruang pembelajaran, dan ruang penyembuhan.
Kita butuh politik budaya yang membumi. Bukan yang elitis dan birokratis, tapi yang berangkat dari pengalaman rakyat. Bukan yang sibuk dengan branding kota kreatif, tapi yang peduli pada regenerasi nilai dan kearifan lokal.
Politik budaya harus lahir dari akar. Ia harus bersentuhan dengan kehidupan petani, nelayan, pekerja informal, dan anak muda kampung. Karena merekalah pemilik sah kebudayaan, bukan elite yang sibuk mengurus laporan.
Keluar dari struktur adalah bagian dari strategi menuju politik budaya baru ini. Dan semakin banyak yang melakukannya, semakin kuat pula fondasi ekosistem budaya yang otentik.
Penutup: Jalan Sunyi yang Ramai
Jalan keluar dari struktur mungkin terlihat sunyi. Tapi sebenarnya ia sedang ramai. Ramai oleh orang-orang yang memilih untuk tidak tunduk. Ramai oleh ide-ide yang tak lagi muat di ruang formal. Ramai oleh percakapan, pertunjukan, riset, dan praktik yang benar-benar hidup.
Probo Darono Yakti dan banyak lainnya menunjukkan bahwa keberanian itu ada. Dan bahwa kita tidak sendiri. Gerakan ini sedang tumbuh. Dari desa, dari komunitas, dari mereka yang selama ini suaranya dipinggirkan.
Kami menulis ini bukan hanya untuk menyatakan dukungan, tapi juga untuk meyakinkan diri sendiri: bahwa keluar dari struktur bukan akhir, tapi awal dari kebudayaan yang lebih sehat dan merdeka.
Salam budaya dari jalan setapak.


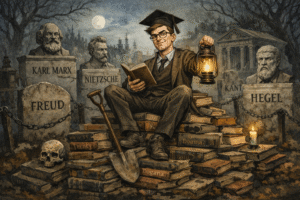

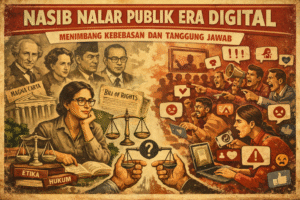


Be First to Comment