Esai
Kades Hoho, pemimpin desa bertato yang mendobrak stigma, hadir sebagai simbol resistensi budaya dan legitimasi rakyat. Simak analisis sosiologis, politik identitas, dan psikologi massa tentang figur kontroversial namun inspiratif ini.
Villain Bertato yang Menginspirasi Kepemimpinan Baru di Desa
Pendahuluan: Tubuh yang Bekerja, Simbol yang Menyimpang
Di tengah laju politik lokal yang kerap kaku dan penuh formalitas, muncul sosok yang mendobrak pakem: Welas Yuni Nugroho atau lebih dikenal sebagai Kades Hoho, kepala desa Purwasaba, Banjarnegara. Bukan karena kebijakan kontroversial atau praktik korupsi, melainkan karena tubuhnya—penuh tato seperti Yakuza, rambut klimis, pakaian santai, dan gaya tutur yang dekat dengan rakyat. Namun alih-alih menjadi simbol kekacauan, Hoho justru membalik stigma itu dengan kerja nyata: membangun jalan, mengembangkan BUMDes, menyumbangkan ambulans, bahkan membuka peternakan ayam dan sapi yang menopang ekonomi desa.
Fenomena Kades Hoho bukan sekadar viralitas media sosial. Ia merupakan gejala budaya kontemporer yang menarik untuk dibaca melalui pendekatan sosiologis dan politik identitas. Bagaimana tubuhnya menjadi medan diskursif atas stigma, bagaimana identitasnya membelah citra pemimpin desa yang konservatif, dan bagaimana ia secara diam-diam mendekonstruksi batas antara “yang sah memimpin” dan “yang tampak menyimpang”.
Tubuh dan Kekuasaan: Menyigi Representasi Visual
Dalam kajian representasi Stuart Hall, makna bukanlah sesuatu yang melekat secara tetap, melainkan produk dari sistem tanda, simbol, dan proses budaya. Tubuh bertato seperti milik Hoho dalam masyarakat konservatif biasanya diasosiasikan dengan kekerasan, premanisme, atau kriminalitas. Dalam struktur masyarakat pedesaan yang masih menjunjung moralitas visual sebagai ukuran kebaikan, tubuh bertato bisa menjadi simbol ketakutan.
Namun Hoho menghadirkan tubuh yang bekerja. Ia turun ke sawah, mengatur kandang ayam, memperbaiki jalan desa. Tato-tato yang tadinya menjadi simbol marginalitas justru menjadi pembuka percakapan, bukan intimidasi. Hoho memperlihatkan bagaimana tubuh yang distigmakan dapat di-reklamasi menjadi alat legitimasi baru. Dalam pengertian Foucaultian, tubuh Hoho adalah lokasi resistensi terhadap “rejim estetika kekuasaan”—di mana kekuasaan tidak hanya mengatur melalui hukum, tapi juga melalui pengendalian terhadap bagaimana pemimpin harus tampil.
Antara Villain dan Hero: Dekonstruksi Narasi Kepemimpinan
Dalam budaya populer, terutama pasca-modern, muncul arketipe anti-hero atau villain yang justru memiliki agenda moral. Dari Joker dalam film 2019 yang memperjuangkan suara kaum termarjinalkan, hingga tokoh seperti V dalam V for Vendetta, kita belajar bahwa penampilan “gelap” tidak serta merta menandakan kerusakan moral. Hoho, dalam konteks ini, bisa dibaca sebagai “villain visual”—dengan tubuh penuh tato dan gaya nyentrik—tetapi dengan tindakan sosial yang justru memenuhi fungsi seorang pemimpin.
Pierre Bourdieu menyebutkan konsep habitus, yaitu kerangka persepsi dan tindakan yang dibentuk oleh struktur sosial. Hoho tidak memenuhi habitus kekuasaan desa yang selama ini berbaju dinas, formal, dan bersikap berjarak dengan rakyat. Ia justru memproduksi modal simbolik baru: pemimpin desa yang hidup seperti warganya. Modal ini menjadi kekuatan politik baru yang tidak diambil dari legalitas birokrasi semata, tetapi dari legitimasi afektif dan kultural.
Desentralisasi Estetika Kekuasaan
Di banyak desa, pemimpin cenderung meniru estetika pusat: mulai dari cara berpakaian hingga gaya bicara. Fenomena ini merupakan bentuk simbolisasi kekuasaan yang diturunkan. Hoho melawan itu dengan estetika lokal dan tubuh yang dianggap menyimpang. Ia memperlihatkan bahwa kepemimpinan bukan tentang meniru pusat, melainkan merepresentasikan rakyat secara otentik.
Dalam pendekatan budaya kontemporer, ini adalah bentuk desentralisasi simbol kekuasaan. Hoho membuka ruang baru bagi identitas rakyat untuk tampil sebagai pengelola kekuasaan, tanpa perlu mengadopsi simbol elite. Ia menghadirkan narasi bahwa menjadi pemimpin tidak memerlukan perubahan bentuk tubuh menjadi “layak tampil”, tapi cukup dengan menjadi fungsional, adil, dan mengakar.
Politik Identitas dan Tubuh Subaltern
Politik identitas kerap dibahas dalam isu gender, ras, atau kelas. Namun dalam kasus Hoho, politik identitas muncul dari tubuh yang menyeberang batas moral dominan. Tato, gaya berpakaian, dan tutur kasualnya adalah bahasa tubuh subaltern—yakni kelompok yang selama ini tidak mendapat ruang dalam struktur formal.
Gayatri Spivak dalam esainya Can the Subaltern Speak? menyebutkan bahwa subaltern sering kali tidak didengar bukan karena tidak berbicara, tetapi karena suara mereka ditolak oleh struktur dominan. Dalam konteks ini, Hoho tidak hanya berbicara, tapi berteriak melalui kerja nyatanya. Tubuhnya yang selama ini dianggap tidak representatif justru menjadi kanal legitimasi alternatif yang tak terbantahkan.
Ekonomi Rakyat, Legitimasi Baru
Keberhasilan Hoho dalam membangun ekonomi desa menunjukkan bahwa politik bisa berakar dari kebutuhan rakyat, bukan janji elite. Ia mengembangkan peternakan dengan produktivitas tinggi, membuka kafe desa, bahkan merancang kolam renang untuk anak-anak. Ini adalah bentuk redistribusi sumber daya yang tidak bergantung pada pusat, tetapi dikelola secara kolektif dan lokal.
Secara sosiologis, ini merupakan bentuk “ekonomi moral rakyat” (James C. Scott). Ketika negara gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, rakyat mencari pemimpin yang menghadirkan keadilan distributif meski tidak mengikuti formalisme kekuasaan. Hoho berhasil membangun sistem yang legitim bukan karena aturan, tapi karena keberpihakan.
Psikologi Massa dan Efek Simbolik Tubuh Hoho
Dalam perspektif psikologi massa, tubuh dan gaya kepemimpinan Hoho dapat dibaca sebagai pemicu efek resonansi kolektif. Mengacu pada teori Gustave Le Bon, massa cenderung merespons figur yang kuat secara simbolik—tidak selalu dari aspek rasional, tetapi karena kemampuan memicu afeksi dan identifikasi. Hoho, dengan tubuh penuh tato dan gestur non-formal, justru menciptakan kedekatan afektif yang sulit dicapai oleh pemimpin konvensional.
Alih-alih menciptakan jarak simbolik, Hoho menjelma menjadi cermin dari massa itu sendiri—representasi dari “kita yang biasanya tidak pernah tampil di atas panggung kekuasaan.” Di sinilah psikologi massa bekerja: bukan sekadar pada retorika, tetapi pada tubuh yang mampu menyalurkan aspirasi kolektif melalui kesamaan, bukan perbedaan status.
Negara dan Politik Relasi Kuasa: Di Mana Posisi Negara?
Fenomena Hoho juga menantang posisi negara dalam relasi kuasa lokal. Negara selama ini memainkan peran sebagai penentu norma representatif kekuasaan melalui regulasi, birokrasi, dan estetika kepemimpinan. Namun dalam kasus Hoho, negara tidak menjadi pusat legitimasi utama. Legitimasi hadir dari rakyat secara langsung, melalui kebermanfaatan dan representasi afektif.
Dalam kerangka Michel Foucault, ini adalah bentuk kuasa mikro—di mana kekuasaan tidak selalu vertikal, melainkan tersebar dan hadir dalam praktik sosial sehari-hari. Negara, dalam kasus Hoho, lebih berperan sebagai entitas administratif ketimbang sebagai pemilik tunggal otoritas politik. Ini menandakan pergeseran penting: dari negara sebagai pusat kebenaran, menuju komunitas sebagai pusat legitimasi sosial.
Kesimpulan: Villain adalah Konstruksi, Kepemimpinan adalah Fungsi
Kades Hoho adalah potret kompleks dari budaya kontemporer yang terus bergeser. Ia membongkar mitos bahwa kekuasaan hanya dapat diakses oleh tubuh yang steril dan tampan. Ia memperlihatkan bahwa tubuh bertato, yang dianggap “villain” oleh budaya dominan, justru bisa menjadi simbol pemulihan martabat sosial.
Fenomena Hoho adalah bukti bahwa kita hidup di era transisi representasi. Di mana pemimpin tidak lagi dinilai dari simbol, tetapi dari fungsi. Di mana tubuh rakyat bisa menembus struktur formal dan memimpin tanpa harus mengganti kulitnya.
Ia adalah contoh bahwa politik identitas bukan hanya soal pengakuan, tapi juga tentang siapa yang memiliki hak untuk membentuk makna dan fungsi sosial baru. Dan di dalam tubuh Hoho, narasi itu hidup dan terus bekerja.
Daftar Bacaan:
- Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Sage, 1997.
- Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books, 1995.
- Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press, 1984.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?” in Marxism and the Interpretation of Culture. University of Illinois Press, 1988.
- Scott, James C. The Moral Economy of the Peasant. Yale University Press, 1976.
- Le Bon, Gustave. The Crowd: A Study of the Popular Mind. Macmillan, 1896.


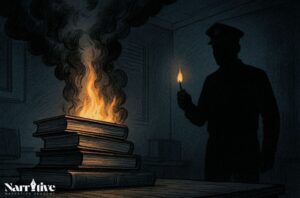
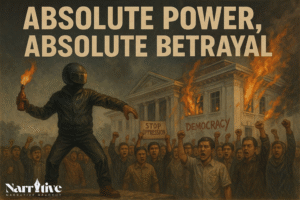
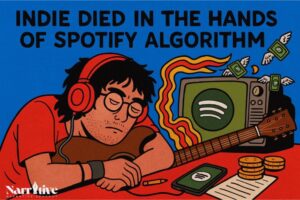

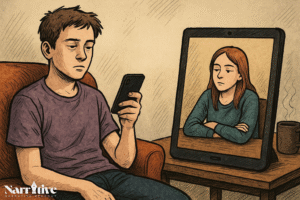
Be First to Comment