Esai | penulis : Viper Berbisaberbusaberbisikbersisik
Kebakaran Gedung Grahadi Surabaya 2025 membuka luka kolektif. Apa bedanya api perjuangan Bandung Lautan Api 1946 dengan bara kekecewaan hari ini?
Api selalu punya dua wajah: ia bisa menjadi cahaya yang menghangatkan, atau bara yang melalap habis kenangan. Semalam, di Surabaya, wajah yang kedua tampak lebih nyata—Gedung Grahadi, bangunan cagar budaya yang pernah menjadi saksi panjang perjalanan sejarah Jawa Timur, kini menjadi arang di tengah hiruk pikuk demonstrasi. Api melompat dari jendela ke jendela, di hadapan ratusan orang berdesakan di jalanan, sebagian mengutuk, sebagian terdiam, sebagian lagi mengabadikan momen itu dengan kamera ponselnya.
Kemarahan publik pun segera menyebar. Ada yang menyebutnya sebagai bukti anarkisme massa, ada yang meyakini bahwa itu bukanlah ulah para demonstran melainkan kerja “massa susupan” yang menyusup di tengah gejolak. Isu itu berputar cepat, menjadi kabut hitam yang menutupi inti persoalan. Namun, bagaimana pun juga, yang tersisa kini adalah kenyataan getir: sebuah bangunan bersejarah telah diciderai, dan polemik sosial baru dibuka.
Tulisan ini tidak hendak membenarkan tindakan anarkis yang membakar warisan budaya. Tidak juga untuk mengabaikan kemungkinan adanya susupan yang memperkeruh situasi. Justru, esai ini ingin menempatkan peristiwa tersebut dalam bingkai sejarah yang lebih luas: bahwa api, betapapun menyakitkannya, sering hadir di momen-momen krisis bangsa. Kita pernah melihatnya di Bandung, pada Maret 1946, ketika sebuah kota rela dijadikan lautan api demi harga kemerdekaan. Menyisakan pertanyaan di hadapan puing-puing Grahadi: apakah kita masih mampu membedakan api yang lahir dari pengorbanan dengan api yang sekadar meninggalkan kehancuran?
Bandung Lautan Api: Api Sebagai Harga Kemerdekaan
Bandung, Maret 1946. Malam itu, langit tidak hanya diterangi bulan, tetapi juga oleh nyala yang membelah horizon. Dari atap-atap rumah, gudang, kantor, hingga jalan-jalan besar, api berkobar serentak, menjadikan kota itu lautan cahaya merah. Bukan karena amarah spontan, bukan pula ulah tangan-tangan liar tanpa tujuan. Api itu lahir dari keputusan pahit—sebuah strategi bumi hangus agar kota Bandung tidak dikuasai kembali oleh pasukan Sekutu dan NICA.
Bayangkan getirnya: rakyat dipaksa meninggalkan rumah mereka, menyerahkan harta, bahkan kenangan, untuk dibakar dengan tangan sendiri. Setiap kobaran api bukan sekadar kayu yang terbakar, tetapi juga perabot, foto keluarga, pakaian bayi, dan sejarah hidup yang ikut lenyap. Namun, dalam kepedihan itu ada tekad yang mengeras: lebih baik membakar kota sendiri daripada melihatnya jatuh ke tangan penjajah.
Sejarawan menyebutnya sebagai simbol pengorbanan kolektif—sebuah revolusi yang dibayar dengan arang dan air mata. Dalam lautan api itu, rakyat Bandung seakan menyampaikan pesan yang jauh lebih keras daripada peluru: bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan harga yang harus ditebus, bahkan jika yang harus dikorbankan adalah tanah kelahiran sendiri.
Di situlah letak perbedaan mendasar: api Bandung 1946 menyala dengan makna, meski menyakitkan. Ia adalah api yang diarahkan, dipilih, dan dimaknai sebagai bagian dari perjuangan. Api yang tidak sekadar membakar bangunan, tetapi menyalakan martabat sebuah bangsa.
Harga Revolusi dalam Perspektif Ahli
Sejarah selalu menuntut bayaran. Tidak ada revolusi yang lahir tanpa korban; tidak ada perubahan besar yang tumbuh tanpa kehilangan. Para pemikir kita telah lama mengingatkan hal ini.
Koentjaraningrat, antropolog besar Indonesia, pernah menekankan bahwa revolusi adalah usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan arus zaman. Ia tidak datang dengan mulus, tetapi melalui benturan, kegelisahan, dan pengorbanan. Revolusi, dalam pandangan ini, adalah pertemuan antara harapan dan luka.
Widjojo Nitisastro, ekonom yang kerap membaca sejarah sebagai transformasi, menyebut revolusi sebagai perombakan total atas pola sosial, politik, dan ekonomi. Itu artinya, perubahan semacam itu tak mungkin tanpa guncangan. Ia seperti pohon tua yang harus ditebang demi tumbuhnya hutan baru. Bunyi kapak dan serbuk kayu adalah harga yang melekat.
Sementara Soerjono Soekanto, sosiolog, menegaskan revolusi sebagai perubahan mendasar yang tidak bisa dielakkan. Ia lahir ketika ketegangan dalam masyarakat mencapai titik didih, ketika jalan damai terlalu sempit untuk dilalui. Dalam ruang itu, korban hampir selalu menjadi konsekuensi.
Seorang penulis pernah menuliskan kalimat yang getir: “Korban adalah harga sebuah revolusi… nilai yang harus dibayar demi sebuah kejayaan.” Kalimat itu tidak romantis; ia justru mengandung ironi. Karena dalam setiap api yang menyala, ada wajah-wajah yang kehilangan rumah, ada anak-anak yang kehilangan buku sekolah, ada sejarah yang terhapus.
Maka, jika kita bertanya: apa harga sebuah revolusi? Jawabannya tidak tunggal. Kadang ia dibayar dengan darah, kadang dengan air mata, kadang dengan kenangan yang dipaksa dilupakan. Yang pasti, harga itu selalu mahal, terlalu mahal, sehingga harus ditimbang dengan penuh kesadaran.
Membaca Grahadi Lewat Sejarah Api
Di ujung sabtu malam minggu, Gedung Grahadi—simbol keanggunan sekaligus wajah pemerintahan Jawa Timur—berubah menjadi bara. Api itu tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari perasaan publik yang terbelah antara amarah, kecewa, dan putus asa. Di jalanan, ribuan orang berkumpul, bersuara, lalu sebagian menyalakan api. Seperti semua tragedi, ia lahir bukan dari satu sebab, melainkan akumulasi yang lama terkubur.
Kemarahan ini bukan tanpa alasan. Dikutip dari BeritaSatu, massa yang datang ke Grahadi pada malam itu menolak keras tindakan represif aparat dan menuntut pembebasan rekan mereka yang ditangkap dalam aksi sebelumnya. Kekecewaan terhadap institusi pemerintah menjadi latar yang membara, menjadikan Grahadi bukan hanya sebuah bangunan, melainkan simbol kekecewaan yang sulit lagi ditahan.
Api kemudian benar-benar menjilat dinding barat gedung. Dikutip dari Times Indonesia, massa melempar bom molotov hingga ruangan press room terbakar, disusul bagian dalam gedung yang porak poranda. Perabot, arsip, dan dokumen lenyap dalam hitungan jam, berubah menjadi abu. Apa yang dulu berdiri sebagai rumah megah kini berdiri sebagai puing hitam.
Kerusakan itu tidak berhenti pada bangunan. Dikutip dari Liputan6, sejumlah laptop, printer, hingga kursi kantor raib dijarah, sementara motor-motor yang terparkir ikut terbakar. Bahkan, menurut laporan Suara Surabaya, lebih dari 21 sepeda motor menjadi arang di halaman Grahadi. Semua itu bukan sekadar kerugian material, tetapi juga luka simbolik: rusaknya wajah pemerintahan, luntur pula rasa percaya rakyat pada institusi yang seharusnya melindungi mereka.
Seorang warga yang ditemui Detik berkata dengan getir, “Lebih parah dari ’98.” Kalimat itu bukan sekadar perbandingan, tetapi tanda bahwa luka sosial kini lebih terasa mendalam, karena ia terjadi di era demokrasi yang mestinya memberi ruang aman bagi ekspresi rakyat.
Tentu, kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan adanya provokator atau massa susupan. Isu itu nyata, dan banyak pihak mengingatkannya. Tetapi, sebagaimana api tidak bisa menyala tanpa bahan bakar, begitu pula kerusuhan tak akan membesar tanpa ada kekecewaan yang sudah lama menumpuk di dada masyarakat.
Jika Bandung 1946 adalah api yang dinyalakan dengan sadar demi merengkuh kemerdekaan, maka Surabaya 2025 adalah api yang lahir dari puncak kekecewaan terhadap institusi, dari perasaan ditinggalkan oleh rumah yang mestinya menjadi pelindung. Satu api diarahkan sebagai strategi; satu lagi meledak sebagai jeritan. Keduanya sama-sama pahit, tapi dengan makna yang berbeda.
Penutup: Belajar dari Api, Bukan Pembakarannya
Sejarah kerap diingat lewat kobaran api. Bandung, 1946, memperlihatkan bahwa api bisa menjadi pilihan sadar, dipeluk meski pedih, demi harga kemerdekaan. Surabaya, 2025, menunjukkan bahwa api bisa pula meledak tiba-tiba, sebagai puncak kekecewaan ketika suara tak didengar, ketika saluran demokrasi terasa buntu, ketika institusi yang semestinya melindungi justru dipandang melukai.
Namun ada perbedaan mendasar yang perlu kita jaga: api Bandung adalah simbol pengorbanan kolektif, sementara api Grahadi adalah simbol frustrasi sosial. Keduanya lahir dari rasa sakit, tetapi yang satu berbuah martabat, sedang yang lain meninggalkan abu kemalangan.
Kita memang tidak boleh terjebak pada demonisasi anarkisme yang membuat kita lupa dengan sejarah yang tak hanya ditulis dengan tetesan darah tapi juga dengan lidah-lidah api. Kita juga tidak bisa menutup mata dari isu provokator atau massa susupan—isu itu nyata dan patut dicermati. Tetapi menyempitkan pandangan hanya pada itu pun berbahaya, karena bisa mengaburkan jeritan kekecewaan rakyat yang sesungguhnya. Api bukan hanya persoalan siapa yang menyalakan, tetapi juga mengapa kayu-kayu kekecewaan dibiarkan menumpuk begitu lama.
Bandung mengajarkan bahwa revolusi memang mahal. Surabaya mengingatkan kita agar tidak salah bayar. Harga perubahan tidak harus selalu ditukar dengan arang dan puing; ia bisa, seharusnya, ditukar dengan dialog, dengan keadilan yang nyata, dengan keberanian moral untuk mengoreksi diri.
Api akan selalu menjadi bagian dari sejarah, tapi pilihan kita hari ini menentukan: apakah api itu akan menjadi cahaya yang menuntun jalan, atau hanya bara yang menghanguskan kenangan.


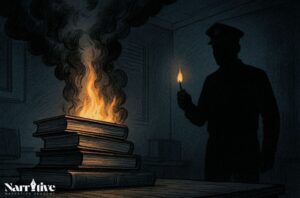
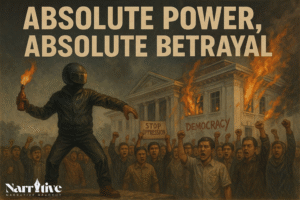
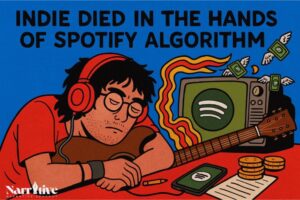

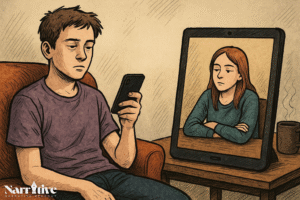
Be First to Comment