Esai
Fenomena video call tanpa percakapan menunjukkan absurditas komunikasi digital dan simulakra kehadiran. Kajian budaya dengan Camus & Baudrillard.
Bias Realitas dalam Media Komunikasi Modern: Telaah Absurditas dan Simulakra
Di ruang-ruang kecil yang dipenuhi cahaya layar, manusia modern menjalani kebersamaan yang aneh. Dua orang menyalakan video call dari kamar masing-masing. Kamera menyala, wajah terpampang di layar, tetapi tak ada kata yang diucapkan. Yang satu membaca buku, yang lain memainkan gim, sementara panggilan terus berlanjut. Lima belas menit, setengah jam, satu jam berlalu dalam hening. Mereka tidak berbicara, tetapi tidak juga menutup sambungan. Aneh, tetapi keduanya merasa sedang bersama. Fenomena seperti ini kian lazim, terutama di kalangan anak muda, dan disebut dengan berbagai istilah: “nongkrong online”, “teman layar”, atau sekadar call-an.
Sekilas, fenomena ini tampak remeh. Namun bila ditelusuri lebih jauh, ia menyimpan pertanyaan serius tentang makna komunikasi di era digital. Apakah komunikasi hanya tentang bertukar pesan, ataukah cukup dengan menghadirkan tanda kehadiran? Mengapa keheningan virtual bisa dianggap sebagai kebersamaan? Dan bagaimana teknologi komunikasi modern menciptakan bias realitas, di mana tanda menggantikan kenyataan? Untuk menjawabnya, kita perlu menengok dua teori besar dalam kajian budaya: absurditas dari Albert Camus dan simulakra dari Jean Baudrillard.
Camus menyingkap absurditas sebagai ketegangan antara harapan manusia akan makna dan kenyataan hidup yang hampa. Dalam The Myth of Sisyphus, ia menggambarkan Sisifus yang dihukum para dewa untuk mendorong batu ke puncak gunung hanya untuk melihatnya menggelinding lagi. Itulah metafora hidup manusia: bekerja, berusaha, mencari arti, tetapi selalu berhadapan dengan kekosongan. Namun, Camus tidak berhenti pada keputusasaan. Ia menulis bahwa manusia bisa memilih untuk menyadari absurditas itu dan tetap hidup, bahkan bahagia, dengan menerimanya. Dalam absurditas, manusia menemukan kebebasan baru.
Sementara Baudrillard berbicara tentang simulakra, dunia di mana tanda dan citra tidak lagi merepresentasikan realitas, melainkan menciptakan realitasnya sendiri. Dalam Simulacra and Simulation, ia menjelaskan bagaimana iklan, media, dan teknologi membangun hiperrealitas: kondisi di mana simulasi terasa lebih nyata daripada kenyataan. Disneyland, misalnya, tidak hanya mewakili dunia fantasi, tetapi menjadi “realitas” yang lebih meyakinkan daripada kota nyata di luar gerbangnya. Begitu pula iklan makanan yang tampak lebih menggoda daripada rasa asli makanannya. Dalam dunia simulakra, orang puas dengan tanda, bukan dengan kenyataan yang ditandai.
Fenomena video call tanpa percakapan memperlihatkan pertemuan kedua teori ini. Dari Camus, kita bisa melihat absurditas: manusia menyalakan layar, terhubung, tetapi tidak berbicara. Kehadiran tanpa percakapan adalah ritual kosong yang tetap diulang, seperti Sisifus yang tetap mendorong batu meski tahu hasilnya sia-sia. Namun, dari Baudrillard, kita melihat bahwa kehadiran digital itu bukan sekadar kosong. Ia adalah simulakra kebersamaan: tanda kamera menyala, wajah di layar, suara aktivitas samar, semua itu menciptakan ilusi kebersamaan yang cukup memuaskan. Kebersamaan nyata digantikan oleh tanda kebersamaan, dan tanda itulah yang diterima sebagai realitas.
Pergeseran makna komunikasi tampak jelas di sini. Dulu, komunikasi dipahami sebagai pertukaran pesan: kata, ide, informasi. Kini, komunikasi bisa berarti sekadar tanda kehadiran. Status “online” di WhatsApp, titik hijau di Messenger, atau kamera menyala di Zoom sudah cukup membuat orang merasa terhubung. Isi percakapan menjadi nomor dua; yang utama adalah keberlangsungan tanda. Itulah mengapa video call bisa berlangsung berjam-jam tanpa percakapan: karena nilai utamanya bukan isi, melainkan tanda “kita bersama”.
Pergeseran ini juga mengubah cara orang memahami keintiman. Dalam relasi dekat, ada keyakinan bahwa orang bisa nyaman berdiam bersama tanpa merasa canggung. Keheningan menjadi tanda kedekatan. Fenomena video call tanpa percakapan mengambil logika itu, tetapi memindahkannya ke ruang digital. Aneh memang: keheningan yang biasanya lahir dari kehadiran fisik, kini diproduksi oleh jaringan internet. Namun justru di situlah letak absurditas sekaligus simulakra: keheningan virtual dianggap setara dengan keheningan nyata.
Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kehidupan personal, tetapi juga pada struktur sosial dan budaya. Kehadiran kosong yang dinormalisasi membuat masyarakat terbiasa dengan komunikasi tanpa isi. Nongkrong online dianggap sah, meski tak ada percakapan. Bahkan, dalam beberapa kasus, dianggap lebih intim karena tidak ada tuntutan untuk terus berbicara. Keheningan bersama di layar dipandang sebagai bukti kedekatan, meski sebenarnya ia adalah ilusi.
Selain itu, fenomena ini juga terkait erat dengan ekonomi digital. Jam-jam hening dalam video call berarti jam-jam penggunaan aplikasi. Bagi perusahaan penyedia layanan komunikasi, ini adalah keuntungan. Absurdnya manusia modern yang rela berlama-lama dalam kebersamaan kosong dijadikan komoditas. Platform komunikasi menjual kebersamaan digital sebagai fitur, memasarkan simulasi sebagai pengalaman nyata. Absurditas tidak hanya menjadi kondisi eksistensial, tetapi juga bisnis yang menguntungkan.
Dari sisi psikologis, fenomena ini juga bisa dipahami sebagai strategi menghadapi kesepian. Dalam dunia yang semakin individualistik, banyak orang merasa terasing meski berada di tengah keramaian. Media sosial tidak selalu mampu mengisi kekosongan itu, karena ia penuh dengan sorotan publik dan performa diri. Video call tanpa percakapan menawarkan alternatif: kehadiran yang privat, hening, dan tidak menuntut. Di sanalah manusia modern menemukan cara baru untuk menipu kesepian, dengan simulasi kebersamaan.
Namun, pertanyaan yang lebih dalam adalah: apakah fenomena ini tanda kemunduran komunikasi, atau justru bentuk baru komunikasi yang lebih sesuai dengan zaman? Camus mungkin akan melihatnya sebagai absurditas yang wajar: manusia tetap menjalankannya meski tanpa makna, dan di situlah mereka menemukan kebahagiaan kecil. Baudrillard, sebaliknya, akan melihatnya sebagai gejala hiperrealitas: kebersamaan nyata tergantikan oleh simulasi kebersamaan, dan manusia tidak lagi peduli pada perbedaan antara keduanya.
Kedua perspektif ini, meski berbeda nada, sama-sama menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar kebiasaan sepele. Ia adalah cermin kondisi manusia di era digital, ketika teknologi komunikasi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga membentuk realitas. Manusia modern menerima simulasi sebagai kenyataan, menerima absurditas sebagai kebiasaan, dan menemukan kenyamanan dalam kebersamaan yang kosong.
Inilah bias realitas yang lahir dari media komunikasi modern. Realitas tidak lagi berdiri sendiri, tetapi selalu diproduksi ulang oleh tanda dan teknologi. Video call tanpa percakapan memperlihatkan bagaimana batas antara realitas dan simulasi makin kabur, bagaimana kehadiran bisa diciptakan tanpa tubuh, dan bagaimana makna bisa digantikan oleh tanda. Fenomena ini mungkin tampak absurd, tetapi justru di situlah ia paling jujur menggambarkan keadaan manusia digital.
Manusia selalu mencari cara untuk dekat, dan teknologi memberi jalan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun kedekatan itu dibayar dengan ironi: semakin canggih alat komunikasi, semakin tipis perbedaan antara hadir dan absen, antara bersama dan sendiri. Video call tanpa percakapan adalah wajah komunikasi modern, wajah yang absurd sekaligus hiperreal. Ia mengajarkan kita bahwa di era digital, komunikasi tidak lagi tentang kata-kata, melainkan tentang tanda kehadiran; tidak lagi tentang makna, melainkan tentang ilusi; tidak lagi tentang realitas, melainkan tentang bias realitas yang kita sepakati bersama.
Pada akhirnya, manusia digital mungkin tidak berbeda jauh dari Sisifus. Mereka terus mendorong “batu” berupa sinyal internet, terus menyalakan layar, terus menerima absurditas itu sebagai bagian dari hidup. Bedanya, Sisifus hidup di gunung mitis, sementara manusia modern hidup di gunung data dan jaringan. Dan seperti kata Camus, kita harus membayangkan Sisifus bahagia. Begitu pula manusia digital: bahagia dalam absurditas, nyaman dalam simulakra, dan setia pada layar yang menyala.


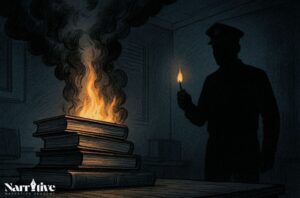
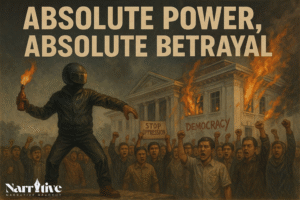
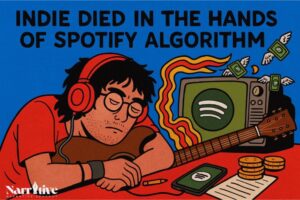

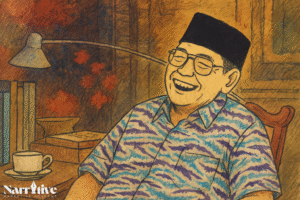
Be First to Comment