Esai kuratorial dari pameran ‘Fragmen dari yang Utuh’ di Sampun Nusantara
Ruang yang Mengingat, Ruang yang Menghidupkan
Dalam tradisi ruang pamer modern, kita terbiasa dengan dinding putih, pencahayaan steril, dan keheningan yang dibuat-buat. Ruang galeri kerap diciptakan untuk meniadakan gangguan dunia luar, agar pengunjung dapat “fokus” pada karya seni, seolah-olah seni hanya dapat dimengerti bila dipisahkan dari kehidupan. Namun, dalam pameran ini, ruang justru dikembalikan pada kehidupan itu sendiri. Tidak ada dinding putih, tidak ada batas steril antara pengunjung dan alam. Tanah menjadi lantai, bambu menjadi dinding, udara menjadi cahaya, dan aroma sekam yang terbakar menjadi bingkai yang tak terlihat bagi setiap karya.
Pameran ini tidak berupaya meniru galeri, melainkan menolak cara berpikir yang memisahkan estetika dari pengalaman hidup. Ia menolak ide bahwa kebudayaan hanya bisa dilihat dalam bentuk yang bersih, rapi, dan jauh dari debu dunia. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kebudayaan adalah ruang yang terus hidup, yang pori-porinya masih berisi udara, bunyi, dan bau. Ketika foto-foto para pekarya digantung pada dinding kayu dan tiang bambu, mereka tidak sekadar dipajang, tetapi ditempatkan kembali ke konteks asalnya: kehidupan yang tumbuh bersama tanah dan waktu.
Ada semacam kontinuitas yang sengaja dihadirkan di sini. Ketika pengunjung melangkah di atas tanah basah, merasakan angin menyentuh kulit, dan melihat pantulan cahaya sore menimpa permukaan foto, pengalaman yang terjadi bukan lagi sekadar apresiasi visual, melainkan pengalaman tubuh. Ruang pamer berubah menjadi lanskap kultural yang mengundang tubuh untuk hadir sepenuhnya. Dalam konteks inilah, konsep pameran menjadi perluasan dari tema kebudayaan itu sendiri karena kebudayaan, pada dasarnya, bukan hanya soal apa yang terlihat, tetapi juga tentang bagaimana manusia mengalami dunia.
Dalam konteks semiotik, ruang ini bekerja sebagai teks yang terbuka. Material bambu, kayu, dan tanah tidak hadir sekadar sebagai properti visual, tetapi sebagai penanda yang menautkan makna. Bambu yang lentur dan berongga memanggil kembali citra masyarakat agraris, masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, bukan di atasnya. Kayu yang mulai menua dan berbau lembap menghadirkan kesan waktu: kehadiran masa lalu yang masih hidup di antara kita. Tanah basah di bawah kaki adalah ingatan yang paling purba; ia menjadi penghubung antara tubuh dan bumi, antara seni dan keberlanjutan. Semua elemen itu bekerja bukan sebagai dekorasi, melainkan sebagai bahasa yang menyusun pengalaman.
Karya-karya foto yang dipajang, berukuran 30×40 cm, tampak sederhana pada pandangan pertama. Namun, kesederhanaan itu sengaja dipilih untuk menjaga keseimbangan antara representasi dan konteks. Di sini, gambar tidak berusaha mendominasi ruang; justru ruanglah yang memperluas makna gambar. Foto-foto yang diambil dari Sukabumi, Mentawai, Wae Rebo, dan Bali kembali menemukan rumahnya di ruang yang bernafas sama, ruang yang hidup dari material yang sama dengan yang terekam dalam foto. Dengan demikian, pengunjung tidak sekadar “melihat” kebudayaan, tetapi menghidupi suasana yang sama dengan para subjek di dalamnya.
Dalam ruang terbuka ini, batas antara karya dan kenyataan menjadi kabur. Bau sekam yang terbakar, suara daun bergesekan, dan kilau cahaya yang berganti setiap menit menjadi bagian dari komposisi pameran. Tidak ada kontrol penuh atas cahaya, tidak ada pengatur suhu, tidak ada dinding yang menutup suara. Segala sesuatu yang hidup ikut berpartisipasi: angin menjadi kurator yang mengubah posisi foto, cahaya menjadi seniman yang mengedit warna, waktu menjadi pengunjung yang tak pernah diam.
Melalui strategi ini, pameran tidak hanya menampilkan kebudayaan, tetapi mewujudkan kebudayaan. Ia mengembalikan seni pada fungsi awalnya: sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat adat yang menjadi subjek foto, seni dan kehidupan tidak pernah terpisah. Sebuah tenunan bukan sekadar objek estetika, tetapi cara berpikir; sebuah ritual bukan sekadar tontonan, tetapi cara memahami dunia. Maka, menghadirkan karya dalam ruang alami seperti ini bukan romantisasi terhadap “masa lalu”, melainkan bentuk penghormatan terhadap pengetahuan yang telah lama hidup di dalam struktur masyarakat tersebut.
Bila dalam dunia modern ruang pamer sering kali menjadi simbol kemajuan, dengan desain arsitektur yang steril dan penuh kontrol, maka ruang ini justru menawarkan pembalikan. Ia menghadirkan gagasan tentang ketidakterkendalian sebagai bentuk kebijaksanaan. Bahwa dalam kebudayaan, tidak semua hal harus diatur; sebagian justru dibiarkan mengalir, tumbuh, dan berinteraksi dengan waktu. Pameran ini mengajarkan kita untuk mempercayai alam sebagai bagian dari narasi, bukan gangguan terhadapnya. Dalam artian tertentu, ruang ini bukan hanya ruang pamer, melainkan juga ruang perenungan ekologis.
Spasialitas yang dibangun di sini memunculkan pengalaman multisensori. Pengunjung tidak hanya melihat karya, tetapi mencium, mendengar, dan merasakan atmosfer yang membungkusnya. Aroma tanah basah membangkitkan sensasi ingatan, mungkin ingatan masa kecil di kampung, atau sekadar perasaan bahwa dunia pernah lebih sederhana. Bambu yang bergoyang diterpa angin menimbulkan bunyi yang mengiringi langkah kaki. Semua itu menciptakan komposisi yang cair, di mana pengunjung menjadi bagian dari karya. Dalam istilah fenomenologi, pengalaman semacam ini adalah bentuk embodied perception kesadaran tubuh yang menyatu dengan ruang.
Jika dalam ruang galeri modern, tubuh pengunjung sering diatur dan didisiplinkan dilarang menyentuh, diharuskan diam, diarahkan pada satu jalur pandang, maka dalam pameran ini tubuh dibebaskan untuk berpartisipasi. Tidak ada jarak hierarkis antara penonton dan karya. Pengunjung dapat berjalan, berhenti, menunduk, bahkan berbicara sambil merasakan udara sore. Kebebasan ini menciptakan bentuk apresiasi yang lebih organik, yang tumbuh dari rasa ingin tahu alih-alih aturan kuratorial yang kaku.
Dari sisi konseptual, pendekatan ini adalah upaya mengembalikan representasi pada pengalaman. Dalam banyak pameran modern, karya seni berfungsi sebagai jendela menuju dunia lain yang “diwakilinya”. Namun, di sini, foto-foto tidak menjadi jendela, melainkan cermin. Ia tidak membawa kita ke tempat yang jauh, tetapi mengembalikan kita ke dalam diri, ke dalam ruang kultural yang telah lama kita tinggalkan. Dengan melihat foto masyarakat adat atau agraris di ruang alami seperti ini, kita tidak hanya menatap “mereka” sebagai objek, melainkan juga menatap kembali “kita” yang telah tercerabut dari relasi semacam itu.
Pilihan material seperti bambu dan kayu juga memuat lapisan makna semiotik yang kaya. Dalam kebudayaan Indonesia, bambu sering menjadi metafora bagi keseimbangan: kuat namun lentur, kosong namun berdaya guna. Kayu, di sisi lain, adalah simbol kontinuitas waktu, ia merekam jejak usia, menyimpan cerita dari musim ke musim. Ketika kedua material ini digunakan untuk menopang karya foto, makna yang muncul bukan sekadar estetika, melainkan dialog antara masa kini dan masa lalu. Ia menjadi semacam arsitektur pengetahuan yang mengingatkan bahwa modernitas tidak lahir dari ruang kosong; ia tumbuh dari akar yang dalam.
Ruang pamer ini, dengan segala kesederhanaannya, justru menjadi bentuk kompleksitas yang jujur. Ia tidak berusaha menjadi megah, melainkan tulus. Dalam keterbukaannya, ruang ini menolak hierarki antara yang disebut “tinggi” dan “rendah”, antara seni dan kehidupan. Ia menyajikan kebudayaan sebagaimana adanya: rapuh, hangat, berlapis, dan senantiasa berubah.
Dalam pandangan semiotik Roland Barthes, setiap ruang adalah teks yang bisa dibaca, dan setiap objek di dalamnya adalah penanda yang membentuk sistem makna. Dengan cara itu, ruang pamer terbuka ini bisa dibaca sebagai teks tandingan terhadap ruang-ruang pamer konvensional. Jika galeri putih adalah representasi dari ide kemurnian modernitas, di mana seni dilepaskan dari konteks sosialnya, maka ruang ini adalah representasi dari keterhubungan. Ia menolak “kemurnian” dan memilih kebercampuran; menolak “jarak” dan memilih kedekatan; menolak “abstraksi” dan memilih kehidupan.
Melalui strategi spasial ini, pameran Fragmen dari yang Utuh tidak hanya berbicara tentang kebudayaan sebagai tema, tetapi juga menjadi kebudayaan itu sendiri. Setiap elemen ruang bekerja seperti sistem nilai yang hidup, mengajarkan keseimbangan, kepekaan, dan kesadaran ekologis. Dalam ruang ini, estetika tidak lagi dipahami sebagai keindahan yang terpisah dari etika, tetapi sebagai cara hidup yang menyatu dengannya.
Ada dimensi temporal yang menarik di sini. Waktu dalam ruang pamer ini tidak bersifat linear seperti dalam museum modern. Ia tidak memaksa pengunjung menelusuri urutan tertentu, melainkan memberi kebebasan untuk tersesat. Dalam keterbukaan itu, waktu menjadi siklus: siang berganti malam, cahaya berubah arah, dan setiap kunjungan menghadirkan pengalaman yang berbeda. Pameran ini, dengan demikian, menolak gagasan permanensi dan menghidupkan kembali kesadaran bahwa kebudayaan selalu dalam proses menjadi.
Kebudayaan, dalam konteks ini, bukanlah sesuatu yang usang yang kita rawat di balik kaca, melainkan sesuatu yang terus tumbuh di dalam tubuh dan ruang kita. Ruang pamer terbuka ini menjadi metafora dari tubuh kebudayaan itu sendiri, terbuka, berpori, dan penuh kemungkinan. Dalam setiap tiupan angin dan suara dedaunan, kita diajak untuk menyadari bahwa kehidupan itu sendiri adalah karya yang paling dinamis.
Mungkin inilah yang ingin ditegaskan oleh para penyelenggara: bahwa berbicara tentang kebudayaan tidak cukup dengan menatapnya dari kejauhan. Kita perlu masuk ke dalamnya, menyentuh, mencium, mendengar, dan merasakannya. Dalam ruang semacam ini, kebudayaan tidak lagi menjadi konsep yang abstrak, melainkan pengalaman yang konkrit. Ia hadir dalam setiap langkah, setiap tarikan napas, setiap percakapan antara pengunjung dan karya.
Ketika pengunjung meninggalkan ruang pamer, yang tersisa bukan hanya citra visual, tetapi sensasi yang melekat di tubuh, bau tanah, suara bambu, dan bayangan cahaya yang berubah di permukaan foto. Semua itu menjadi semacam ingatan kolektif yang meneguhkan bahwa kita masih bagian dari dunia yang sama dengan yang terekam dalam foto-foto itu. Dalam dunia yang semakin terputus dari alam dan tradisi, pengalaman semacam ini menjadi bentuk perlawanan kecil namun berarti.
Pameran Fragmen dari yang Utuh pada akhirnya bukan sekadar acara seni, melainkan sebuah percakapan panjang antara ruang, karya, dan manusia. Ia mengajukan pertanyaan yang sederhana tapi mendalam: bagaimana kita ingin hidup di dunia ini? Apakah kita ingin terus membangun tembok yang memisahkan seni dari kehidupan, manusia dari alam, modernitas dari akar? Atau kita ingin kembali membuka ruang, membiarkan udara dan waktu masuk, agar kebudayaan bisa bernafas kembali?
Di antara tiang bambu dan bau sekam yang samar, pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu dijawab bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kesadaran.


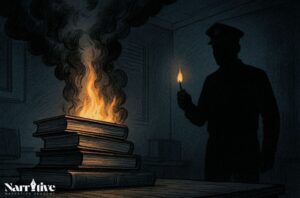
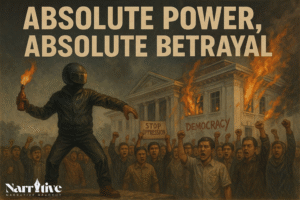
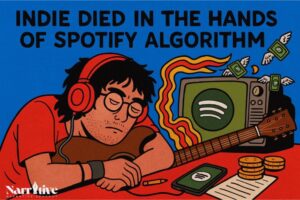

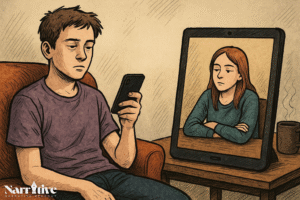
Be First to Comment