Opini
Festival “jazz” kini sering jadi kemasan pop dan kapitalisme belaka. Artikel ini menyorot hilangnya semangat improvisasi dan integritas musik jazz, serta menyerukan dukungan bagi musisi jazz sejati.
“Who the fuck are you? You’re not jazz, dude.” Kalimat itu mungkin terdengar kejam, bahkan bagi sebagian orang terasa kelewat kasar untuk dibuka di hadapan khalayak festival musik. Tapi sejujurnya, itu adalah pertanyaan yang berkecamuk di kepala begitu kaki saya menapak di pelataran acara yang berani menempelkan kata “jazz” sebesar baliho iklan rokok, sementara apa yang keluar dari speaker justru suara pop yang dibungkus saksofon seadanya. Saya berdiri di tengah kerumunan yang sibuk berswafoto, memandangi panggung yang berkilauan lampu LED, dan bertanya-tanya: apakah kita sedang menyaksikan jazz, atau sekadar pesta merk dagang dengan label yang menipu?
Jazz, bagi saya, bukan sekadar aliran musik. Ia adalah pernyataan sikap. Sebuah kebebasan improvisasi yang lahir dari penderitaan dan semangat perlawanan. Kita bisa menelusuri jejaknya ke awal abad ke-20, ke klub-klub gelap di New Orleans, ketika komunitas kulit hitam memadukan blues, ragtime, dan ritme Afrika menjadi bahasa musik yang menolak tunduk pada kekakuan musik klasik Eropa. Di sanalah jazz bernapas: liar, penuh kejutan, tanpa partitur kaku. Setiap nada adalah protes, setiap improvisasi adalah kebebasan. Itu sebabnya menyebut pertunjukan pop setengah matang sebagai “jazz” terasa seperti penghinaan terhadap sejarah panjang pemberontakan itu.
Namun kapitalisme, seperti biasa, punya cara mengebiri makna. Kata “jazz” kini menjadi semacam mantra pemasaran. Cukup tempel kata itu di spanduk, tambahkan gambar saksofon atau topi fedora, dan tiket pun ludes terjual. Penyelenggara tahu betul, jazz punya citra keren: dewasa, elegan, sedikit edgy. Pasar menengah ke atas menyukainya karena terkesan cerdas dan kosmopolitan. Jadilah festival-festival “jazz” bermunculan di setiap kota, dari mal hingga pantai. Tapi ironisnya, yang tampil seringkali bukan musisi jazz. Kita disuguhi band pop yang menambahkan satu-dua lick saksofon atau aransemen swing yang dipaksakan. Kadang malah EDM dengan loop sederhana yang kebetulan punya trumpet elektronik. Jazz di sini hanyalah kemasan, bukan substansi.
Yang membuat lebih getir, para pengisi acara tampaknya tidak merasa malu. Mereka berdiri di panggung bertuliskan “jazz festival” dengan percaya diri, memainkan lagu radio yang hanya sedikit dipermak. Mereka mengaku “bereksperimen” atau “menjazzkan” lagu pop, seolah menaburkan akor tujuh sudah cukup untuk disebut jazz. Padahal eksperimen sejati menuntut keberanian membongkar struktur, bukan sekadar memoles agar enak di telinga penonton yang mengantre minuman bersponsor. Saya tak menuduh setiap musisi pop yang tampil di festival itu oportunis, tapi ketika panggungnya mengusung nama “jazz”, ada tanggung jawab estetik yang sedang diabaikan.
Di sisi lain, kita harus jujur: audiens pun turut melanggengkan kebohongan ini. Banyak penonton datang bukan untuk menikmati improvisasi atau poliritme yang menantang, melainkan untuk mengejar suasana “jazz” yang instagramable. Mereka membeli tiket bukan karena cinta pada musik, melainkan untuk mengunggah foto dengan latar panggung berlabel jazz, menandai diri sebagai “penikmat seni”. Budaya FOMO, takut ketinggalan momen mendorong orang datang hanya untuk membuktikan eksistensi. Alhasil, penyelenggara tidak merasa perlu mengundang musisi jazz asli; mereka tahu massa akan tetap datang selama ada lampu cantik, minuman mahal, dan poster bertuliskan J-A-Z-Z.
Fenomena ini tentu bukan sekadar persoalan selera. Ada konsekuensi nyata bagi ekosistem jazz sejati. Musisi jazz yang serius, yang menghabiskan jam-jam panjang mempelajari harmoni kompleks, melatih improvisasi, dan mendalami sejarah musik sering tersisih dari panggung yang seharusnya menjadi ruang mereka. Honor untuk mereka kalah oleh band pop yang lebih “marketable.” Jam session yang seharusnya menjadi laboratorium kreativitas berubah menjadi gimmick panggung sekadar formalitas. Jazz yang semula liar dan bebas kini dipenjarakan dalam format 45 menit yang rapi dan aman untuk sponsor.
Kapitalisme festival bekerja dengan logika yang dingin: selama tiket laku, siapa peduli isi panggung? Jazz yang dulu lahir sebagai perlawanan terhadap tatanan sosial yang menindas kini dijadikan alat penjualan. Semangat improvisasi digantikan kalkulasi pemasaran. Sponsor besar menempelkan logo mereka di setiap sudut, dari gelas minuman hingga gelang akses VIP, seolah ruh jazz bisa dibeli dengan paket promosi. Ironi ini semakin menyakitkan ketika kita menyadari bahwa jazz awalnya berkembang di pinggiran, lahir dari komunitas yang justru terpinggirkan oleh sistem ekonomi yang serakah. Kini musik yang lahir dari perlawanan justru dimanfaatkan oleh mekanisme pasar yang sama-sama menindas.
Ada yang berkilah, “Bukankah musik seharusnya bebas? Mengapa harus ada polisi genre?” Pertanyaan ini memang menggoda. Musik memang bebas, tetapi kebebasan sejati berbeda dengan penyalahgunaan istilah. Menyebut sembarang musik pop sebagai jazz bukanlah kebebasan; itu pemalsuan. Bayangkan jika sebuah restoran menjual mie instan dengan nama “Rendang Asli Padang” hanya karena menaburkan sedikit cabai. Tentu orang Minang akan marah, bukan karena benci mie instan, tetapi karena nama “rendang” memiliki makna, sejarah, dan teknik yang tak bisa dipalsukan. Begitu pula jazz: menyematkan label itu tanpa memahami atau menghargai esensinya adalah bentuk pengaburan yang merendahkan.
Masalahnya, industri tahu bahwa kebanyakan orang tidak peduli sedalam itu. Sebagian besar penonton tidak punya referensi cukup untuk membedakan bebop dari bossa nova, apalagi mendeteksi harmoni tritone substitution atau poliritme kompleks. Bagi mereka, “jazz” hanyalah suasana: lampu redup, minuman mahal, dan saksofon yang meliuk. Penyelenggara memanfaatkan ketidaktahuan ini untuk menjual apa saja dengan label jazz, dari festival kuliner hingga pesta pantai. Kita pun, mungkin tanpa sadar, ikut menjadi kaki tangan kapitalisme budaya ini ketika membeli tiket tanpa mempertanyakan isinya.
Di titik ini, saya teringat pada semangat awal jazz: kebebasan, improvisasi, dan dialog antar-musisi. Jazz bukan musik yang mencari kenyamanan, melainkan mengguncang kenyamanan. Dengarkan rekaman-rekaman awal Louis Armstrong, bebop Charlie Parker, atau free jazz Ornette Coleman: ada kegilaan yang disengaja, ketidakpastian yang memaksa pendengar waspada. Setiap pertunjukan adalah percakapan yang tak bisa diprediksi, sebuah ajakan untuk keluar dari kebiasaan. Itulah yang membuat jazz relevan, bahkan revolusioner. Ketika festival “jazz” hari ini hanya menawarkan musik pop manis dengan label palsu, kita kehilangan inti yang seharusnya dirayakan.
Apakah solusi dari semua ini? Tentu tidak mudah. Kita tidak bisa melarang orang bermain musik pop di festival manapun. Tapi kita bisa menuntut kejujuran label. Jika sebuah acara adalah festival pop, sebut saja pop. Jika menampilkan campuran genre, katakanlah “fusion festival” atau “urban music festival”. Menggunakan kata “jazz” semata-mata demi gengsi adalah bentuk pembohongan publik. Selain itu, penonton pun perlu lebih kritis. Jangan membeli tiket hanya karena kata “jazz” di poster. Tanyakan siapa musisinya, dengarkan rekaman mereka. Apakah mereka benar-benar bermain jazz atau hanya memoles pop dengan akor tujuh? Tanpa tekanan dari penonton, penyelenggara akan terus menjual kemasan kosong.
Sebagian orang mungkin akan menyebut kritik ini elitis, seolah hanya “puris jazz” yang berhak menentukan apa itu jazz. Tapi kritik ini bukan soal kemurnian dogmatis; ini soal integritas. Jazz sendiri lahir dari percampuran, dari pertemuan budaya yang beragam. Tidak ada yang menolak inovasi atau kolaborasi lintas genre. Masalahnya adalah ketika kolaborasi hanya jadi kedok untuk pemasaran, tanpa semangat eksplorasi yang jujur. Ketika pop tetap pop tapi dijual sebagai jazz, kita sedang berbicara tentang penipuan, bukan evolusi.
Di tengah kekecewaan itu, masih ada titik terang: komunitas jazz sejati yang tetap berkarya di ruang-ruang kecil, dari bar bawah tanah hingga ruang komunitas. Mereka tidak mencari kilau sponsor atau panggung raksasa, tetapi mengejar dialog musikal yang tulus. Jam session mingguan di sudut kota, workshop harmoni untuk anak muda, rekaman independen yang lahir dari kantong sendiri, semua ini adalah bukti bahwa ruh jazz belum mati. Namun mereka membutuhkan dukungan nyata, bukan sekadar pujian. Membeli tiket ke pertunjukan mereka, membeli album mereka, atau sekadar menyebarkan kabar adalah langkah kecil tapi berarti untuk menjaga api itu tetap menyala.
Kemarahan saya terhadap festival “jazz” palsu bukan berarti menolak musik pop atau hiburan massal. Pop punya tempatnya sendiri, dan hiburan bukan dosa. Yang saya tolak adalah manipulasi: ketika label digunakan untuk mengelabui penonton dan mengikis makna sejarah. Ketika sebuah kata yang lahir dari perlawanan diperalat menjadi stiker komoditas, kita semua seharusnya marah. Karena pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya musisi jazz, tapi juga kita sebagai pendengar yang haknya atas kejujuran seni telah dirampas.
Namun kapitalisme tak pernah puas hanya pada satu trik. Begitu kata “jazz” terbukti laris, pola yang sama menjalar ke kota-kota lain seperti jamur setelah hujan. Setiap tahun muncul “Jazz on the Bay”, “Mountain Jazz”, “Sunset Jazz Picnic” nama-nama yang terdengar puitis tapi ujung-ujungnya hanyalah pasar malam berlampu mewah. Kadang saya merasa sedang menonton remake buruk dari film lama: panggung raksasa, barisan food truck, deretan artis yang lebih sering nongol di tangga lagu pop ketimbang ruang improvisasi bebop. Orang bertepuk tangan bukan karena solo trumpet yang mengguncang, melainkan karena kembang api yang meledak tepat di akhir lagu. Jazz di sini hanyalah dekorasi, semacam bumbu eksotis untuk menjustifikasi harga tiket.
Mari kita telusuri logika di baliknya. Sponsor korporat mencari acara yang bisa menggaet pasar menengah ke atas: mereka yang mau membayar mahal untuk “pengalaman eksklusif”. Jazz, dengan reputasinya yang intelektual dan kosmopolitan, cocok menjadi payung pemasaran. Penyelenggara kemudian merancang konsep: lokasi instagramable, lineup yang “ramah radio”, merchandise premium, dan tentu saja label “jazz” untuk memberikan kesan canggih. Sementara itu, musisi yang benar-benar bermain jazz dianggap terlalu “niche”, terlalu sulit dicerna. Mereka tidak mendatangkan massa sebesar band pop yang sedang naik daun. Maka pilihan pun jatuh pada nama-nama yang aman: penyanyi pop yang sesekali menambahkan akor tujuh, band indie yang memainkan chord progression sederhana tapi “dijazzkan” dengan sax midi. Semua demi memastikan tiket ludes tanpa repot mendidik telinga penonton.
Saya pernah berbicara dengan seorang pianis jazz yang frustasi. Ia bercerita tentang betapa sulitnya menembus panggung festival besar meski telah merilis album yang dipuji kritikus. “Mereka bilang musik saya terlalu rumit,” katanya. “Padahal bukankah jazz seharusnya rumit? Improvisasi, perubahan tempo, poliritme, itu rohnya. Tapi mereka lebih memilih penyanyi pop yang bisa menarik 10 ribu orang selfie.” Cerita seperti ini bukan kasus tunggal. Banyak musisi jazz tulen terpaksa bermain di bar kecil atau mengajar privat demi bertahan hidup, sementara panggung megah yang seharusnya menjadi ruang eksperimen justru dikuasai kapitalisme kemasan.
Penonton pun punya andil besar. Alih-alih menuntut keaslian, banyak yang justru menyambut gembira campuran genre instan. “Yang penting asik,” kata seorang pengunjung festival kepada saya, sambil meneguk minuman sponsor. “Nggak harus jazz beneran, yang penting vibe-nya dapet.” Kata “vibe” menjadi mantra yang mematikan argumen apa pun tentang integritas musik. Vibe, dalam konteks ini, hanyalah rasa nyaman, latar untuk bersosialisasi dan berfoto. Jazz sejati, dengan ketidakpastian dan tantangannya, justru dirasa mengganggu. Kita telah mengganti petualangan artistik dengan wallpaper sonik.
Lebih ironis lagi, festival-festival ini sering mengklaim “mengangkat musisi lokal” atau “mendukung komunitas”. Kenyataannya, dukungan itu sering bersifat kosmetik. Satu-dua band lokal diundang sebagai pembuka, diberi slot siang ketika penonton belum datang. Mereka digaji minim, kadang hanya diberi “kesempatan tampil”. Sementara headliner yang notabene bukan musisi jazz, mendapat panggung malam dan honor besar. Ini bukan dukungan, melainkan eksploitasi simbolis: menggunakan musisi lokal sebagai hiasan agar acara tampak inklusif. Padahal inti jazz justru komunitas; ia tumbuh dari interaksi setara, jam session spontan, bukan dari hierarki sponsor.
Kalau kita mau jujur, inilah wajah kapitalisme budaya: memanfaatkan istilah penuh makna menjadi alat jualan. Sama seperti kata “organic” pada produk makanan cepat saji atau “eco-friendly” pada mobil sport bertenaga besar, “jazz” di festival hanyalah label untuk menenangkan hati konsumen sambil mengosongkan kantong mereka. Ia memberi ilusi kedalaman tanpa komitmen pada substansi. Kita merasa lebih sophisticated karena menonton “jazz festival”, padahal yang kita konsumsi hanyalah pop instan dengan kemasan mahal. Ini seperti membeli buku klasik hanya untuk pajangan rak, bukan untuk dibaca.
Sebagian pihak mungkin membela diri: “Tapi bukankah genre selalu berevolusi? Jazz pun dulu campuran dari berbagai musik.” Benar, jazz lahir dari percampuran. Tapi ada perbedaan mendasar antara evolusi organik dan komodifikasi dangkal. Evolusi jazz, dari swing ke bebop ke fusion terjadi melalui eksplorasi musikal, melalui dialog intens antar-musisi yang berani menantang pendengar. Komodifikasi festival “jazz” masa kini hanyalah tempelan gaya. Tidak ada dialog, hanya kalkulasi pasar. Perpaduan genre sejati menuntut keberanian artistik; festival ini hanya menuntut keberanian menghitung ROI.
Kita juga harus menyoroti bagaimana media ikut bermain. Banyak liputan mengagungkan “kemeriahan festival jazz” dengan foto kerumunan dan headline bombastis. Jarang ada kritik tentang minimnya musisi jazz asli. Jurnalis musik yang seharusnya menjadi pengawal integritas justru tergoda klik dan undangan VIP. Media sosial memperparahnya: feed Instagram penuh foto orang-orang yang “hadir di festival jazz”, mengenakan outfit bohemian sambil memegang minuman craft. Tak ada yang bertanya siapa yang sebenarnya bermain di panggung. Jazz menjadi latar estetik, bukan pengalaman mendengar.
Di balik semua ini, ada tragedi yang lebih besar: hilangnya ruang pendidikan telinga. Jazz mengajarkan kita mendengar secara aktif, mengikuti percakapan musikal yang tak terduga. Ia melatih kesabaran, memperkaya rasa, dan menantang pola pikir. Ketika festival menggantinya dengan pop aman, kita kehilangan kesempatan itu. Generasi muda tumbuh dengan mengira bahwa jazz hanyalah pop dengan saksofon, kehilangan akses pada warisan artistik yang kaya. Ini bukan hanya masalah puritan musik; ini kehilangan warisan budaya.
Apa yang bisa dilakukan? Pertama, penyelenggara harus berani jujur. Jika ingin menampilkan pop atau campuran, sebut saja apa adanya. Jangan menjual “jazz” sebagai umpan. Kedua, perlu keberanian mengedukasi penonton. Menghadirkan musisi jazz sejati memang mungkin tidak mendatangkan penonton sebanyak artis pop, tetapi dengan kurasi cerdas dan promosi yang tepat, audiens bisa diajak untuk belajar menikmati kompleksitas. Lihat saja beberapa kota yang berhasil menggelar festival jazz murni dengan dukungan komunitas: mereka mungkin tidak semegah festival komersial, tetapi memiliki dampak budaya jauh lebih besar.
Penonton pun perlu merebut kembali peran kritisnya. Jangan membeli tiket hanya karena kata “jazz”. Lihat lineup, dengarkan musik mereka di platform daring. Jika mayoritas adalah band pop, tanyakan pada penyelenggara mengapa disebut jazz. Dukungan pada musisi jazz sejati juga penting: hadiri jam session lokal, beli album independen, dukung ruang komunitas. Uang kita adalah suara kita. Tanpa tekanan dari bawah, industri akan terus bermain aman.
Musisi yang menolak tunduk pada arus pasar juga perlu bersatu. Kolaborasi lintas kota, pertukaran jam session, dan publikasi digital bisa menjadi cara membangun ekosistem mandiri. Di era internet, distribusi musik tak lagi bergantung pada label besar. Komunitas bisa menciptakan festival kecil yang fokus pada kualitas, bukan kemasan. Memang tidak mudah, tetapi sejarah jazz menunjukkan kekuatan komunitas bawah tanah yang gigih.
Di tengah semua kegelisahan ini, saya masih menemukan momen-momen kecil yang mengingatkan bahwa jazz sejati belum mati. Suatu malam di sebuah kedai sempit, saya menyaksikan tiga musisi muda, pianis, bassis, dan gitaris melakukan jam session tanpa rencana. Tidak ada setlist, hanya percakapan musik yang liar. Penonton yang hanya belasan orang duduk hening, mendengarkan setiap pergeseran harmoni. Tidak ada sponsor, tidak ada kamera besar. Hanya musik, murni dan hidup. Di sanalah saya merasakan kembali semangat yang hilang dari festival raksasa: keberanian untuk menantang, kebebasan untuk berimprovisasi, ketulusan yang tak bisa dibeli.
Kontras itu semakin menegaskan betapa absurdnya festival “jazz” komersial. Di satu sisi, kita punya musisi sejati yang berjuang di ruang kecil; di sisi lain, kita punya panggung gemerlap yang menjual kata “jazz” sebagai latar pesta. Ironi ini adalah cermin masyarakat kita yang lebih peduli citra ketimbang isi. Kita membayar mahal untuk ilusi kedalaman, sementara kedalaman yang nyata kita abaikan karena tidak cukup “instagramable”.
Jadi, siapa sebenarnya yang harus ditantang dengan pertanyaan “Who the fuck are you? You’re not jazz, dude”? Bukan hanya penyelenggara atau musisi pop yang tampil di festival itu, tapi juga kita semua: penonton, media, bahkan pecinta musik yang kadang memilih diam. Kita semua berperan dalam normalisasi kebohongan ini. Pertanyaan itu adalah cermin: apakah kita masih peduli pada integritas seni, atau sudah puas dengan kemasan semata?
Jika jazz lahir sebagai bentuk perlawanan, maka mungkin saatnya kita melanjutkan perlawanan itu. Bukan dengan marah membabi buta, tapi dengan memilih secara sadar: mendukung musisi jazz sejati, mengkritisi festival palsu, menolak ilusi. Perlawanan ini mungkin tidak sepopuler festival berlampu neon, tapi justru di sanalah semangat jazz menemukan relevansinya kembali, sebagai musik yang tidak tunduk pada kenyamanan, sebagai bahasa kebebasan yang menolak dikomersialisasi.
Karena pada akhirnya, jazz bukan sekadar genre; ia adalah sikap hidup. Dan sikap itu tidak bisa dipalsukan dengan dekorasi panggung atau hashtag. Jadi lain kali Anda melihat poster “Mega City Jazz Festival” dengan lineup yang penuh band pop, tanyakanlah pada diri sendiri: apakah kita sedang merayakan jazz, atau hanya menari di atas kuburnya?


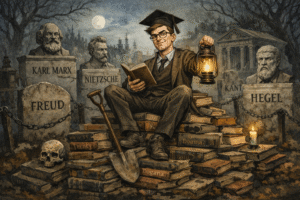

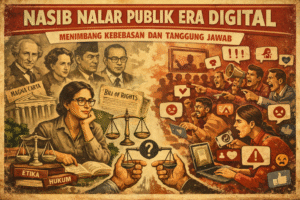


Be First to Comment