Opini
Korupsi laptop Rp1,98 triliun bukan sekadar skandal hukum, tetapi skandal peradaban. Bagaimana nasib bangsa jika pendidikan “suapan pertama bagi generasi muda” disuapi oleh tangan maling? Opini kritis dengan pandangan Noam Chomsky.
Bagaimana Nasib Bangsa Jika Suapan Pertama Pada Generasi Yaitu Pendidikan Disuapi oleh Tangan-Tangan Maling
Pendidikan sering kali dipandang sebagai suapan pertama yang diberikan bangsa kepada anak-anaknya. Suapan pertama ini adalah titik tolak, sebuah fondasi yang kelak menentukan seperti apa wajah generasi dan arah peradaban. Namun, bayangkan ketika suapan pertama itu bukan berupa gizi yang sehat, melainkan racun yang diselundupkan oleh tangan-tangan maling. Apa jadinya sebuah bangsa ketika generasi mudanya sejak awal sudah dipaksa menelan makanan busuk hasil dari kebohongan, korupsi, dan kerakusan elite? Pertanyaan ini kini menjadi lebih dari sekadar retorika, sebab kasus korupsi laptop yang menyeret nama Nadiem Makarim dan dugaan kerugian negara hampir dua triliun rupiah menunjukkan bahwa pendidikan di negeri ini bukan hanya gagal sebagai sarana pencerdasan, tetapi juga telah dikapling menjadi lahan perampokan.
Kita perlu melihat persoalan ini tidak hanya sebagai tindak pidana biasa, melainkan sebagai tanda betapa rapuhnya sistem yang seharusnya menjadi tulang punggung peradaban. Ketika pendidikan dijadikan ajang bancakan, yang tergadaikan bukan hanya angka rupiah, melainkan masa depan sebuah bangsa. Inilah tragedi sesungguhnya: pendidikan, yang seharusnya menjadi pintu masuk menuju pembebasan, justru dijadikan alat pemiskinan struktural yang menguntungkan segelintir orang. Noam Chomsky, intelektual publik yang tajam dalam menganalisis relasi kuasa, pernah menegaskan bahwa institusi pendidikan dalam masyarakat kapitalis kerap berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ideologi, bukan pembebasan. Ia menulis bahwa negara dan korporasi memanfaatkan pendidikan untuk mencetak individu patuh yang sesuai dengan kebutuhan pasar, bukan manusia merdeka yang mampu berpikir kritis. Apa yang kita saksikan di negeri ini tidak hanya mengonfirmasi tesis Chomsky, tetapi menambah bab baru: bahkan sebelum sampai ke tahap indoktrinasi ideologis, pendidikan kita sudah dicuri sejak dari anggarannya.
Korupsi laptop untuk sekolah bukan sekadar masalah teknis mengenai spesifikasi atau vendor. Ia adalah simbol. Laptop yang mestinya membuka jendela ilmu justru berubah menjadi bukti kriminal. Alih-alih menjadi instrumen demokratisasi pengetahuan, ia justru menjadi alat akumulasi modal bagi para pejabat busuk. Dan simbol ini sangat berbahaya karena ia menandai bahwa sejak “suapan pertama,” anak-anak Indonesia tidak diberi gizi intelektual, tetapi dipaksa menelan residu kerakusan. Apa yang akan tumbuh dari suapan pertama yang beracun itu? Tentu bukan generasi yang sehat, melainkan generasi yang tumbuh dengan trauma, ketidakpercayaan pada institusi, dan rasa sinis pada negara.
Ketika rakyat mendengar kasus ini, banyak yang mungkin merasa lelah: lagi-lagi korupsi, lagi-lagi pejabat, lagi-lagi pendidikan. Namun, lelah bukanlah jawaban, karena justru di titik inilah kita harus menyadari dampak jangka panjangnya. Jika generasi muda tumbuh dengan kesadaran bahwa pendidikan hanyalah lahan pencurian, maka mereka belajar satu hal sejak dini: bahwa kejujuran adalah kemewahan, integritas adalah lelucon, dan negara hanyalah mesin predator. Inilah yang paling menakutkan. Sebuah bangsa tidak mati hanya karena dirampok triliunan rupiah, tetapi ia mati ketika anak-anaknya kehilangan iman terhadap makna pendidikan. Dan kehilangan iman ini adalah keruntuhan yang lebih fatal daripada keruntuhan gedung atau anggaran.
Mari kita tarik ke dalam kerangka Chomsky. Ia berkali-kali menyebut bahwa masyarakat modern yang dikuasai kapitalisme global bekerja dengan cara “manufacturing consent” membentuk persetujuan palsu melalui media, pendidikan, dan propaganda. Negara, katanya, bekerja sama dengan korporasi untuk memastikan rakyat tetap jinak, sibuk, dan tidak pernah benar-benar memahami bahwa mereka sedang dieksploitasi. Dalam kasus laptop ini, kita bisa melihat bagaimana konsep itu bekerja: program digitalisasi pendidikan dikemas sebagai narasi mulia, katanya untuk membawa anak-anak bangsa masuk ke era digital. Tetapi di balik narasi itu, terdapat agenda tersembunyi: kontrak dengan vendor tertentu, keuntungan bagi kelompok tertentu, dan tentu saja, praktik memperkaya diri. Dengan kata lain, pendidikan di sini tidak hanya gagal memberi akses ke teknologi, tetapi juga digunakan sebagai alat “manufacturing consent” menjual ilusi kemajuan digital padahal yang terjadi hanyalah perampokan terstruktur.
Namun, mari kita berhenti sejenak. Apakah kita benar-benar menyadari bahwa masalah ini jauh melampaui angka Rp1,98 triliun? Angka itu memang mengejutkan, tetapi yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa para elite tidak lagi takut mencuri di hadapan publik, bahkan di sektor pendidikan yang dianggap sakral. Mereka mencuri terang-terangan, dengan penuh keyakinan bahwa sistem hukum dan politik akan melindungi mereka. Apalagi, kita tahu bahwa kasus-kasus besar sering berakhir dengan vonis ringan, pengurangan hukuman, atau bahkan grasi politik. Maka, korupsi laptop ini harus kita baca sebagai indikator bahwa garis merah moral bangsa sudah dilanggar, dan mereka melanggarnya dengan tanpa rasa malu.
Kekhawatiran terbesar kita bukan hanya soal kerugian materi, melainkan soal dampak kulturalnya. Apa jadinya ketika masyarakat terus-menerus melihat bahwa pendidikan tidak steril dari maling? Pertama, akan lahir generasi apatis, yang percaya bahwa sekolah hanyalah formalitas tanpa makna. Kedua, akan tumbuh budaya permisif: jika pejabat boleh mencuri, mengapa rakyat kecil tidak boleh menyontek, memalsukan, atau mengakal-akali aturan? Ketiga, akan lahir generasi yang tidak percaya lagi pada meritokrasi. Mengapa belajar sungguh-sungguh jika kenyataannya sukses ditentukan bukan oleh kemampuan, melainkan oleh akses pada jaringan korupsi? Tiga dampak kultural ini lebih berbahaya daripada angka kerugian, karena ia merusak etika sosial dari akar.
Inilah titik yang harus kita waspadai bersama. Chomsky selalu menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan pembebasan, tetapi ia juga sadar bahwa pendidikan yang dikuasai oleh elite akan menjadi instrumen domestikasi. Dalam konteks Indonesia, masalahnya lebih parah: pendidikan tidak hanya menjadi instrumen domestikasi ideologi, melainkan juga instrumen perampokan. Ini artinya, sebelum anak-anak sempat “dibentuk” oleh ideologi, mereka sudah lebih dulu dikorbankan sebagai angka-angka dalam laporan proyek. Mereka bahkan belum sempat merasakan manfaat dari laptop yang dijanjikan, tetapi dana untuk laptop itu sudah berpindah tangan ke kantong pejabat. Pendidikan di negeri ini, dengan demikian, tidak pernah benar-benar dimulai. Yang terjadi hanyalah simulasi pendidikan, anak-anak dipotret seolah memasuki era digital, sementara perangkat yang dijanjikan rusak, tidak layak, atau bahkan tidak sampai ke sekolah.
Apakah kita akan terus diam? Apakah kita akan membiarkan suapan pertama anak-anak bangsa kita terus-menerus disuapi oleh maling? Jika suapan pertama saja sudah busuk, bagaimana kita bisa berharap mereka tumbuh sehat? Kita tidak bisa lagi sekadar mengutuk atau menghela napas. Kita harus menuntut pertanggungjawaban serius, tidak hanya dari individu yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga dari sistem yang memungkinkan hal ini terjadi. Dari DPR yang menyetujui anggaran tanpa pengawasan serius, dari aparat hukum yang sering kali hanya berani menindak jika tekanan publik besar, hingga dari masyarakat sipil yang kadang terlalu cepat melupakan kasus besar. Semua pihak harus terlibat.
Kita tahu, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Negara-negara maju bisa menjadi maju karena mereka memastikan suapan pertama yang diberikan kepada anak-anaknya penuh gizi: sekolah yang layak, guru yang kompeten, fasilitas yang memadai. Bandingkan dengan kita, yang bahkan untuk memberi laptop saja masih dicuri. Apa yang kita harapkan dari generasi yang suapan pertamanya penuh racun? Yang kita panen bukan inovator, bukan pemimpin, bukan warga kritis, melainkan individu-individu yang sudah terbiasa hidup dalam sistem busuk. Mereka tidak akan melihat korupsi sebagai masalah, melainkan sebagai bagian wajar dari hidup. Dan ketika itu terjadi, tamatlah sebuah bangsa.
Maka, opini ini adalah peringatan keras: bangsa ini sedang berada di tepi jurang kultural. Korupsi laptop bukan hanya skandal hukum, tetapi skandal peradaban. Ia menunjukkan bahwa kita tidak lagi serius pada pendidikan, dan lebih memilih menjadikannya ladang perburuan rente. Bila tidak ada perubahan radikal, maka generasi muda akan terus disuapi oleh maling, dan dari mulut mereka hanya akan keluar budaya sinis, apatis, dan permisif.
Chomsky pernah berkata, “Jika kita tidak percaya pada kebebasan berbicara untuk orang-orang yang kita benci, maka kita tidak percaya pada kebebasan sama sekali.” Mari kita para rakyat menerjemahkan kalimat itu ke dalam konteks pendidikan: jika kita tidak mampu melindungi pendidikan dari tangan-tangan maling, maka kita tidak pernah percaya pada masa depan bangsa sama sekali. Suapan pertama harus kita rebut kembali. Kita harus memastikan bahwa anak-anak bangsa tidak lagi dipaksa menelan racun, melainkan diberi gizi intelektual, moral, dan kultural yang sehat. Jika tidak, maka nasib bangsa ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah dunia: sebuah negeri besar yang mati karena membiarkan generasi mudanya diracun oleh maling-maling pendidikan.



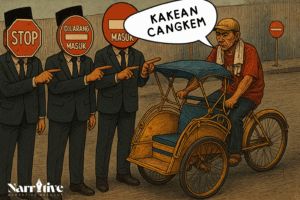
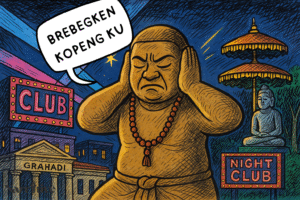

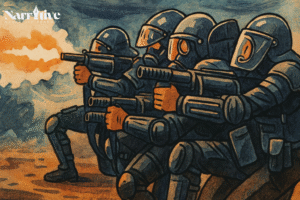
Be First to Comment