Opini
Data BPS 2025 menunjukkan beras jadi penyumbang kemiskinan terbesar. Bukti kegagalan negara agraris memberi makan rakyatnya sendiri.
Negara Agraris yang Gagal Memberi Makan Rakyatnya: Sebuah Olok-olok Kesejahteraan
Bayangkan absurditas paling konyol dalam sejarah negeri yang katanya tanah subur, sawah menghampar, dan hujan turun hampir setiap bulan: Indonesia, negara agraris, justru mencatat “beras”—makanan pokok—sebagai penyumbang terbesar kemiskinan rakyatnya. Inilah ironi paling telanjang yang dihadirkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025. Bukan karena rakyat tak mampu membeli mobil, rumah mewah, atau iPhone keluaran terbaru, melainkan karena mereka tidak mampu memastikan perutnya kenyang dengan nasi. Bukankah ini sebuah penghinaan yang luar biasa brutal bagi martabat bangsa? Bukankah ini menampar wajah para pejabat yang tiap kali berdiri di podium dengan lantang menyebut Indonesia sebagai negeri agraris, lumbung pangan dunia, negeri gemah ripah loh jinawi? Omong kosong! Fakta ini membuktikan bahwa jargon-jargon itu hanyalah kentut politik yang baunya busuk, sementara rakyat dicekik oleh harga beras yang justru memiskinkan mereka.
Data BPS menyebutkan beras menyumbang 21,06% garis kemiskinan nasional, lebih tinggi di desa (24,93%) ketimbang kota (21,01%). Apa artinya ini? Artinya orang-orang yang hidup di tanah yang penuh sawah, orang-orang yang tiap hari menunduk di lumpur, petani yang menyemai benih, memanen padi, justru menjadi kelompok yang paling tercekik oleh harga beras. Sebuah kebodohan struktural yang tak bisa ditutupi lagi. Petani kita bukan hanya miskin, mereka bahkan terjebak dalam paradoks menggelikan: menanam padi sepanjang tahun, tapi tetap lapar karena tidak mampu membeli beras yang mereka sendiri hasilkan. Inilah wajah nyata kegagalan negara, bukan sekadar gagal dalam teknis, tetapi gagal secara fundamental, gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya: makan.
Apakah ini bukan bukti bahwa negara bekerja bukan untuk rakyat? Apakah bukan bukti bahwa segala program swasembada pangan, segala subsidi pupuk, segala janji-janji “kedaulatan pangan” hanyalah pepesan kosong? Sementara rakyat dipaksa percaya bahwa pemerintah peduli, faktanya beras—makanan paling dasar, makanan rakyat jelata—justru menjadi indikator paling telanjang dari betapa busuknya sistem yang mereka jalankan. Jangan salahkan rakyat karena makan nasi, salahkan negara yang membuat nasi menjadi barang mewah. Jangan salahkan rakyat karena uangnya habis untuk beras, salahkan pejabat yang berulang kali menjual tanah subur kepada korporasi sawit, tambang, dan properti, hingga sawah hanya tinggal sejarah di brosur pembangunan. Negara ini memiskinkan rakyatnya dengan cara yang paling brutal: membuat makanan pokok menjadi komoditas mahal, lalu berlagak heran ketika rakyat jatuh miskin.
Apa lebih konyol lagi? Negara agraris yang bangga menyebut diri lumbung pangan, tapi rakyatnya antre beras impor dari Thailand, Vietnam, bahkan Pakistan. Para pejabat berfoto di dermaga dengan kapal kontainer berisi beras impor, seakan itu prestasi. Prestasi macam apa yang harus dirayakan ketika tanah sendiri subur tapi tidak mampu memberi makan rakyat? Bukankah itu sama saja mengakui bahwa mereka gagal mengurus negeri? Bahwa mereka tidak becus melindungi petani? Bahwa mereka lebih memilih rente impor ketimbang memastikan sawah rakyat tetap lestari? Di titik ini, kita tidak sedang bicara soal sekadar mahalnya harga beras, kita bicara soal negara yang rela melepaskan kedaulatan pangan demi kepentingan segelintir elit.
Lalu mari kita lihat lebih dalam: data BPS memang menyebut beras, rokok, dan kopi sachet sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan. Orang akan mudah menghakimi rakyat: “Lihat, mereka miskin karena doyan rokok dan kopi.” Tetapi berhentilah sejenak. Apakah salah rakyat yang hidup di tengah tekanan ekonomi, kerja serabutan, gaji UMR pas-pasan, mencari sedikit hiburan murah dengan kopi sachet dan sebatang rokok? Tidak. Yang salah adalah negara yang membiarkan kebutuhan dasar—beras—menjadi momok utama penyumbang kemiskinan. Bahwa rokok dan kopi hanyalah pelarian, bukan akar masalah. Akar masalahnya jelas: negara gagal memberi jaminan perut kenyang kepada rakyat. Apa artinya bicara pembangunan infrastruktur, IKN, megaproyek tol laut, kalau rakyat masih kesulitan membeli beras? Ini bukan sekadar kontradiksi, ini penghinaan.
Di pedesaan, angka beras sebagai penyumbang garis kemiskinan lebih tinggi daripada di kota. Bukankah ini semakin gila? Para petani yang menanam justru lebih miskin daripada pegawai kantoran yang membeli beras di minimarket. Inilah bukti nyata bahwa petani tidak pernah dilindungi. Harga gabah ditentukan oleh tengkulak, pupuk langka, biaya produksi tinggi, hasil panen dijual murah, lalu ketika masuk pasar harga beras melambung. Siapa yang menikmati selisih harga ini? Tentu saja korporasi besar, pedagang besar, mafia pangan, dan pejabat yang berkolusi. Petani hanya kebagian lelah, rakyat kebagian lapar, sementara elit kenyang mengisap rente. Negara seakan hanya berfungsi sebagai perantara yang melanggengkan eksploitasi ini, bukan pemecah masalah. Kalau ini bukan kegagalan fundamental, lalu apa?
BPS seharusnya tidak hanya berhenti pada data pengeluaran rakyat untuk beras, rokok, dan kopi. BPS harus berani merilis data yang lebih brutal: lembaga negara mana yang paling memiskinkan rakyat? Apakah Kementerian Pertanian dengan kebijakan yang membiarkan pupuk subsidi raib di jalan? Apakah Kementerian Perdagangan yang gemar membuka keran impor setiap kali panen raya tiba, menjatuhkan harga gabah petani? Apakah Bulog yang lebih sibuk menimbun daripada menyalurkan? Atau DPR yang tiap tahun menyetujui APBN dengan pos anggaran pangan yang besar, tapi bocor ke kantong oligarki? BPS harus transparan: kemiskinan rakyat bukan lahir dari perut mereka sendiri, tapi dari kebobrokan sistem negara yang bekerja secara struktural, sistematis, dan masif. Rakyat miskin bukan karena malas, bukan karena boros, tapi karena mereka dipaksa miskin oleh sistem.
Mari kita bayangkan absurditas ini lebih jauh: di negeri agraris, orang miskin bukan karena tidak mampu beli mobil, bukan karena tidak mampu bayar listrik, tapi karena tidak mampu beli beras. Apakah ada absurditas yang lebih hina dari ini? Seolah-olah negara berkata: “Kami gagal memberi makan kalian, tapi kami berhasil membangun jalan tol, bandara, dan gedung-gedung pencakar langit.” Apa gunanya semua itu kalau rakyat lapar? Apa gunanya klaim pertumbuhan ekonomi kalau harga beras terus mencekik? Inilah pembangunan versi negara: membiarkan rakyat mengemis untuk kebutuhan paling dasar, sementara elit menari di atas statistik pertumbuhan.
Dan jangan lupakan satu hal: beras bukan sekadar makanan, ia adalah simbol hidup orang Indonesia. Dari lahir hingga mati, beras hadir dalam setiap ritual. Dari tumpeng, kenduri, hingga sesajen, beras bukan sekadar karbohidrat, ia adalah kultur. Maka ketika beras menjadi penyumbang terbesar kemiskinan, sesungguhnya negara bukan hanya gagal memberi makan, tetapi juga menghancurkan kebudayaan. Ia merobek urat nadi rakyatnya sendiri. Ia menjadikan sesuatu yang paling sakral dalam kehidupan masyarakat sebagai sumber penderitaan. Bukankah ini kejahatan?
Maka jelaslah, data BPS ini harus dibaca bukan sekadar angka, tapi sebagai vonis. Vonis bahwa negara ini gagal secara fundamental. Bahwa jargon negara agraris hanyalah ilusi. Bahwa mereka yang berkuasa tidak pernah serius membangun kedaulatan pangan, karena lebih menguntungkan membiarkan rakyat miskin dan tergantung. Rakyat lapar lebih mudah dikendalikan. Rakyat miskin lebih mudah dibeli suaranya setiap pemilu. Dan beras, makanan yang seharusnya menjadi hak dasar, dijadikan alat politik paling efektif. Harganya dimainkan, stoknya dipermainkan, dan rakyat dijadikan korban permanen.
Jadi, jangan biarkan narasi resmi menyesatkan kita dengan menyalahkan rokok dan kopi. Rokok dan kopi hanyalah pelarian, tetapi beras adalah kebutuhan dasar. Fakta bahwa beras menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan adalah bukti telanjang bahwa negara gagal menjalankan tugas paling dasar: menjamin rakyat bisa makan. Negara boleh bicara soal industrialisasi, digitalisasi, bahkan artificial intelligence, tetapi selama rakyat masih miskin karena beras, semua itu hanyalah sandiwara murahan. Negara ini berdiri di atas perut lapar warganya, dan itu adalah bentuk kegagalan yang paling hina.
Dan di sinilah absurditasnya: Indonesia, negara agraris, negara sawah dan padi, gagal memberi makan rakyatnya dengan beras. Tidak ada ejekan yang lebih parah daripada ini. Tidak ada hinaan yang lebih brutal daripada fakta ini. Maka jangan salahkan rakyat kalau mereka marah. Jangan salahkan rakyat kalau mereka muak. Karena kemiskinan mereka bukan lahir dari pilihan, tapi dari sistem yang korup, bejat, dan busuk. Selama negara gagal memberi makan rakyatnya, negara ini tidak pantas disebut negara. Ia hanyalah mesin pemiskinan yang bekerja untuk kepentingan segelintir elit, sambil menjerumuskan jutaan rakyat ke dalam perut lapar yang tak kunjung terisi.




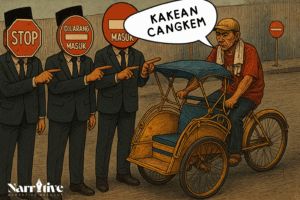
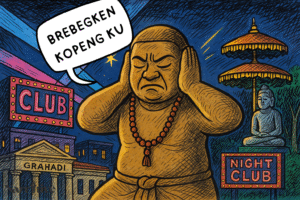
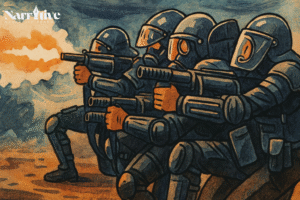
Be First to Comment