Penulis : Dr. Probo Darono Yakti
Saya sepakat dengan opini NarrativeReadout yang menegaskan bahwa keluar dari struktur bukan tanda menyerah, melainkan tindakan etis. Tapi kali ini, izinkan saya menambahkan: berhentilah berharap pada struktur yang sudah jelas beku, apalagi jika namanya adalah Dewan Kesenian Jawa Timur. Bukan hanya karena “seni” di sini terlalu sempit, tetapi juga karena sebagian orang di dalamnya punya pikiran yang sama sempitnya. Kalau kita ingin kebudayaan tumbuh, maka seharusnya berhenti memohon ruang pada meja rapat yang kursinya sudah lama dipenuhi ego. Saatnya membangun panggung kita sendiri, dunia kita sendiri. Bukan panggung yang diatur protokol, tapi ruang yang kita tata bersama dengan ritme yang kita tentukan, dengan bahasa yang kita pahami, dan dengan visi yang lahir dari kebutuhan nyata di lapangan.
Saya salut pada orang-orang yang memilih jalan ini. Salah satunya Tatang “Totenk” Rusmawan MT. Datang dari nun jauh di bumi Parahyangan ke Surabaya, mendirikan Sanggar Lidi bukan untuk sekadar pementasan, tetapi untuk membentuk ekosistem kreatif bagi anak-anak kampung. Lalu ia kembali ke daerah asalnya membawa pulang pengalaman, jaringan, dan api yang tak mungkin padam hanya karena tak ada surat tugas. Pergerakan kultural seperti ini yang tumbuh dari tanah, berakar di masyarakat, dan berbuah di keseharian lebih menjanjikan dibanding seribu rapat koordinasi. Ia tidak menunggu restu, ia tidak tunduk pada siklus anggaran, dan ia tidak takut disebut “tidak resmi.” Justru di situ letak kemerdekaannya.
Mungkin Kang Totenk Belum Pernah Merasakannya
Izinkan saya memulai pembicaraan serius ini dengan ungkapan: “mungkin Kang Totenk belum pernah merasakannya”. Sebuah ungkapan atas pengalaman empiris yang pernah saya alami ketika berorganisasi kebudayaan yang plat merah tapi mengaku lembaga non-struktural itu. Mungkin Kang Totenk belum pernah merasakan menyelenggarakan sebuah acara yang diinisiasi oleh sebuah instansi bernama Departemen secara tahunan. Acara ini memiliki anggaran yang di atas kertas tampak besar, namun ketika dibuka pos-posnya, sebagian besar justru dipotong untuk Steering Committee yang terdiri atas personil Badan Pengurus Harian (BPH). Porsi operasional acara hanya kebagian seperlima karena sisanya habis untuk honorarium.
Contohnya, ketika membuat sebuah program podcast yang mengundang narasumber dari luar, Steering Committee yang kerjanya hanya mengarahkan tanpa ikut mempublikasikan atau terjun dalam persiapan teknis malah mendapat honor lebih besar. Bukan persoalan besarnya honor yang membuat miris, tetapi hasil akhirnya. Program podcast yang seharusnya bisa menjadi wajah DKJT di ruang publik justru dikerjakan ala kadarnya. Padahal, segelintir golongan muda di DKJT yang ada di Departemen-lah yang selama ini terus menjaga eksistensi lembaga itu lewat podcast, meskipun organisasi di sekitarnya compang-camping dan kehabisan anggaran.
Pola ini juga terlihat ketika menyelenggarakan acara yang seharusnya berkelanjutan untuk bidang tertentu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, entah itu pelindungan dan inventarisasi, pengembangan, pemanfaatan, atau pembinaan. Sayangnya, di tengah perjalanan, proposal dan konsep acara diubah-ubah setiap tahun. Dulu, ketika saya berada di Departemen Litbang, konsep awalnya adalah riset dan pengarsipan karya budaya Jawa Timur yang sifatnya strategis. Tetapi konsep tersebut diubah menjadi FGD yang miskin makna, tanpa arah jelas, dan tidak menghasilkan dampak nyata. Lebih menyedihkan lagi, output-nya dibuat sekadar untuk memenuhi laporan, bukan untuk membangun kesinambungan.
Di atas semua itu, DKJT membentuk sistem elitis yang bahkan terlihat dari warna jaket yang dipakai. Warna jaket hitam untuk BPH, warna biru untuk Departemen. Seolah-olah BPH adalah majikan, sedangkan Departemen hanyalah kuda tunggangan. Ketika program berhasil, BPH akan mengklaim sebagai pencapaian mereka. Namun ketika program gagal, Departemen-lah yang menjadi kambing hitam.
Belum lagi rapat-rapat yang seakan tiada habisnya. Ada Rapat Kerja, Rapat Koordinasi yang mengundang DK Kabupaten/Kota meskipun tidak ada relevansi langsung kecuali pada Musyawarah Daerah lima tahunan, hingga Rapat Evaluasi. Semua ini memakan proporsi anggaran yang sangat besar. Setidaknya dua pertiga anggaran DKJT terserap untuk BPH, operasional, dan segala macam rapat tersebut. Departemen hanya kebagian sepertiga, dan itu pun seringkali masih dikurangi lagi untuk pos yang disebut “presidium pendamping”.
Hubungan dengan OPD induk, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pun sengaja dibuat berjarak. Kesannya agar terlihat kritis dan proaktif, tetapi pada kenyataannya kontraproduktif. Dulu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah mengembangkan Lokadata Budaya dan Daksa Budaya Jawa Timur. Di tengah proses itu, DKJT malah dengan penuh kebanggaan mengklaim telah membuat aplikasi pendataan seniman se-Jawa Timur. Bedanya, laman web aplikasi Dinas sampai sekarang masih dapat diakses, sedangkan aplikasi DKJT hilang begitu saja karena domainnya tidak diperpanjang. Banyak program DKJT dibuat seolah-olah ia adalah Disbudpar, padahal yang terjadi adalah kompetisi, bukan kolaborasi. Bahkan, dalam hubungan kelembagaan, mereka cenderung datang ke Dinas hanya ketika butuh anggaran untuk tahun berikutnya atau menjelang Musda. Sementara itu, untuk urusan pribadi, mereka bisa dengan santai menghadap pejabat instansi tersebut tanpa beban. Titel mereka panjang, gelar akademis mentereng, dan selalu mengaku memiliki jejaring luas. Tetapi untuk urusan membangun lembaga sendiri, rekam jejaknya justru memalukan.
Belajar dari Laku Kultural yang Membumi
Tidak semua pegiat budaya terjebak di dalam lingkaran rapat-rapat panjang, seremonial penuh foto, atau klaim sepihak atas kerja kolektif. Ada juga yang memilih jalan sunyi, membangun dari bawah, tanpa menunggu instruksi atau anggaran. Di titik inilah saya merasa perlu mengangkat nama Kang Totenk sebagai contoh laku kultural yang membumi. Ia datang dari bumi Parahyangan ke Surabaya, bukan dengan misi mengejar panggung prestisius, melainkan untuk membangun ruang bagi anak-anak dan warga sekitar lewat Sanggar Lidi. Kini ia memang kembali ke tanah kelahirannya, tetapi jejak yang ia tinggalkan di Surabaya adalah bukti bahwa pergerakan kultural sejati tidak lahir dari proposal, melainkan dari keberanian memulai.
Laku seperti ini jarang mendapat sorotan dari mereka yang sibuk berbicara “politik kebudayaan” di forum-forum resmi. Kang Totenk tidak pernah repot memikirkan warna jaket pengurus, siapa yang duduk di presidium, atau bagaimana caranya melobi OPD. Ia mengandalkan modal sosial: mengajar anak-anak membuat kerajinan, menghidupkan panggung sederhana untuk musik dan teater, dan mengundang siapa saja untuk terlibat tanpa memandang latar belakang. Tidak ada tarif masuk, tidak ada pembatas akses. Yang ada adalah kesediaan untuk berbagi ruang dan waktu.
Kerja-kerja Kang Totenk juga ditopang oleh keberadaan sebuah kafe sederhana di bagian selatan Kota Surabaya, Cakrawala Kata, yang hadir bak sinar rembulan di malam hari. Panggung publik yang rutin ia sediakan justru mampu mengisi ruang-ruang yang barangkali DKJT sendiri tidak sanggup menjangkaunya. Jangankan menjangkau ruang publik, meniru laporan tahunan Dewan Kesenian Jakarta atau memaparkan transparansi anggaran saja tidak bisa; lembaga ini sungguh sulit diaudit. Agaknya saya melihat realitas terbalik: karya-karya Kang Totenk, yang tidak lekang oleh zaman termasuk Paramesvari justru menjadi momen paripurna sebelum ia kembali hijrah ke Bandung.
Dengan pengalaman personal bertemu Kang Totenk di berbagai ruang publik, mulai dari Bang Bang Wetan, obrolan filsafat di Cakrawala Kata hingga dini hari, sampai akhirnya saya diundang mengisi diskusi Reboan yang disiarkan di YouTube, semuanya menjadi pengalaman luar biasa. Saya diterima sebagai individu yang dihargai gagasan dan pemikirannya secara setara. Forum-forum ini justru mengasah consciousness saya sebagai akademisi. Bukan debat kusir yang penuh caci-maki. Apalagi yang mengaku orang kebudayaan, tetapi tutur katanya tidak mencerminkan keluhuran, seperti “tak pancal lambemu” hanya karena kalah argumen.
Dari laku seperti inilah kita belajar bahwa kebudayaan tidak butuh banyak jargon. Ia butuh tempat untuk bersemi, dan itu hanya bisa terjadi jika ada orang-orang yang mau kotor tangannya, mau membagi waktunya, dan mau mendengar suara warga. Sanggar Lidi adalah contoh nyata bagaimana sebuah komunitas bisa menjadi wadah pembelajaran, pengarsipan, dan regenerasi, tanpa harus menggantungkan hidupnya pada “anggaran tahun berjalan”.
Yang membedakan laku ini dari program-program lembaga kaku adalah keberlanjutan. Tidak perlu menunggu Musda atau pengesahan anggaran, Sanggar Lidi tetap berjalan selama ada semangat gotong royong. Tidak ada rapat evaluasi yang menghabiskan dua pertiga anggaran, tapi ada diskusi kecil setiap malam yang membahas acara besok atau pekan depan. Tidak ada struktur presidium pendamping, tapi ada warga yang saling mendampingi satu sama lain. Inilah bentuk ekosistem budaya yang tidak mudah roboh, karena ia tumbuh dari akar yang benar-benar menancap di tanahnya sendiri.
Rasanya, seorang pribadi seperti Kang Totenk mampu mengalahkan wawasan seluruh personel sebuah lembaga yang kalau tampil di media congkak dengan gaya “KYY” alias, meminjam istilah orang Yogyakarta, koyo’ yok-yok’o. Sebaliknya, saya justru kerap merasakan tendensi konfrontatif dari sebagian personel DKJT, misalnya saat saya diundang mengisi acara pemerintahan lalu dinyinyiri karena dianggap pemerintah salah menunjuk representasi DKJT. Menurut mereka, kalau mengundang DKJT, ya harus mengundang BPH-nya. Padahal saya hadir karena kapasitas saya sebagai akademisi kampus, bukan sebagai perwakilan DKJT. Sejak saat itu, saya mantap berkata pada diri sendiri: gak pathek’en saya bawa-bawa nama DKJT lagi.
Refleksi: Belajar dari Pergerakan Kultural yang Luwes
Di luar pagar-pagar seremonial dan rapat-rapat formal, ada denyut kultural yang hidupnya ditopang oleh orang-orang biasa, dengan cara yang sederhana tetapi efektif. Pendidikan alternatif tumbuh di kelas-kelas seni, musik, teater, dan literasi berbasis komunitas. Di sana, anak-anak belajar bukan untuk mengejar sertifikat, melainkan untuk merawat imajinasi. Kamera seadanya dan arsip yang tersimpan di ponsel justru menjadi catatan sejarah yang paling jujur: merekam tradisi lokal sebelum tergilas proyek pembangunan. Di jalanan, advokasi ruang hidup muncul untuk menolak penggusuran dan komersialisasi berlebihan atas ruang publik yang sudah lama menjadi tempat berkumpul warga. Bukan sebatas mengadakan demonstrasi namun meminta diakomodasi dengan “uang tutup mulut” serta mengatasnamakan masyarakat kesenian Jawa Timur.
Mereka yang bergerak tanpa “plat merah” sering kali lebih lincah. Tidak ada beban laporan seremonial atau target kinerja yang mati rasa; kolaborasi bisa melompat lintas sektor tanpa menunggu tanda tangan pejabat; ide-ide tidak mati di meja rapat; dan respons terhadap isu aktual bisa dilakukan seketika entah itu bencana, perubahan kebijakan, atau momentum budaya tertentu.
Tentu saja, perjuangan ini tidak bebas dari tantangan. Sumber daya yang terbatas diatasi dengan gotong royong, crowdfunding, atau patronase warga. Minimnya dokumentasi dijawab dengan pelatihan sederhana agar warga sendiri yang jadi pengarsip. Ancaman kooptasi dihadapi dengan menjaga independensi finansial dan ideologis. Regenerasi dilakukan dengan melibatkan anak muda sejak awal, bukan hanya sebagai penonton atau penutup acara.
Pada akhirnya, perlawanan kultural membutuhkan ruang dan waktu yang dibangun bersama. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton atau pengkritik; setiap orang punya peran di lingkarannya masing-masing. Seperti yang pernah saya rasakan, forum-forum organik ini lebih mengasah kesadaran daripada debat kusir yang sering muncul di panggung resmi. Budaya terlalu besar untuk diserahkan pada rapat-rapat. Apakah DKJT mampu melakukannya? Sepertinya tidak. Suka jaim, seolah-olah para personil DKJT adalah pejabat publik di birokrasi yang bisa kenal siapa-siapa dan berbuat apa-apa karena kekuasaan dan kekuatannya mempengaruhi para pegiat, pelestari, aktivis, seniman, dan budayawan di akar rumput. Makanya saya memutuskan keluar.
Budaya tumbuh dari tangan yang bekerja, bukan dari tangan yang mengangkat palu sidang. Saya berorganisasi kebudayaan bukan untuk mencari uang, saya berorganisasi kebudayaan untuk menjaga nilai sebagai titipan anak-cucu. Sayonara, Kang!
Probo Darono Yakti
Doktor Ilmu Sosial, Pegiat Kebudayaan
Perintis Cultural Odyssey, Ketua BN SETALOKA

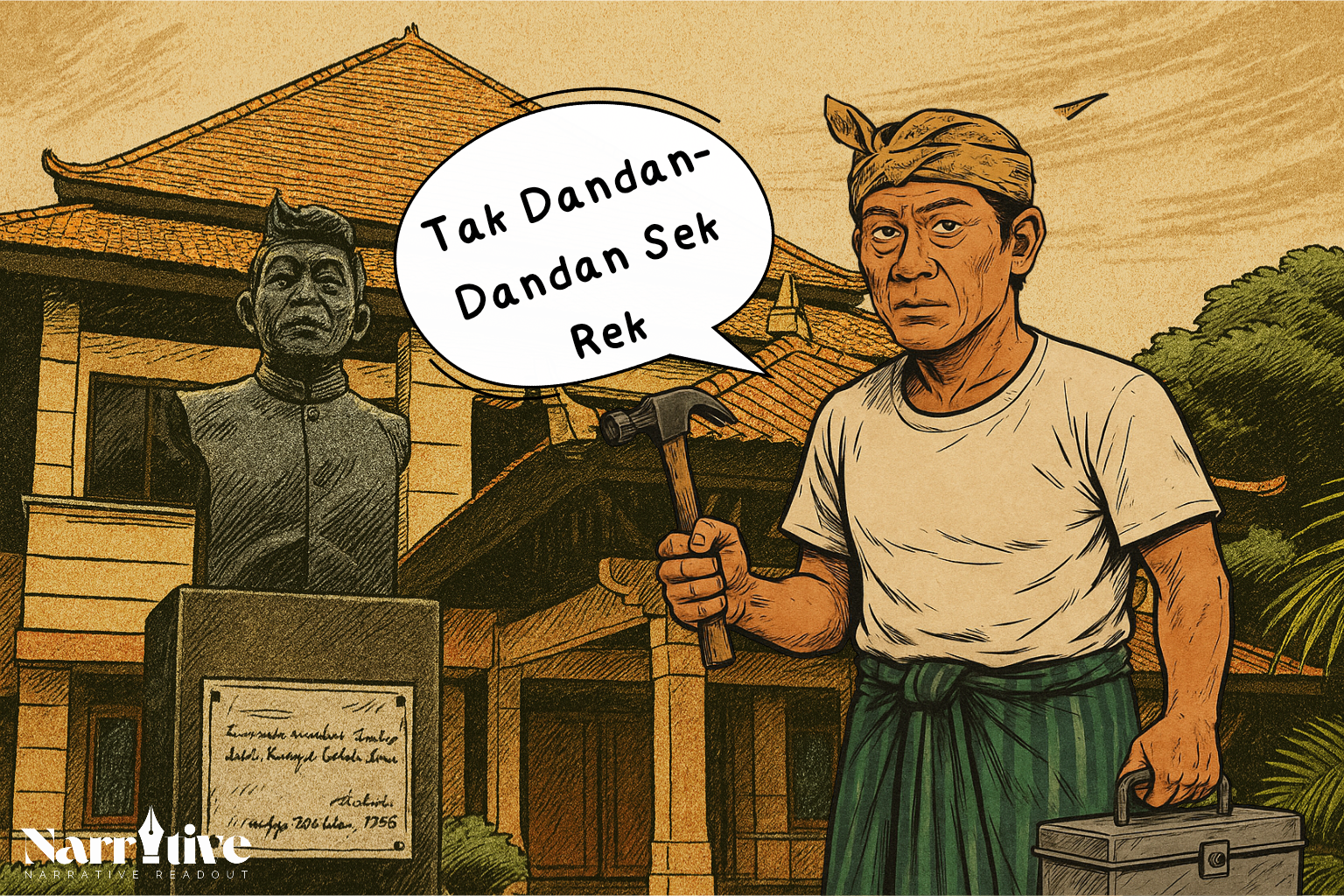


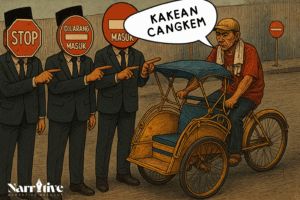
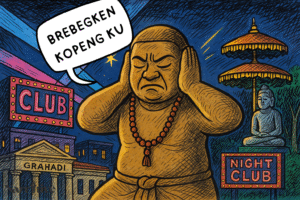
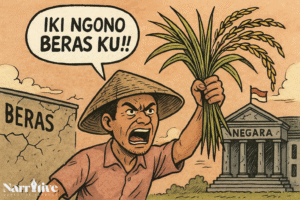
Be First to Comment